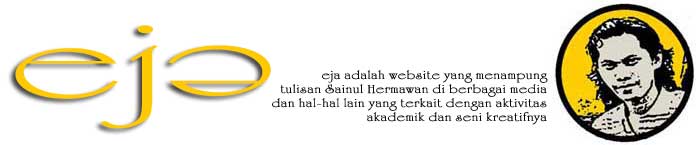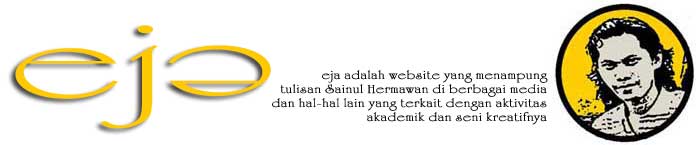Unsur
Fals Novel Palas
Oleh Sainul Hermawan
Palas nampaknya merupakan salah satu
puncak pencapain prestasi Aliman Syahrani dalam menekuni seni
kata jika kita membaca riwayat perjalanan karir kepenulisannya
di bagian akhir novel ini. Keberhasilan Syahrani menerbitkan
novel itu tidak hanya menaklukkan rekor proses kreatifnya
sendiri, melainkan juga meretas kebekuan jagat sastra
Kalimantan Selatan yang sejauh ini lebih dikenal sebagai
wilayah penulis puisi daripada sebagai wilayah penulis cerita
pendek (cerpen) dan novel. Meskipun setiap pekan kita dapat
menyaksikan kehadiran cerita bersambung di harian lokal,
tetapi yang mampu menerbitkannya menjadi buku dan disambut
banyak pembaca tampaknya masih jarang.
Tulisan
ini ingin menunjukkan bagaimana Syahrani mengelola kata
menjadi kekuatan yang menentukan “derajat kesastraan”
novelnya. Seluruh uraian didasarkan pada asumsi teoretis bahwa
sastrawan dan ilmuwan (dalam pengertian dikotomik yang
simplistik) menghadapi atau memperlakukan bahasa secara
berbeda. Ilmuwan cenderung memanfaatkan bahasa sebagai alat
untuk menyampaikan gagasan, tetapi sastrawan tidak
menghadapinya sebagai alat, tetapi sebagai tujuan. Dengan kata
lain, bahasa seorang ilmuwan atau politisi hanyalah input
dan medium, sedangkan bahasa sastrawan adalah sarana dan
sekaligus sasaran, input dan output. Sastrawan
tidak sekedar memakai bahasa, tetapi ia mengerjakan, mengolah,
menggarap, dan menciptakan bahasa (Lihat Ignas Kleden, Sastra
Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya, Pustaka
Utama Grafiti, 2004, hlm. 277).
Oleh
karena itu, sastrawan menghasilkan jenis pengetahuan yang
disebut pengetahuan puitis (poetic knowledge). Menurut
filsuf Perancis, Jacques Maritain dan Raissa Maritain (dalam
Kleden, 2004: 293), pengetahuan puitis lahir dari konnaturalitas
afektif yang cenderung menyatakan dirinya sendiri dalam
suatu karya atau pengetahuan yang lahir bukan dari “cara
mengetahui”, tetapi melalui insting dan kecenderungan,
melalui resonansi dalam diri subyek, yang bergerak menuju
penciptaan suatu karya. Dalam pengetahuan seperti ini peranan
kata-kata mental dan peranan keputusan dalam pengetahuan
spekulatif diambil alih oleh peranan obyek yang diciptakannya.
Dengan kata lain, pengetahuan puitis bersifat implisit karena
mediasinya berlangsung tidak melalui pikiran, tetapi melalui
perasaan dan pengalaman.
Jadi,
pengetahuan puitis yang lahir dari konnaturalitas afektif
jelas berbeda dengan pengetahuan konseptual yang lahir dari konnaturalitas
intelektual. Dalam konteks ini, karya sastra yang in
optima forma adalah karya sastra yang nol referensi dengan
makna yang tidak terbatas (Kleden, 2004: 296). Artinya, novel
yang berhasil tidak hanya melahirkan makna akibat adanya
hubungan antara teks dengan objek di luar teks, tetapi juga
harus mampu menghasilkan makna yang lahir dari teks itu
sendiri karena adanya hubungan-hubungan internal dalam teks (Kleden,
2004: 296-297).
Konnaturalitas
yang terdapat dalam Palas tampak berada dalam kerangka
intertekstualitas. Oleh karena itu, diskusi tentang lingkup
jaringan teksnya perlu disajikan untuk menjajaki kemungkinan
sikap penulis terhadap orisinalitas tekstual.
Konnaturalitas
intelektual teks sastra antara lain dapat dilihat pada adanya
fakta sejarah dalam teks itu yang dijadikan baik sebagai
sarana penceritaan maupun sasaran penceritaan. Kehadirannya
yang sangat kuat terutama dapat dilihat pada penggunaan
diksi-diksi yang tidak menyuguhkan “dunia tekstual” yang
unik. Dalam hal ini Palas dapat dibandingkan dengan
novel Saman, karya Ayu Utami (2000), dalam mengelola
komponen tersebut. Pembandingan ini penting dilakukan agar
konnaturalitas intelektual yang tidak perlu tidak terlalu
dominan hadir dalam teks sastra. Kadang-kadang konnaturaltas
intelektual juga diperlukan jika ia dijadikan sasaran penulis
sebagai sarana untuk melakukan sindiran terhadap realitas yang
ingin dirujuknya.
Di
sekitar halaman 35 terdapat uraian yang cukup panjang tentang
hutan yang lebih layak dipaparkan oleh penyuluh kehutanan
daripada novelis. Jika elemen ini dianggap sebagai unsur yang
harus ada, seharusnya bahasanya dipoles lebih indah, lebih
eliptis, lebih estetis, sehingga pembaca tidak terus-menerus
mengerutkan dahi karena merasa teks yang dihadapinya tidak
mampu membawanya ke dunia kata yang lebih baru.
Karya Syahrani nampak didominasi
oleh konnaturalitas intelektual karena bahasa di
dalamnya lebih sering dipakai dengan cara yang sangat terkesan
terlalu akademis. Indikasi bahasa yang terlalu akademis itu
dapat dibaca pada bagian tentang kebakaran hutan (hlm. 34-36),
pembukaan lahan (hlm. 37-41), rumah urang Bukit dan letak
geografis Loksado (hlm. 72-75), dan jihad Ibnu Hajar (hlm.
98-110). Bagian-bagian itu membuat novel ini tampak lebih
terkesan menjadi cacatan sejarah yang mengedepankan aspek konnaturalitas
intelektual yang mempersempit konotasi daripada aspek
konnaturalitas afektif yang memberi sedikit ruang bagi
denotasi. Di dalamnya terdapat unsur-unsur kalimat yang belum
dipadatkan. Jika keberadaannya dianggap sebagai pilihan gaya
pengarang, maka pilihan ini adalah pilihan yang sudah sangat
usang. Jiwa zaman pengguna bahasa senantiasa berubah. Karya
sastra baru harus mampu menangkap jiwa zaman yang baru itu
jika ia ingin disambut dengan baik.
Cobalah bandingkan dengan
bagaimana Saman (2000: 139-140) memperlakukan fakta
sejarah yang pada awalnya jelas merupakan fakta konnaturaliats
intelektual, tetapi kemudian diubahnya menjadi unsur
cerita yang bersifat konnaturalis afektif. Fakta
sejarah ini diangkat bukan hanya sebagai sesuatu yang
diketahui tetapi juga sesuatu yang dialami.
Syahrani dan Utami menggunakan
fakta sejarah secara berbeda. Dalam karya Syahrani sejarah
diletakkan sebagai unsur yang terpisah dari tokoh aku atau
sebagai sesuatu yang diketahui saja, tetapi dalam karya Utami
sejarah menjadi gaya bertutur untuk menjelaskan betapa aneh
dunia yang dihadapi tokoh aku dan keanehan itu pun bukan hanya
dialami oleh tokoh-tokoh sejarah dari tempat yang ingin
dikunjunginya, melainkan juga dialami oleh tokoh aku itu
sendiri. Dengan kata lain, kutipan fakta sejarah dalam karya
Syahrani cenderung berupa konnaturalitas intelektual,
sedangkan pada karya Utami cenderung berupa konnaturalitas
afektif.
Di samping itu, kesan adanya
banyak tekstur cut and clue dalam Palas (2004)
juga sangat terlihat ketika novel ini disejajarkan dengan
hipogram yang tampaknya memberikan banyak inspirasi, yaitu
novel Lingkar Tanah Lingkar Air (LTLA) karya
Ahmad Tohari (1999). Dalam kasus intertekstual linier, sebuah
hipogram biasanya terbit lebih dahulu. Proses saling
mengilhami antarkarya sastra adalah sesuatu yang wajar. LTLA
tampak mengilhami Palas dalam aspek pelataran dan
pengaluran cerita. Yang tidak wajar dan bukan menjadi
persoalan intertekstualitas adalah penjiplakan. Jika Palas
di bandingkan dengan LTLA ada kesan penjiplakan yang
sangat kental.
Beberapa tahun sebelum Palas
terbit, Ahmad Tohari menuliskan ekspresi sebagai berikut dalam
LTLA: Pagi hari musim kemarau di tengah belantara
hutan jati adalah kelengangan yang tetap terasa purba. Senyap
yang selalu membuat aku merasa terpencil dan asing. Padahal,
ibarat ikan, hutan jati dan semak belukar yang mengitarinya
sudah bertahun-tahun menjadi lubuk tempat aku dan
teman-temanku hidup dan bertahan…. (Tohari, 1999: 1).
Dalam Palas, ekspresi yang nyaris sama dapat ditemukan
bukan di halaman awal, melainkan di halaman tengah: Malam
hari di awal musim penghujan di desa terpencil kaki pegunungan
Meratus adalah kelengangan yang tetap terasa purba. Senyap
yang menyergap membuatku merasa terpencil dan asing. Padahal,
Loksado adalah kenangan. Loksado berarti tanah tumpah
kelahiran…. (Syahrani, 2004: 47).
Memang tidak seluruh ekspresi Palas
berupa transfer dari karya sastra lain seperti kutipan di atas.
Tetapi sekecil apapun kehadiran ekspresi yang telah
diungkapkan penulis lain dalam Palas akan ikut
memperkuat kesan intertualitas negatif yang dapat mengurangi
orisinalitas tekstualnya, kecuali penulis mengakui seperti
kebiasaan Seno Gumira Adjidarma yang dengan akurat memberikan
catatan kaki pada setiap ekspresi yang dengan sengaja ia ambil
dari karya sastra lain. Seno Gumira Adjidarma mencontohkan
bahwa pengambilan elemen karya sastra lain terhadap karyanya
bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan asalkan ada pengakuan
sadar bahwa unsur-unsur pinjaman itu bukan ekspresi
orisinalnya. Dalam cerpen Partai Pengemis, misalnya,
Seno menulis satu paragraf yang merupakan mozaik dari beragam
teks (Lihat dalam kumpulan cerpen Iblis Tidak Pernah Mati.
Galang Press, 1999, hlm. 83).
Seno
memberikan catatan kaki bahwa cerpen Partai Pengemis
karyanya adalah hasil adaptasi dari komik Walet Merah
karya Hans Djaladara. Ekspresi inilah nanah, yang meleleh
dari luka, sambil berjalan kau usap juga tidak diakui
sebagai ekspresinya, melainkan dipinjam dari sajak Peminta-minta
karya Chairil Anwar, dan ekspresi puitis lalat terbang dari
nanah ke nanah dipinjam dari sajak Lalat karya
Sutardji Calzoum Bachri (1981: 107).
Bahkan
ada bagian dialog dalam cerpen Para Pengemis yang
diakui Seno sebagai kutipan yang persis aslinya dan dia hanya
memperbarui ejaannya. Sehingga bagian yang lain yang tidak
diberi keterangan adalah asli kreasi orisinil yang mungkin
tetap berada dalam kerangka adaptasi atau sama sekali lepas
darinya. Dengan cara inilah Seno mempermainkan relativitas
orisinalitas.
Pengakuannya
di setiap catatan kaki cerpennya adalah kesadaran intelektual
terhadap keberadaan intertektualitas teks sehingga yang dia
kejar bukan lagi orisinal komponen atau apa yang menyusun
baris-baris prosanya, melainkan bagaimana dia meramu
unsur-unsur itu menjadi karya baru yang segar: komik dan sajak
lebur menjadi cerpen. Meskipun demikian, dia tidak mau
terjebak dalam konnaturalitas intelektual yang berlebihan.
Karenanya dia melakukan adaptasi dan renarasi, bukan imitasi
linier. Sedikit hal yang semacam ini dapat ditemukan dalam Palas.
Bahasa karya sastra adalah adalah
gerbang utama memasuki dunia imajianasi yang hendak ditawarkan
oleh penulis karya fiksional itu. Aspek ini pun sering
dijadikan indikator pembeda antara karya sastra dan karya non-sastra.
Oleh karena itu, aspek ini dapat dipakai sebagai salah satu
ukuran sukses dan tidaknya sebuah prosa. Bahasa prosa yang
berhasil cenderung mengurangi beban referensial bahasa yang
digunakannya karena ia berangkat dari pengetahuan dasar bahwa
hubungan antara sastra dan realitas yang diacunya sebaiknya
bersifat simbolik. Dalam konteks ini, novel Palas penuh
dengan beban yang pertama sehingga medan konotasi bahasa yang
digunakannya menjadi sempit dan asosiasi imajinatif pembaca
menjadi kurang berkembang.
Melalui tulisan ini penulis Palas
dapat melihat bagaimana serapan dari teks lain dapat
dimainkannya menjadi bangunan tekstual yang berhasil. Serapan
yang memang bukan kreasi orisinal sendiri sebaiknya diakui
sebagai bentuk pertanggungjawaban berkesenian. Jika tidak
ingin demikian, unsur-unsur serapan itu harus dirombak total
menjadi ekspresi yang sepenuhnya berbeda karena seniman kata
memang berlomba untuk menciptakan kata, sebab kata-kata tidak
dihadapinya hanya sebagai sarana melainkan sekaligus sebagai
sasaran.
Banjarmasin,
14 Maret 2005
Radar
Banjarmasin, Minggu 3 April 2005
URL:
http://www.oocities.org/ejabudaya/esai_unsur_fals.html |