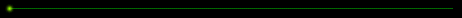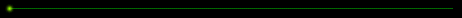|
AGAMA / PANJI NO. 26 TAHUN III. 13 OKTOBER 1999
Agar Tidak Anarkis
Syariah Islam: Pemberlakuan syariah Islam di Aceh mulai dimasyarakatkan menyusul pengesahan UU Keistimewaan Aceh. Tapi, masih saja muncul perdebatan.
“Kawasan Wajib Jilbab”, demikian bunyi spanduk besar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh. Di sekitar masjid tampak para satpam berjilbab menjaga pintu masuk. Bagi para wanita yang mengunjungi masjid tanpa mengenakan jilbab atau kerudung, niscaya mereka dilarang masuk oleh satpam tersebut--sekalipun mereka hendak salat.
Begitulah antara lain suasana di sekitar Masjid Baiturrahman Banda Aceh belakang ini, menyusul pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Aceh dua pekan lalu. Tak cuma itu, seperti terlihat di televisi, ibu-ibu di sana juga berpatroli dengan sapu setiap Jumat dan memukul kaum lelaki dewasa yang enak-enak nongkrong tak mau salat Jumat. Masyarakat pun makin gencar memberantas praktek maksiat dengan mengampanyekan Gerakan Anti-Maksiat.
Busana penutup aurat wanita tampak juga dikenakan masyarakat umum. Para wanita di Aceh mengaku malu kalau keluar rumah tanpa kerudung. Sekarang ini, menurut Ketua Umum MUI Aceh Tengku Muslim Ibrahim, berkerudung sedang menjadi tren muslimah Aceh. Begitu fenomenalnya sehingga para pedagang kerudung mulai kehabisan stok.
Memang, sejak disahkannya UU tersebut, masyarakat Aceh tampak menyambut dengan gembira, bahkan langsung menerapkan pemberlakuan syariah Islam. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur implementasi pelaksanaan UU itu belum ada. Tapi, begitulah antusiasme masyarakat Aceh. Menurut Rektor IAIN Ar-Raniri Aceh Safwan Idris, pemberlakuan syariah Islam di sini sudah ditunggu-tunggu masyarakat.
Membudaya. Safwan menegaskan, pemberlakuan syariah Islam pernah terjadi di Aceh selama hampir 100 tahun,yakni pada zaman kesultanan. Karena itu kehadiran UU Keistimewaan Aceh bisa menghidupkan kembali budaya yang bersumber dari syariah Islam itu.
Jika seorang pencuri tertangkap, misalnya, maka ia tak perlu diserahkan kepada polisi. Cukup kepada tengku. Dicontohkan, belum lama ini ada seorang pencuri buah pala tertangkap. Dia kemudian dikurung di surau dan semua orang melihatnya. Di dadanya digantung tulisan “Saya pencuri pala”. Kemudian dia diarak berkeliling. Sanksi seperti ini bisa mendidik si pelaku dan membuatnya jera karena malu. “Budaya malu harus kembali dikedepankan. Karena selama ini orang berani mencuri, korupsi, karena tidak tahu malu,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Tengku Muslim. Menurut dia, kalau ada masalah di tingkat desa diselesaikan secara hukum adat. Jika ada orang tidak salat berjamaah, misalnya, maka sanksi adat diberlakukan: orang-orang tak perlu datang kalau dia mengadakan kenduri. Tapi keputusan ini tentu setelah dibahas melalui tuha lapan dan tuha ampat--semacam DPR yang ada di tingkat desa. “Kalau tak bisa diselesaikan juga,” kata Muslim, “baru dilanjutkan ke pengadilan agama,” tegasnya.
Bagaimana dengan mereka yang bukan Islam? Menurut Safwan, orang-orang non-Islam tidak termasuk dalam pemberlakuan syariah. Umat Islam tidak akan memaksa mereka salat. Semua berjalan apa adanya. Mereka bebas menjalankan ajaran agamanya. Selama tidak mengganggu hak dan ketenteraman umat Islam, ada jaminan keamanan bagi nonmuslim. Jika mereka memelihara babi, Safwan mencontohkan, jangan sampai berkeliaran di lingkungan umat Islam.
Anarkis. Menanggapi pemberlakuan syariah Islam di Aceh, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Fathurrahman Djamil menegaskan, pada dasarnya pemberlakuan itu wajib. Namun dalam pengertian fikih, perlu dilihat mana yang cocok pada masyarakat yang bersangkutan dan mana yang tidak cocok untuk masyarakat lain. Soal pemukulan ibu-ibu terhadap lelaki dewasa yang tidak salat di sana, termasuk salat Jumat, misalnya, ia melihatnya perlu ditinjau kembali karena tidak ada dalam tuntunan Al-Quran atau hadis.
Memang ada hadis Nabi yang berbunyi, “Barangsiapa meninggalkan salat dengan sengaja, ia telah kafir.” Namun menurut Fathurrahman, berdasarkan pendapat Imam Syafi`i, kafir di situ bukan lawan dari mukmin, melainkan lawan dari mensyukuri nikmat. Sehingga, meninggalkan salat tak masuk kategori kafir walaupun disengaja--apalagi tak sengaja. “Jadi sanksi fisik di Aceh itu sebaiknya ditinjau kembali. Tidak ada hukuman bunuh atau rajam bagi yang tak salat. Yang ada sanksi ukhrawi,” tegasnya.
Begitu pula dalam soal jilbab atau kerudung. Menurut Fathurrahman, kita harus lebih dulu mengerti posisi hukum Islamnya. Mula-mula dikaji apakah memang bagi yang tak berjilbab ada sanksi fisik atau sekadar sanksi moral. Sebab hikmah penetapan jilbab adalah agar tak terjadi perzinaan. Dan jilbab menurut dia hanya salah satu bentuk sarana penutup aurat sehingga tidak mutlak semua muslimah mengenakan penutup aurat dalam bentuk jilbab. Bisa bentuk lain, asal menutup aurat.
Lebih jauh Fathurrahman mengusulkan agar dalam menentukan hukuman-hukuman tertentu dalam pemberlakuan syariah di Aceh perlu dibentuk lembaga resmi yang menetapkan aturan yang tetap berpegang pada ketentuan Islam--semacam lembaga muhtasib atau wilayatul hisbah di Arab Saudi. Tugas lembaga ini adalah amar makruf nahi munkar.
Segala tindakan apa pun yang keras dalam amar makruf nahi munkar sudah dikonsentrasikan ke lembaga agar tercipta ketertiban. “Jadi tidak setiap orang bebas melakukan amar makruf nahi munkar secara beramai-ramai. Kalau ini yang terjadi, keadaan bisa anarkis. Kalau ada yang sentimen pada seseorang, dia bisa saja melakukan yang tidak-tidak dengan dalih amar makruf nahi munkar,” tutur Fathurrahman.
Politik darurat. Dalam perspektif yang berbeda, Rektor IAIN Jakarta Azyumardi Azra melihat bahwa pemberlakuan syariah Islam di Aceh merupakan langkah politik darurat pemerintah untuk menyelamatkan Aceh ke dalam pangkuan Republik. Dengan penerapan syariah itu diharapkan akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh.
Lebih jauh Azyumardi melihat, secara sosiologis, penerapan syariah di Aceh sangat kompleks. Kompleksitas pertama terletak pada realita sosiologis masyarakat muslim Aceh sendiri. Menurut dia, masyarakat Aceh sekarang jauh berbeda dengan masyarakat Aceh pada masa kesultanan dulu. Diversifikasi dan diferensiasi masyarakat Aceh, terutama sebagai hasil dari perubahan sosial sejak 1970-an, membuat pandangan dunia berbagai lapisan sosiologis masyarakat Aceh tentang Islam juga berbeda-beda. “Lebih tegas lagi, terdapat perbedaan pemahaman tentang syariah, khususnya dalam posisinya sebagai hukum positif dalam sistem hukum Daerah Istimewa Aceh nantinya,” ujarnya.
Kerumitan pada tingkat sosiologis ini, lanjut Azyumardi, bergandengan dengan realita institusional muslim di Aceh yang harus diakui mengalami kemerosotan signifikan sejak pascakemerdekaan. Lembaga-lembaga Islam, bukan hanya mahkamah syariah, melainkan juga lembaga-lembaga lain seperti meunasah, dayah, dan rangkang, yang berfungsi mereproduksi fungsionaris agama--khususnya hakim dan qadhi--praktis mengalami disfungsi. Nah, Azyumardi melihat bahwa kelembagaan yang masih efektif menjalankan fungsi ini agaknya tinggal IAIN Ar-Raniri. Namun, perlu dicatat, posisi IAIN vis-a-vis masyarakat sedikit berbeda dibandingkan dengan dayah dan rangkang tadi.
Kerumitan lain, menurut Azyumardi, justru terletak pada kenyataan adanya konflik antara hukum syariah dan hukum nasional dalam segi-segi tertentu. Harus diakui, hukum positif nasional banyak bersumber dari hukum Belanda, yang sampai sekarang belum banyak disesuaikan dan diubah. Akibatnya, terdapat ketentuan hukum yang tidak kompatibel dengan syariah atau persisnya hudud. “Kenyataan ini,” kata Azyumardi, “perlu diantisipasi dan dipecahkan sehingga hukum syariah yang akan diterapkan dapat berfungsi secara efektif.”
Yang tak kurang krusialnya adalah kerumitan dalam sistem hukum syariah itu sendiri. Menurut Azyumardi, dewasa ini terdapat keinginan kuat di banyak kalangan masyarakat muslim seperti di Aceh untuk menerapkan hukum Islam sebagai pengganti hukum nasional yang bersumber dari Barat. Tapi, aspirasi ini tidak disertai dengan prakondisi penting, yaitu bagaimana membuat syariah lebih fleksibel sehingga dapat menampung apa yang disebut Bassam Tibi sebagai akomodasi kultural dari perubahan (cultural accommodation of change). “Tanpa prasyarat seperti itu, maka syariah sangat mungkin oleh pihak tertentu--termasuk kalangan muslim sendiri--hanya dianggap sebagai residu dari masa pra-industri,” tegasnya.
Akhirnya Azyumardi menegaskan, sebagaimana disarankan Tibi, penerapan hukum Islam memerlukan rekonstruksi syariah. Tanpa rekonstruksi itu, maka seruan untuk penerapan hukum Islam merupakan respons kultural defensif belaka terhadap perubahan struktural yang terus terjadi dalam masyarakat.
Nasrullah Ali-Fauzi
|