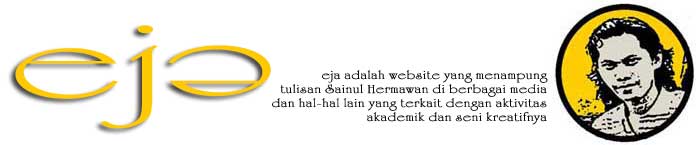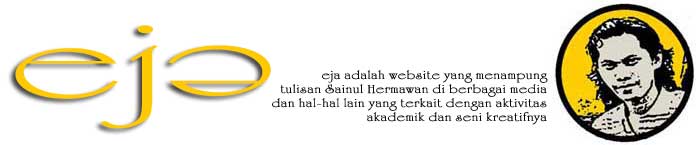Baby
Blues
Cerpen Sainul Hermawan
Akhirnya
Angga kembali lagi ke kota bunga tanpa sebuah rencana mau apa di
sana. Keinginanya saat ini hanya satu: menjauhi gaduh yang
menuduhnya sakit jiwa. Sendiri sejenak dia berdiri di ruang tamu
kontrakannya. Ruang yang mulai kosong dari deretan buku. Ruang
yang telah mengantar keempat kakaknya dan adik bungsunya menjadi
sarjana. Sarjana. Bibirnya berat melafalkannya. Sarjana. Dia
mengulanginya lalu berfikir: mengapa tak mudah kuraih? Ah,
sarjana.
Dia
kemudian mengabaikan kata itu, masuk kamar setelah menyalakan TV
hitam putih di saluran tak beriklan dan penuh bintik-bintik
elektron. Suaranya tak cukup mampu mengusir kata sarjana di
kepalanya, entah di mana. Dia selalu perlu menyetel radio untuk
menambah meriah suasana. Barulah dia memutar roda dengan tambang
penarik timba, sampai tercipta paduan suara TV, radio, dan
kerekan sumur. Musik latar untuk setiap galau batinnya. Kadang
dia sampai lupa kalau air bak mandi itu meluap. Di rumah ini
kerekan, tambang, dan timba abadi. Mereka tak perlu reformasi.
Orkestrasi
bunyi-bunyi itu membuatnya tak mendengar dengan jelas ketukan
pintu seorang tamu. Seorang kawan yang sudah paham kalau harus
menunggu dia menyelesaikan mandinya, dan mencegatnya pada saat
dia melintas menuju kamarnya.
“Assalamu’alaikum,….”.
“Kum
salam. Eh, Mir masuk. Nggak dikunci, kok,” dia langsung masuk
kamar. Amir tak berhasil membuka pintu sampai dia datang
membukanya.
“Masuk.
Sudah lama di sini?”.
“Aku
nggak pulang. Teman kosan belum ada yang balik. Jadi aku tak punya teman ngobrol. Untung kamu datang.”.
“Aku
baru saja tiba. Gimana, nanti malam nginap sini, ya? Toh, di
kosan kamu sendirian.”.
“Gantianlah,
sekali-kali kamu temani aku di kosan. Masa aku terus yang
bermalam di sini.”.
“Aku
bisa, tapi tidak untuk malam ini.”.
Amir
sepakat. Seperti biasa, dia lebih suka tidur di ruang tamu,
sambil memelototi TV sampai acara paling akhir. Angga, karena
lelah, telah pulas lebih awal. Sampai jam satu dini hari, Amir
susah tidur. Kantuknya tak jadi datang ketika TV itu padam
seketika. Sayup-sayup dari lantai beralas karpet yang dia tiduri,
terdengar tangis bayi. Amir berusaha mengusir suara itu dengan
nalar: ah, paling-paling bayi tetangga. Udara malam memang
gampang mengantarkan suara tetangga yang jauh sekalipun.
Tapi
dia masih belum bisa lelap sempurna. Ketika kantuk menyelinap ke
kelopak matanya, dia melihat darah. Darah segar menggenang di
hadapannya. Pelan-pelan bergerak ke arahnya, seakan ingin
menenggelamkan Amir. Hah!
Keringat
tak pantas membanjiri sekujur tubuh Amir, sebab malam di kota
ini tak pernah panas. Dia terbelalak. Angga sudah duduk di
depannya, nonton berita TV paling pagi. Amir masih malas duduk
dan tetap berbaring.
“Ngga,”
katanya. Yang dipanggil cuma mengernyitkan dahi dan bertanya
dengan kata apa.
“Kamu
yang nyalakan TV?”.
“Kamu
lupa matikan. TV-nya hidup semaleman.
Suaranya sampai ke kamarku. Makanya aku bangun lebih pagi.”.
Angga
cuma bengong. Dia bercerita tentang darah. Keesokan malamnya
Amir tidak mau lagi diajak Angga bermalam dikontrakannya. Jam
dua dini hari, tangis bayi itu terdengar di telinga Angga. Dia
mencoba menyikapinya seperti Amir. Tetapi gagal setelah darah
yang sama jatuh setetes, dua tetes, sampai seperti gerimis dari
langit-langit kamarnya. Akhirnya dia bangun dan melihat jam
weker di pojok kamar: jam dua?
Bagi
Angga mimpi buruk tengah malam bukan mimpi main-main. Dia bangun
untuk ber-wudhu lalu sholat. Guru spiritualnya seakan hadir
setelah hitungan zikirnya mencapai hitungan seratus, lalu lenyap
bersama suara: bacalah dinding yang tak pernah bicara ….
bacalah dinding …. tak pernah bicara. Angga berhenti membaca
mantra. Tangis bayi terdengar lagi. Tak jelas dari arah mana,
tapi seperti dekat sekali. Rambut-rambut halus di lehernya mulai
berdiri. Perasaan takut mau menahan langkahnya untuk mencari
sumber suara itu. Tapi bukan kebiasaan Angga berhenti sebelum
ketemu dengan yang dicari.
Dia
masuk kamar Anggi, kamar adiknya. Adik yang mendahuluinya
menjadi sarjana. Tangis bayi itu berhenti. Tak terdengar lagi.
Tapi tangis itu terdengar lagi jika Angga berdiri di ruang tamu
dan kamarnya. Bulu kaki Angga ikut-ikutan berdiri. Tangis bayi
itu nyata. Dia bergumam sendiri. Tangis bayi itu pergi bersama
adzan subuh.
*
* *
Pagi-pagi
Angga pergi ke wartel, sebelum pulsa bertarif ganda. Dia
menghubungi rumahnya di seberang pelabuhan Tanjung Perak.
Maksudnya ingin bicara dengan adiknya, tapi sial, yang menyambut
bapaknya. Satu-satunya suara yang menurutnya paling bising di
dunia. Sebelum gagang itu pindah ke tangan Anggi, Angga menerima
serangkaian pertanyaan interogasi bapaknya yang selalu
dijawabnya dengan kebohongan: sudah mengisi KRS, SPP-nya sudah
dibayar, sudah daftar ulang, kapan ikut KKN, dan lain-lain.
Jawabannya selalu mantap. Tapi bohong!
“Ada
apa Ngga?” suara Anggi menyapa.
“Malam
ini aku diganggu, Nggi.”.
Angga
menceritakan kejadian dini hari ini dengan rinci. Adiknya Cuma
diam. Di ujung percakapan dia menjanjikan jawaban.
“Aku
nggak bisa cerita sekarang, Ngga. Minggu aku ke sana untuk
melegalisir ijasah. Nanti aku ceritakan semuanya.”.
Telepon
putus. Seperti diputus gangguan yang sering dibuat-buat Telkom.
Padahal Angga menyengajanya. Dia tak kuasa menahan amarah,
karena selama Anggi sekontrakan dengannya diam-diam menyimpan
rahasia. Rahasia misteri ngeri: tangis bayi.
Setiap
tengah malam selama menunggu Anggi datang, tangis itu semakin
akrab di telinga Angga. Dia tak lagi ingin mencari sumber suara
itu, meskipun dia tahu suara itu ada di rumah ini. Sambil
berbaring Angga selalu berdoa agar arwah bayi itu damai di
alamnya. Tapi, suara itu terus hadir tepat waktu. Sampai-sampai
Angga bertanya pada dinding yang tak mau bicara, apa yang
diinginkan suara itu darinya.
“Bicaralah
dengan bayi itu!”.
Angga
terperanjat, bangkit dari dipan kayu, menjauhi dinding di
sampingnya.
“Kau,
dinding, kau yang ngomong itu? Sungguh?” Mata Angga melebar.
Keringat dingin mulai terasa mengalir di lehernya.
“Ajaklah
bayi itu bicara!”.
Tidak.
Tidak …. Ti…. Dia keluar, tak peduli jam dua dini hari.
Pergi ke kosan Amir. Di sana mereka membagi cerita yang sama,
tangis bayi dan darah. Angga tak berani lagi tidur sendiri di
rumah kontrakannya. Secarik pesan ditempatkan agak tinggi di
pintu utama: “Untuk sementara aku ngungsi ke kosan Amir….
Angga.”
Pada
malam yang dijanjikan, Anggi tiba. Angga kembali berani kembali,
setelah dapat kabar dari Amir kalau adiknya menunggu di depan
pintu kontrakan. Anggi tak diberi kesempatan untuk cuci muka
dulu. Dia langsung didaulat membuka rahasia itu. Si bungsu
sedikit bingung harus mulai dari mana. Dia memulai kisah dengan
kata maaf.
*
* *
Di
ruang tamu ini, di mana sekarang kakak beradik itu berbincang,
Ferda dan Anton, setahun tahun yang lalu, mulai saling mengenal.
Mereka sama-sama lupa kapan tepatnya. Ferda teman Anggi, Anton
teman Angga. Tak lebih dari seminggu mereka telah menyatakan
sebagai sepasang kekasih. Sangat instan. Seperti proses memasak
mie kesukaan mereka.
“Kak
Angga masih ingat kan, kepada siapa kita nitip kunci kontrakan kita ketika kita harus sama-sama pulang karena
penyakit bapak kambuh?”
Yang
ditanya cuma diam. Cuma memberi tanda dengan sedikit bahasa
tubuhnya, dari raut wajahnya, untuk melanjutkan cerita.
Kesempatan itu mereka pakai dengan baik. Mereka menyewa VCD dan
nonton film biru berdua di kamar Anggi. Ferda tak tahan ingin
mencoba satu pose. Setelah itu malam meremang. Mereka tak ingat
apa-apa lagi dan entah telah berapa kali pose demi pose dicoba.
Dan tidak selalu di kamar Anggi. Kota bunga memberi lahan subur
bagi benih-benih untuk bersemi. Bahkan pada musim kemarau
sekalipun.
Badai
kecemasan berguncang dari rahin Ferda. Tiga bulan sudah dia
telat mendapat giliran musim gugur kesuburan. Naluri keibuan
pelan-pelan tumbuh. Tapi Anton berusaha meyakinkan betapa
susahnya masa depan dengan satu anak, sementara negeri ini penuh
ketakpastian. Seperti musim yang serba ekstrem.
Ferda
lunglai. Dia terbius. Dia mencari segala jenis bius untuk
benihnya.
Tak
lama kemudian, dia datang dengan wajah bimbang. Akhirnya dia
tahu, Anton sebenarnya tidak mencintainya. Dia tidak pernah
kembali. Dia memilih berhenti kuliah. Kedua orang tuanya juga
kebingungan. Entah dia melancong ke mana.
Pada
hari yang sama, pada posisi matahari yang lebih tinggi, sungguh
aku kaget. Dia setengah berteriak memanggil namaku dari kamar
mandi.
“Anggi
…. Nggi …. To… tolong, a… apa ini….”
Kukira
sejuta kecoak sedang mengerubungi kakinya. Kuminta dia buka
pintu, tapi tak dilakukannya segera. Dia terus menjerit seperti
anak kecil minta digendong. Untung aku ingat. Grendel pintu
kamar mandi itu tidak terlalu baik lagi mengunci pintu. Dengan
dobrakan pelan saja pintu itu terkuak dan,… Aku tak kuat
melihat segumpal darah berayun-ayun di bawah kelaminnya.
Aku
tak segera melakukan apa-apa sampai dia meminta dengan agak
membentak untuk menariknya. Aku tidak bisa. Dengan was-was
kulakukan juga. Dan.…
“Kenapa
kamu nangis?” tegur
Angga sinis.
“Aku
tidak bersalah kan, kak?”.
Yang
ditanya cuma diam. Sebentar-sebentar mengalihkan pandangan ke
arah lain. Seperti membuang gelagat amarah yang tertahan.
Gumpalan
itu tak mampu kutahan dengan segala kekuatan tangan
kiriku. Ia begitu licin. Lalu,… plung
…. dlep …. Ia seperti lari terburu-buru masuk lobang kakus. Kami tak
mampu mengejarnya. Ferda menyiramnya dengan bertimba-timba air,
sambil menangis kupeluk dia. Dia terus terisak memintaku
merahasiakan semua itu kepada siapa saja. Akhirnya aku juga tak
bisa. Ya, rahasia itu telah berbicara sendiri dalam mimpi kak
Angga.
Angga
pergi setelah cerita adiknya usai. Dia pergi ke wartel. Dia tahu
di mana Ferda berada. Sepuluh digit angka dalam beberapa detik
menghubungkannya dengan suara yang sangat dikenalnya.
“Apa
kabar, Fer?”
“Eh,
Angga. Hampir setahun ya kita pisah. Tapi suara kita sama-sama
belum berubah. Gimana kabar Anggi? Kamu lagi nelpon sama dia,
kan? Kasih dong sebentar, aku ingin dengar suaranya.”
“Dia
cuma titip salam buat kamu.”
Sesaat
ada jeda. Seperti sama-sama sedang mencari kata-kata: bagaimana
percakapan selanjutnya?
“Pasti
ada yang penting, nih?”.
Angga
masih diam. Deru angin elektron dalam kabel-kabel gagang telepon
di telinganya menderu bagai badai.
“Angga,
kamu masih di situ?”.
“I…
I… ya… aku masih.…”
“Ada
apa?”
“Aku
cuma ingin tanya, em …?”
Ferda
memberikan kesempatan. Dia mencoba tidak bertanya.
“Aku…
eh… begini: jika kelak kami dikarunia anak, ingin kamu beri
nama apa?”
“Aku
belum tahu”.
“Coba
bayangkan, sekarang, saat ini, sekali lagi sekarang, dalam
pikiranmu, kamu sedang membayangkan anak perempuan atau
laki-laki?”
“Sebentar,
ya?”
“Jangan
lama-lama.”
“Perempuan!”.
“Aku
punya tiga opsi. Coba kamu pilih nama mana yang paling kamu suka:
Baby Sylvia, Baby Blues, atau Baby Jean.”
“Aku
suka yang nge-blues!”
Ferda
tertawa. Angga tersenyum. Lalu Angga menutup telepon itu dengan
kata yang kelak membuat Ferda kadang-kadang menangis tanpa
alasan yang dapat diketahui banyak orang.
“Dah,
mama Baby Blues. Selamat bersenang-senang!”
Ferda
kaget. Kenapa Angga memanggilnya mama. Dia yakin rahasianya
telah terungkap. Dia minta kejelasan pada Anggi. Anggi semakin
heran dan mengiranya ketika dia memanggil sebuah nama sebelum
dia menutup telepon: Baby Blues … oh … Baby Blues, maafkan
mamamu.
Sejak
itu tangis bayi tak terdengar lagi. Kakus kontrakan itu telah
menjadi kubur. Hanya orang-orang yang tak pernah tahu kisahnya
yang berani berak dan kencing di atasnya.
*
* *
Angga
pindah dari rumah itu. Dia memilih kos di tempat Amir. Suatu
malam dia mencret setelah jor-joran menyantap jagung di Batu
dari petang sampai jam sembilan malam. Mencret tengah malam
memang melegakan. Tak ada perasaan was-was akan kemungkinan
tersebarnya rahasia aroma kotoran kita. Tetapi tidak untuk malam
itu. Angga teriak histeris ketika pantatnya terasa disentuh
tangan bayi yang dingin. Sembilan belas temannya terbangun.
Mereka mengedor-gedor pintu, tapi Angga tak mau membukanya.
Ketika ditanya ada apa, Angga cuma minta maaf kalau cirit-cit
mencretnya terlalu keras.
Karangwuni,
Jogja, 11 Maret 2002
|