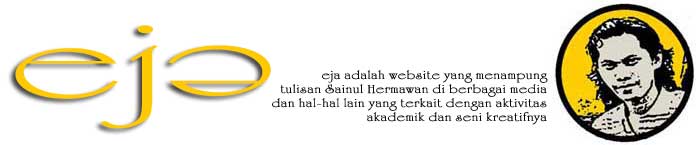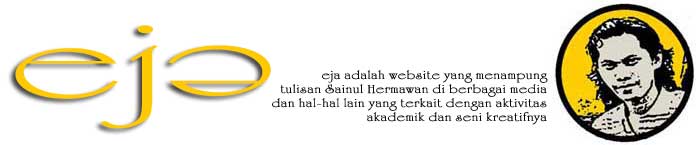Mata
untuk Mama
Cerpen
Sainul Hermawan
Waktu
itu mataku hanya mampu menangkap garis dan warna, belum makna.
Aku lihat mamaku berlari menyeberang jalan, lalu hilang
bersama bis yang melintas. Entah ke mana. Kemudian aku tahu,
dia tak berasamaku beberapa lama. Aku tahu ada bermacam-macam
perempuan mengantikannya. Aku tak ingat lagi ada berapa, juga
nama-nama mereka.
Tatkala
kutanya nenek, ibu papaku, dia bilang kalau mamaku mencari
Arjuna yang akan mengajarinya bercinta. Mengapa tak belajar ke
papa saja? Kata nenek, papa tak perlu perempuan pemuja
keperkasaan, pujangga picisan, atau tikus bagi rumah tangga
orang lain. Dulu aku masih belum tahu bahwa rumah tangga itu
bukan rumah-rumah bertangga dalam gambar-gambar yang sering
kumainkan bersama kawan, menunggu mama pulang. Tapi dia
benar-benar menghilang.
“Mengapa
kamu begitu senang aku mengulang-ulang cerita itu?”
“Karena
kamulah yang punya cerita seperti itu.”
Perempuan
itu lalu bergegas membayar apa saja yang baru saja mereka
makan bersama.
“Terima
kasih buat ceritamu. Semoga kamu tak bosan untuk
menceritakannya besok-besok. Siapa tahu kamu punya garis
cerita baru. Tuh, lihat teman-temanmu berburu pintu pagar
sekolahmu yang mau ditutup. Jam istirahatmu sudah habis.”
“Terima
kasih, Bu.”
Siapa
dia?
Perempuan
berpakaian pejabat. Cantik. Baik hati karena dia selalu
membayar makananku saat aku jajan di warung itu dan kebetulan
dia juga makan di situ. Sekolahku dan kantornya hanya berjarak
sekitar lima bangunan di sisi jalan yang sama. Anehnya, hanya
dia yang tampak berani jajan di warung kelas siswa SMP.
Anehnya, dia selalu memintaku bercerita tentang mamaku yang
hilang ketika mencari Arjuna.
***
Akhirnya
mamaku menemukan Arjuna dan bercinta, konon, sembilan kali
sehari. Perempuan-perempuan lain yang telah dalam pelukannya
iri mendengar kabar itu. Mereka merencanakan makar dengan
menyewa manusia-manusia tanpa jiwa untuk mencelakakan
percintaan mereka. Tapi kabar itu tetap simpang siur. Ada juga
yang bilang, papa membayar orang untuk menebus sakit hati dan
rasa cemburunya.
Suatu
ketika, ketika Arjuna bersendawa bunga dan berkata-kata
wewangian abad dua puluh, mamaku lambat mengingatkannya.
Sesuatu yang licin menerbangkan mereka, entah membentur apa.
Arjuna memang sakti, ia tidak cedera sedikit pun. Kaki kiri
mama patah. Dan Arjuna tak perlu susah-susah menunggu mama
sembuh sebab bercinta adalah menu yang dapat disantapnya dari
pemuasnya yang lain. Mama hanya salah seorang dari mereka yang
hadir dalam hidupnya yang penuh berahi.
Arjuna
menghilang ke kayangan yang lain untuk bercinta sambil
berkayang dengan dayang-dayang pemuja kata-kata mutiara. Mama
menghilang dari rumah sakit, entah ke mana. Dia hanya memberi
kabar kepada keluarganya, tapi bukan kepada keluarga papa. Dia
ada di sebuah desa, di rumah seorang perempuan berhati kapas.
Ketika
luka itu mulai kering dan nyeri mulai sepi, setiap pagi ia
memandang matahari yang menerobos dedaunan. Ia mencari
inspirasi untuk melepaskan diri dari tongkat kayu penyanggah
tubuhnya. Cinta atau nafsu yang menggebu menyuntikkan energi
penyembuh dalam dosis tak terhingga. Tak sampai sebulan ia
mampu berjalan tanpa tongkat meski langkahnya tak seindah dulu.
Tapi Arjuna tak membutuhkan gerak yang berubah itu karena dia
tikus yang lebih melihat isi daripada bentuk.
“Bu,
aku tak bisa melanjutkan cerita ini. Mamaku sepertinya akan
datang entah dari arah mana.”
“Ceritamu
bagus, kamu pasti menjadi pemenangnya. Saya suka membacanya,
meskpun ia baru berupa sketsa kasar.”
Perempuan
berbaju dinas memesankan lagi es degan buat teman ngobrolnya.
“Tapi,
aku tak menulisnya untuk lomba. Aku ingin ketemu, Mama.”
“Kau
pasti ketemu dia jika keyakinanmu sebesar keyakinan mamamu
saat berusaha bangkit dari kelumpuhan semangat, saat didera
nyeri bertubi-tubi di kaki kirinya.” Remaja lelaki kesepian
itu hanya diam sambil memandang kertas-kertas sketsa ceritanya.
“Apa
kamu tahu seperti apa wajah mamamu?”
Dia
ragu antara akan mengangguk dan menggeleng. Akhirnya dia
menggeleng sebab hidup harus punya rahasia tertentu.
***
Mama
tak punya kepala, meski aku tahu seharusnya dia kehilangan
kaki kirinya. Aku ingin mengenalnya dari kaki kirinya saja.
Tapi, apa bisa? Bukankah banyak orang di kota ini yang cara
berjalannya miring ke kiri karena beragam alasan? Aku harus
mengenalinya dari kepalanya, tapi bagaimana? Dan itu hanya
pada awalnya ketika aku masih belum berani bertanya. Tapi kini
tak ada lagi gambarku bersama mama. Entah ke mana lembaran
gambar lama melayang dan berganti dengan gambarku bersama
kakek, nenek, dan papa.
Aku
yakin aku punya mama meski gambarnya telah musnah sebab aku
manusia dan anak-anak burung-burung piaraanku semuanya
berinduk. Tapi papa tak pernah tahu kalau aku telah belajar
dari mereka mencari induknya ketika mereka haus dan lapar.
Inikah naluri binatang piaraan? Papa memang telah sempurna
mengenakkan aku kecuali untuk satu hal: dia tak pernah
menjawab pertanyaanku dengan memuaskan tentang mengapa mama
jatuh ke pelukan Arjuna yang telah menyengsarakannya. Apa beda
papa dan Arjuna itu? Begitukah laki-laki? Akan demikiankah aku?
Tapi
ini tak kuceritakan kepada ibu pejabat yang selalu menemaniku
ngobrol di warung itu meski hari ini adalah pertemuan
terakhirku dengannya sebab dia akan dimutasi ke kantor lain di
luar kota beberapa hari lagi.
“Aku
akan merindukan ceritamu.”
“Aku
akan merindukan kebaikan ibu.”
Mereka
sama-sama dia beberapa saat sambil sama-sama memutar-mutar
sendok di gelas mereka. Mereka bisu bukan karena habis kata,
hanya karena terlalu cinta. Mereka bisu bukan karena mati,
hanya karena rindu: di mana mati tak punya arti.
“Bolehkah
saya tanya satu hal saja, Bu.”
“Boleh.
Semoga ibu bisa jawab. Kalau tidak bisa, kamu jangan marah, ya?”
“Kenapa
ibu suka meluangkan waktu di warung ini dan memilih saya saja
sebagai teman ngobrol?”
Mungkin
hidup memang harus punya rahasia tertentu. Ibu itu memang
berkata-kata tapi tak menjawab apa-apa.
***
Dia
adalah ibu yang kehilangan anak sejak kabut pikirannnya
tersingkap sempurna. Sebelum itu anak hanyalah senjata
suaminya untuk mencincang batinnya hingga remuk
seremuk-remuknya. Sebab lelaki itu merasa perempuan itu
bermartabat karena dirinya yang ningrat, keturunan orang
terpandang, yang berhak menendang mereka yang dianggap kurang
terpandang. Dia merasa dengan mudah mendapatkan perempuan yang
lebih darinya karena setiap perempuan telah dianggapnya
sebagai makhluk bodoh, yang mudah tergiur oleh kekayaannya.
Tapi
dia masih mengenali wajah anaknya karena dia tak pernah
memotong bagian kepalanya saat kabut menelikung kesadarannya.
Dia hanya yakin suatu saat ada saat yang tepat, yang akan
mempertemukannya dalam banjir air mata, jika ia belum kering.
Sebab, hidup harus punya rahasia. Tak seorang pun boleh
melihatnya tampak cengeng ketika kangen menderanya untuk
bertemu dengan buah hatinya.
Banyak
yang pergi, ada yang tak kembali. Jejak ditinggalkan terhapus
angin sepoi. Kubiarkan hanyut. Kuambil sirna betina nasibku.
Apa guna bulan merasuk bulan, tapi putuhnya ditelan awan....
kasihku tetap perawan.
Kukatakan
padanya, jika kelak dia ketemu anaknya dan tak bisa lagi
menangis sebab air mata telah kemarau, aku berjanji untuk
menghadiahkan sepotong gambar mata yang masih kusimpan dan
penuh air. Mata itu kucuri dari satu foto yang belum teraniaya.
Itu mata mama. Hanya sepasang mata.
“Hari
ini aku berangkat. Ini kenang-kenangan buat kamu.”
“Wah,
apa nih?”
“Karena
kamu suka main bola dan menulis, ibu belikan sepatu bola dan
pena. Karena kamu sudah tahu isinya, sebaiknya dibuka nanti
saja, di rumah.”
“Terima
kasih banyak, Bu.”
Remaja
itu segera meraih tangan ibu berpakaian dinas itu. Dia sungkem
tulus. Tapi ibu itu punya rahasia. Ia dingin, datar, dan
menepuk pundaknya sambil berpesan agar remaja itu terus
belajar, berjuang, dan menaklukkan pertanyaan yang belum
terjawab.
“Bolehkah
saya mengajak ibu bertukar pikiran lewat telepon kantor ibu
yang baru?”
***
Dia
adalah mamaku yang kini hilang setelah memberiku sepatu dan
pena. Di dalamnya terselip fotoku bersamanya, tapi dia masih
punya kepala. Orang-orang di kantornya yang dulu tak ada yang
tahu dia dimutasi ke mana. Lebih tepatnya, mereka tutup mulut.
Aku tak harus mencarinya karena kini mungkin waktu yang tak
tepat baginya untuk mengakui kembali aku sebagai anaknya.
Inikah rahasia orang dewasa? Sandiwara kelas tinggi bagiku
yang masih meraba makna cinta. Kini aku tak hanya mengenal
garis dan warna tapi juga mulai mengerti makna rahasia.
Karenanya, aku percaya pasti ada saat yang paling tepat
baginya untuk kembali menemuiku seperti caranya menemuiku di
warung itu. Cara yang tak pernah aku duga.
Papaku
juga tak perlu tahu kalau aku sudah tahu siapa mamaku sebab
dia akan membawaku ke psikiater dan menganggapku tak waras.
Aku jadi tahu bahwa waras berarti berbohong. Kata papa,
kewarasan semacam inilah yang membuat dirinya bermartabat,
bergengsi. Aku, mama, papa memang waras, tapi aku tahu kami
dusta. Apa mama juga menyadarinya?
Banjarmasin,
3 Maret 2005
Koran Radar
Banjarmasin, 24
April 2005 |