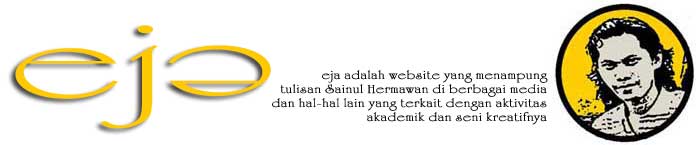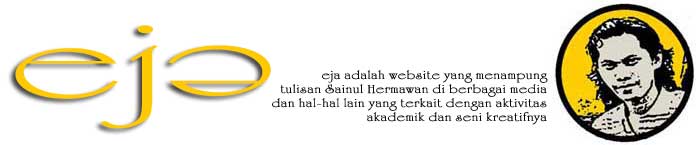Ambiguitas
Kritik “Ya” atau “Tidak”
(Menanggapi
Kritik Rain Fajar)
Oleh
Sainul Hermawan
Saya
sangat senang sekaligus sedih membaca tanggapan R. Fajar atas
penjelasan saya terhadap kritik R. Ayuningrum mengenai
inkonsistensi cerpen “MuM”. Senang karena penjelasan itu
ada yang membaca, meski mungkin juga banyak yang tak peduli.
Senang
karena pembacaan itu tak hanya berakhir di ujung
manggut-manggut pembacanya yang dapat berarti macam-macam (paham,
tak paham, salah paham, pura-pura paham, pura-pura tak paham,
dan sebagainya).
Senang
karena, dengan caranya sendiri, R. Fajar telah berusaha
mengajak saya untuk memberikan penjelasan baru bukan atas nama
cerpen “MuM” yang bebas dari kepentingan penulisnya,
tetapi atas nama penjelasan saya di Radar Banjarmasin
(27/05) tentang
cerpen multisudut pandang yang mungkin kurang jelas.
Sedih
karena ada nuansa “pemaksaan” terhadap proses kreatif
penulis “MuM” yang menyatakan dapat inspirasi dari novel.
Pernyataan R. Fajar yang berbunyi: ... saya tidak ingin
mempermasalahkan pendapat Martin dan Hill. Akan tetapi yang
ingin saya ungkapkan adalah ketidakmengertian saya akan
argumen...bahwa penyudutpandangan cerpen “MuM” dipengaruhi
oleh novel Saman dan The Collector. Bukankah
keduanya adalah novel? Sedangkan MuM adalah cerpen. Saya tahu
Saudara Sainul pasti lebih paham perbedaan ruang gerak antara
cerpen dan novel (paragraf
ke-5).
Dalam
paragraf itu dan beberapa paragraf yang mengikutinya (6 sampai
8) secara tak langsung R. Fajar telah “memdakwa” penulis
“MuM” sebagai penulis yang tidak “taat” asas. Seperti
ada suara teriakan yang sangat keras: “Beri batas yang jelas
dong, seperti yang telah dilakukan oleh Saman
dan cerpen lain yang telah melakukan teknik yang sama, kalau
mau ganti sudut pandang biar pembaca Anda tak bingung!”
Mungkin
dia pun ingin mengatakan, “karena dimensi ruang novel dan
cerpen beda, maka “haram” bagi keduanya untuk saling
mengilhami”. Mungkin sebaiknya saya melakukan apa yang Anda
sarankan tetapi mungkin juga tidak perlu sebab batas yang tak
jelas tersebut sengaja dihadirkan dengan cara demikian dalam
cerpen “MuM” sebagai salah satu ruang penandaan yang bebas
ditafsirkan dengan cara apapun, termasuk dengan cara Anda.
Kok
begitu? Alasannya sederhana: ruang gerak dalam dunia sastra
adalah wilayah penciptaan yang dinamis. Setiap karya
senantiasa berupaya keluar dari belenggu tradisi. Ruang gerak
biasanya disikapi oleh sastrawan bukan sebagai “asas”
melainkan “kanvas”.
Soal
inspirasi. Kesedihan saya mungkin terobati jika kelak ada
dalih-dalih yang lebih mengesankan dan meyakinkan bahwa memang
“haram” bagi penyair menulis puisi yang diilhami oleh lagu
pop, film porno, atau adegan syur di Pantai Jodoh; atau bahwa
memang haram bagi cerpenis menulis cerita yang diilhami oleh
puisinya sendiri; atau juga bahwa haram bagi sutradara untuk
bikin film yang diilhami oleh puisi, cerpen, atau novel hanya
karena alasan ruang gerak yang berbeda.
Sedih,
karena penutup tulisan R. Fajar cukup menyulitkan saya.
Mengapa? Saya ditanya apakah saya setuju dengan pendapatnya
bahwa: kebenaran
absolut ... hanya dapat diperoleh dari Yang Maha Tahu hakikat
segala sesuatu, Dialah Allah!... Saudara Sainul, sepakat
dengan pernyataan saya?... Dijawabnya di dalam hati
saja (paragraf terakhir). Dia hanya menawarkan dua opsi
jawaban: ya atau tidak.
Permintaan
untuk menjawabnya dalam hati seperti ini sungguh merepotkan.
Suruh menjawab tetapi dilarang menjawab. Artinya, dia butuh
jawaban sekaligus tak butuh jawaban karena jawaban dalam hati
mustahil untuk diketahui sampai jawaban itu dituliskan atau
diucapkan.
Saya
tak mau menjawabnya dalam hati, dan inilah jawaban saya.
Sebagai jawaban, tulisan ini bukan dalam rangka menjawab
“ya” atau “tidak” karena hidup juga penuh dengan
nilai-nilai “ya” dan “tidak” absolut yang menyesatkan.
Apakah memang “haram” kalau tidak menjawab “ya” atau
“tidak”? Apakah “ya” pasti berarti “taat” dan
“tidak” berarti “maksiat”? Saya kira “ya” juga
bisa berarti maksiat dan “tidak” berarti “taat” jika
oposisi tersebut tidak semata diletakkan secara sinkronis,
horisontal, sintagmatik, dan tekstual.
Secara
diakronis, vertikal, paradigmatik, dan kontekstual, Allah
dalam imajinasi R. Fajar tak akan pernah sama dengan Allah
dalam imajinasi saya. Lagi pula untuk apa sih membawa-bawa
nama Tuhan hanya untuk sekedar mendiskusikan ide Plato yang
sekuler tentang kebenaran jika ide tentang Allah dalam
imajinasi Anda sudah selesai? Anda amini ide Plato tetapi juga
menolaknya: ambigu.
Selain
itu, tolong sampaikan kepada teman Anda yang muntah-muntah
setelah baca “sastra bau”. Ada sistem hubungan yang kurang
beres antara teman Anda dan “sastra bau” itu.
Ketidakberesan itu tidak hanya ada pada teman Anda dan sastra
bau, tetapi pada hubungan antara keduanya.
Kalau
kita analogikan dengan mabuk laut, udara atau darat, kita jadi
kurang bijaksana kalau kapal, pesawat, atau bis disalahkan
hanya karena ada satu atau beberapa orang saja yang mabuk dan
muntah-muntah. Cara yang saya kira cukup bijaksana adalah
mencari cara bagaimana agar tidak mual menghadapinya, atau
menerima “muntah” secara ikhlas sebagai bentuk kesadaran
diri pada ketidakmampuan mengatasi persoalan-persoalan
psikologis atau etis ketika berhadapan dengan sesuatu yang
memuakkan, menjijikkan atau memualkan.
Bisa
juga solusinya ikut opsi “ya” dan “tidak” yang Anda
tawarkan. Takut mabuk, jangan baca. Siap muntah, baca saja.
Tetapi, apakah persoalan sesederhana ini? Rasanya kok tidak.
Ada banyak orang yang tidak siap muntah terpaksa harus
mual-mual menghadapi hidupnya, demikian juga banyak orang
“mabuk” yang tak pernah menyadari dirinya sedang
“mabuk” dan “muntah” berkali-kali. Saya mungkin
termasuk di dalamnya dan mungkin juga tidak sama sekali.
Terlepas
dari rasa senang, sedih, dan mual di atas, saya sangat
menghargai upaya R. Fajar yang mau berbagi pengetahuan tentang
“sastra bau” yang malah belum sempat saya baca, dan jika
kelak saya sempat membacanya, mungkin saya akan “salah baca”.
Karena itu, kita selayaknya terus berdialog, bukan bermonolog,
dalam rangka saling mengoreksi kesalahan bersama yang mungkin
ada.
Sebab,
seandainya sejak bumi ini diciptakan tak pernah ada orang
salah baca, mungkin kita tak seintim ini dengan
“penderitaan” dalam pengertian yang luas. Jadi, gagasan
tulisan R. Fajar sesungguhnya juga berada dalam bingkai
konsistensi yang inkonsisten atau dalam absolutisme yang
absurd. Dan ini sesuatu yang biasa, dan sering kali terjadi,
meski kadang kita sulit menyadari karena kesadaran semacam itu
justru ditangkap dengan baik frekuensinya oleh orang lain.
Apakah ini berharga? Itu bukan wilayah wewenang saya.
Meskipun
demikian, saya tetap membuka diri bagi kritik-kritik
selanjutnya karena saya yakin keterbukaanlah yang akan lebih
mendekatkan diri dengan kebenaran. Konon semangat
spiritualitas perkotaan juga dibangun dengan prinsip membuka
diri seluas-luasnya, seikhlas-ikhlasnya, bagi kehadiran ruh
spiritual yang mereka cari. Bahkan, kelak, jika saya sempat
menulis cerpen yang lain, warna kritik Anda dapat dilihat,
tetapi mungkin juga tidak. Karenanya, terima kasih juga buat
“kecerdasan” itu.
|