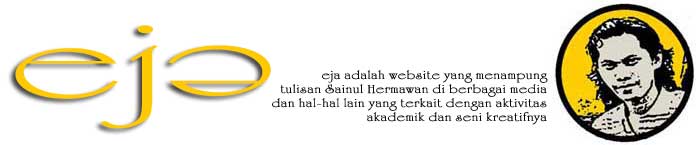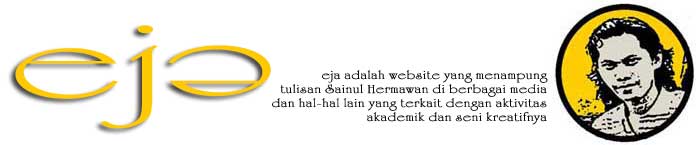(Memahami
Lebih Jauh R. Fajar dan Jamal T, Suryanata)
Oleh
Sainul Hermawan
Minggu,
4 September 2005, yang lalu adalah hari yang sangat istimewa bagi
saya karena saat itu ada dua tulisan berat yang ditujukan untuk
saya dalam rangka memikirkan kebenaran. Satu berasal dari Rain
Fajar (RF) dan yang lain dari Jamal T. Suryanata (JTS). Keduanya
bukan nama sebenarnya. Tulisan ini adalah respons bagi mereka
berdua.
R.
Fajar dan Bahasanya
Terus
terang saya tergelitik untuk berbincang lebih jauh ketika Anda
menulis begini dalam paragraf menjelang akhir dalam tulisan Anda
di Cakrawala (4/9/2005), “…Terkadang tulisan-tulisan
Anda memaksa realitas mengikuti teori yang Anda pilih. Padahal
seharusnya teori harus sesuai dengan realitas.” Dengan
kehadiran kata seharusnya (bukan harus), ada kesan
lunak bahwa teori yang tak sesuai realitas tak dapat sepenuhnya
disalahkan.
Dalam
hal ini Anda terkesan bimbang antara mau sepenuhnya menyalahkan
dan mau sepenuhnya membenarkan. Kehadiran seharusnya mengakibatkan
komentar Anda bersifat tanggung: liminal lagi, ambigu lagi. Jadi,
dalam hal tertentu sikap kita kadang tak jauh beda menyikapi
persoalan: tanggung. Secara implisit Anda menyalahkan teori yang
tidak sesuai dengan realitas, tetapi apakah Anda benar-benar paham
hakikat teori dan realitas?
Saya
bertanya begini bukan berarti saya sangat paham, tetapi apa yang
saya pahami dengan baik tentang keduanya adalah adanya kenyataan
bahwa teori dan realitas begitu berwarna, luas seluas samudera
atau padang pasir. Sedangkan realitas dan teori yang sering kita
perbincangkan adalah setitik noktah dari jutaan spektrum warna,
setetes air dari samudera, dan sebutir pasir dari padang pasir
tersebut (Mungkin JTS berkata dalam hati, “Nah ini dia ramuan
gembrot yang pas untuk kontes Miss Impian).
Tetapi,
kalau saya menyatakan demikian apakah realitas kita memang
demikian adanya padahal saya sangat yakin bahwa bahasa, kata-kata,
punya kemampuan terbatas untuk menjelaskan realitas. Sikap
tanggung adalah sikap yang dapat dimaklumi, wajar, manusiawi
karena unsur-unsur di luar diri kita juga tanggung, bahasa
tanggung, keyakinan tanggung, pemahaman tanggung, dan sebagainya,
dan seterusnya.
Kualitas
akhir sikap tanggung itu mungkin ditentukan oleh cara
menempatkannya: apakah ia ditempatkan sebagai sesuatu yang
berakhir dan mati atau sudah dititiki, atau ia sebagai sesuatu
yang terus berproses untuk mencapai derajat ketanggungan yang
relatif tidak terlalu tanggung? (berputar-putar begini bukan
bermaksud untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menjelaskan duduk
persoalan bagaimana bahasa yang Anda gunakan untuk menyampaikan
gagasan sebenarnya telah memangsa dirinya sendiri. Hal serupa
mungkin juga bisa terjadi dengan tulisan ini. Tetapi, saya sudah
waspada dan siap menerima bantahan apapun.)
Teori
dan realitas adalah dua wilayah yang sebenarnya tak bertepi,
tetapi kemudian untuk kepentingan manusia yang serba terbatas
keduanya dibatasi, diberi tepi, misalnya dengan menyatakan,
“Seharusnya ini begini dan tidak begitu,” meskipun yang begituan
alias tidak beginian menjadi realitas kaprah. Jadi, siapa
sebenarnya yang memaksa realitas mengikuti teori? Saya, Anda, atau
kita?
Ketika
Anda menulis tanggapan untuk tulisan saya dan cerpen Tapal Adam
apakah Anda tidak berteori? Ketika Anda berteori apakah Anda tak
memaksa realitas mengikuti teori Anda? Saya kira tidak, sehingga
sebenarnya Anda mengomentari nada tulisan Anda sendiri yang juga
cenderung memaksa realitas ikut teori yang Anda pilih. Jadi, Anda
tak sepenuhnya mengomentari tulisan saya. Misalnya, pada tulisan
Anda yang lalu tentang cerpen Tapal Adam, Anda
“memaksa” realitas sastra untuk menyesuaikan diri dengan
realitas agama.
Kemudian
jika Anda bertanya apakah tulisan Anda menghukumi haram cerpen
yang memberi sifat-sifat manusia kepada malaikat yang gaib, memang
secara eksplisit tidak, tetapi secara implisit “kesan
pengharaman” itu dapat menjadi konklusi yang tak terelakkan.
Tetapi kembali lagi pada hakikat bahasa yang terbatas, Anda boleh
menyatakan tidak bermaksud demikian tetapi pembaca Anda bukan tak
boleh memahaminya dengan cara berbeda.
Semoga
dengan penjelasan ini Anda semakin paham dengan pernyataan “kita
tak patut menganggap keyakinan diri kita sorangan, sebubuhan,
dan sebagainya sebagai keyakinan yang paling benar. Artinya, di
samping kebenaran yang kita yakini ada kebenaran lain yang
diyakini orang lain yang mungkin juga benar. Meskipun kita tak mau
menyakini karena kita setia pada keyakinan yang “asli” (meski
juga tak lepas dari spekulasi-spekulasi) kebenaran tetaplah
kebenaran. Semua orang berlomba mencapainya dengan caranya
masing-masing. Ada yang melakukannya dengan cara introvert,
dan ada pula yang mengejarnya dengan cara extrovert. Kubu
mana yang paling benar? Kata ustad-ustad TV, “Wallahua’lam
bissawab.”
Kalau
membaca teladan pertahanan keyakinan yang Anda sebutkan saya dapat
berkesimpulan bahwa keyakinan yang paling benar harus
dipertahankan dalam rangka menangkal serangan dari luar yang
hendak mengikisnya. Ketahanan keyakinan bukan untuk menyerang
keyakinan orang lain yang berbeda. Nash-nya jelas, “lakum
diinukum waliadiin.(QS. Alkafirun: 6).
Maka
setiap apropriasi (merebut makna sesuatu untuk kepentingan sepihak)
tentang kebenaran tetap harus diwaspadai. Argumentasi-argumentasi
dalam Open Mind ataupun Supernova 3 juga harus
diwaspadai karena realitas itu sesungguhnya tak bertepi. Realitas
dalam keduanya bukan satu-satunya realitas yang tervalid apalagi
dalam memaknai agnostik yang telah banyak bergeser pengertiannya
mengikuti sejarah perkembangan maknanya. Apalagi keduanya juga
tetap tak lepas dari motivasi politik bahasanya yang dibatasi,
membatasi, dan sudah tak asli lagi meski lagaknya saja asli.
Bahkan
ketika Divan (sumber yang Anda kutip) menulis, “Jadi, orang
agnostis akan mengatakan daripada berspekulasi lebih baik tidak
usah berpikir Tuhan itu ada atau tidak, toh keberadaan-Nya tidak
memiliki relevansi dengan kehidupan,” ini jelas-jelas
interpretasi subyektif yang didasarkan pada salah satu makna
agnostik. Kesimpulan sepihak semacam ini pun harus diwaspadai
karena mungkin tujuannya tidak untuk menjelaskan makna agnostik
secara berimbang, tetapi secara timpang, untuk menghasut
kelompok-kelompok manusia yang senang dihasut. Apropriasi semacam
ini pun bisa jadi sumber penyebab carut-marut pemahaman istilah
agnostik. Tetapi, kita bisa kembali menemukan alasannya yang
mendasar: Kata-kata, bahasa, adalah media manusia yang terbatas.
Meski
demikian, keseluruhan tulisan Anda menyiratkan keyakinan yang luar
biasa pada kemampuan kata-kata untuk memagari perbedaan antara
berpikir dan berimajinasi. Secara teoretis berpikir dan
berimajinasi memang dapat dibatasi. Buktinya, baca saja buku-buku
yang telah Anda sebut, tetapi pada realitasnya berpikir dan
berimajinasi nyaris berhimpitan. Ketika saya berpikir, saya
berimajinasi tentang
apa yang akan saya katakan, yang saya buktikan (kata imagine
dalam American Heritage Dictionary (1997)
juga memiliki sinonim yang banyak mengarah ke aktivitas
mental berpikir, seperti conceptualize, conceive, infer, reason, presume,
speculate, think, calculate, reckon, theorize, hypothesize,
presuppose). Dari
sisi ini lagi-lagi tampak siapa sebenarnya yang suka memaksa
realitas mengikuti teori yang dipilih? Anda, saya, atau kita?
Dalam
mengargumentasikan soal nama dengan membawa-bawa pesan Ali bin Abi
Talib pun Anda kurang menyadari konsekuensi jungkir balik realitas
yang dapat ditimbulkannya. Kalau Anda setuju dengan pernyataan,
“Janganlah engkau menilai kebenaran itu dari orangnya, tetapi
kenalilah kebenaran itu, maka engkau akan mengenal orang yang
mengembannya,” tetapi kenapa harus menyamarkan nama? Kalau
nama yang disembunyikan, berarti ia lebih penting daripada yang
lain-lain.
Sebaliknya,
jika kebenaran yang disembunyikan, berarti ia lebih penting dari
hal lain pula. Kalau keduanya yang disembunyikan, Anda dan
kebenaran yang ingin Anda sampaikan jadi tak berarti apa-apa:
sia-sia. Dalam hal ini Anda berlebihan menyikapi nama. Apakah
kalau Anda menuliskan nama yang sebenarnya, lantas kualitas
tulisan Anda jadi berubah? Apakah sikap pembaca Anda jadi lain?
Belum tentu. What is in a name, kata Shakespeare.
Sebagai
sebuah aktivitas agnostik, penyamaran nama memang menyenangkan.
Jadi tak perlu terlalu alergi dengan bahasa agnostik atau memuja
bahasa apapun melampaui pemujaan kita terhadal Allah SWT.
Disembunyikan atau tidak, nama siapapun bisa jadi agnostik dalam
proses historisnya. Misalnya, namanya Furqon tapi kerjanya suka
menyakiti perasaan orang, namanya Arif tetapi prilakuknya
morat-marit, dan sebagainya.
Karena
itu saya tak punya keinginan untuk cari tahu siapa Anda sampai
Anda menuliskan sendiri pada teks yang dapat dibaca siapa saja.
Seperti saya tahu Jamal T. Suryanata itu nama samaran karena dia
pernah menuliskan sendiri dalam biodata yang pernah saya baca.
Kalau sekedar pengakuan lisan, mungkin saya tak terlalu yakin.
Soal
pertanyaan, adakah nash-nash yang membolehkan penggunaan
nama malaikat, setan, dan sebagainya dalam teks sastra? Dalam hal
ini saya harus angkat tangan: saya bukan spesialis nash-nash.
Yang merasa ini bagiannya, saya sangat berharap bisa belajar dari
siapa pun Anda. Kalau bukan Anda, lalu siapa lagi? Tetapi, jika
sekian lama ditunggu tak muncul juga, silahkan kesimpulan akhirnya
ditarik sendiri. Fasten your seatbelt, biar singset.
Jamal
T, Suryanata dan Bahasanya
Setelah
mengikuti uraian bersambung JTS akhirnya saya sampai pada beberapa
kesimpulan bahwa dalam kesingsetannya sastra Banjar telah
terjerembab pada mitos “kecantiikan”-nya, kearkaisannya,
keadiluhungannya. Dalam sisi tertentu sastra Banjar ternyata juga
agnostik: ada tetapi tidak ada. Dalam pengertian keberadaanya
hanya dapat dirasakan dalam ungkapan-ungakapan keprihatinan atas
dampak buruk invasi kultur luar ketika pada saat yang sama JTS
juga pernah menganjurkan sastrawan Banjar untuk melihat ke dunia
luar.
Setelah
berbincang dengan B. Soebely, R. Syarifuddin, S. Firly, Jarkasi,
dan mahasiswa di PBSID FKIP dalam kesempatan yang berbeda,
keprihatinan mereka hampir seragam: sastra Banjar dengan bahasa
Banjar sudah lama ditinggalkan banyak orang, para pembacanya,
termasuk abah dan mama kandungnya sendiri yaitu para
sastrawan dan pihak-pihak yang semestinya melindunginya dari
kepunahan. Sastra lisannya nyaris musnah tanpa dokumentasi visual
yang memadai. Apalagi tradisi sastra tulisnya yang akhir-akhir ini
tak banyak terlihat medianya yang dapat dibaca setara dengan
membaca tabloid gosip. Orang Banjar mungkin sangat mencintai
bahasa Banjar tetapi kurang sayang pada sastranya. Jadi, sastra
Banjar yang secara singset diimajinasikan oleh JTS memang ada
secara teoretis, tetapi realitasnya yang ada dan mewabah
akhir-akhir ini adalah sastra Banjar dalam penggertian ramuan
gembrot: sastra Banjar tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia
tetapi kebanjaran titisan lisannya masih sangat kental.
Kalau
ada pengamat budaya Kalimantan Selatan yang menyatakan sastra
Banjar dalam bahasa Indonesia tak mengandung “pikiran” sama
sekali dan tidak mampu beranjak dari persoalan kampungnya yang
sangat terbatas, ini mungkin dapat disebabkan oleh dua hal:
pertama, bahasa Banjar yang wilayahnya sangat terbatas, dan kedua,
pikiran sastrawan Banjar yang mungkin malas membuat
terobosan-terobosan kreatif yang dapat mengguncang banua ini.
Syukur-syukur kalau bisa membuat gempar seperti Salman Rusdhie,
asal tujuannya bukan sekedar membuat gempar, tetapi karena memang
ada nilai-nilai mendasar tentang keberadaan manusia dan
kehidupannya. Sekedar informasi, saya tidak tahu mengapa ada
semacam keengganan mahasiswa untuk meneliti sastra Banjar dalam
pengertian yang singset itu meski dorongan untuk mereka agar
meneliti hal tersebut tak kurang-kurang. Dan persoalan ini bukan
semata tanggungjawab PBSID FKIP UNLAM.
Tampaknya,
untuk melihat realitas sastra Banjar yang jelas dalam pengertian
yang singset perlu sinergi empat arah yang baik, yaitu antara
sastrawan, pemerintah, pers (media massa) dan lembaga pendidikan (termasuk
kampus). Ini juga sinergi gembrot. Solusi bagi sastra Banjar yang ngalih
tak bisa pakai galiang singset dan menyerahkan seluruh nasibnya
pada satu aparat sastra saja. Tetapi, siapa yang mau memulai?
Kalau realitasnya yang kedodoran, singset atau gembrot jadi sama
saja, sama-sama kabur realitasnya. Tetapi, tetap saja berguna
sebagai investasi penyegaran pemikiran tentang sastra Banjar.
Keyakinan
berlebihan kepada bahasa sebagai alat yang dapat menghadirkan
realitas, perasaan, pengalaman, universal ataupun nasional yang
utuh kepada setiap orang juga dapat kita baca ketika JTS
menyatakan bahwa Banjar adalah subordinasi Indonesia, maka
karenanya sastra Indonesia tak bisa jadi subordinasi sastra Banjar.
Keyakinan yang singset semacam ini menutup mata bagi kemungkinan
tersubordinasinya sastra Indonesia oleh sastra Banjar karena tak
seluruh “diri” Banjar itu dapat disubordinasi oleh Indonesia,
seperti keinginan yang ingin tetap menjadi singset adalah salah
satu bagian yang ngalih untuk disubordinasi oleh Indonesia.
Bagi
ramuan gembrot, Indonesia yang dipahami secara singset juga
merupakan realitas yang sukar diterima. Jadi, karena Indonesia tak
pernah benar-benar dapat menjadi realitas faktual yang kaffah,
tapi hanya realitas imajiner yang belang-belonteng, coreng-moreng,
keindonesiaan terus berada dalam aneka kemungkinan yang gembrot
dan terus dibangun.
Demikian
pula dengan kebanjaran. Parameter birokratis dan demografis untuk
memahami konsep Indonesia dan Banjar sangat kurang tepat untuk
meletakkan dasar-dasar pemikiran spekulatif untuk meraih
realitas-realitas kebanjaran yang masih kabur, yang agnostik.
Dengan ramuan gembrot kita dapat tertolong untuk tidak menyebut
ekor gajah sebagai gajah, atau menyebut sastra Banjar sebatas
berdasar pada faktor kebahasaannya.
Kalau
kita baca buku La Ventre de Kandangan, Mosaik Sastra Hulu
Sungai Selatan (HSS) 1937-2003 karya Burhanuddin Soebely
(2004), kita bisa melihat betapa ramuan gembrot adalah ramuan
impian yang mampu membuka kemungkinan bagi tersusunnya buku
tersebut sehingga apa yang disebut dengan sastrawan HSS bukan saja
sastrawan yang lahir di HSS tetapi juga mereka yang tak lahir di
HSS namun bekerja dan tinggal lama di HSS, dan mereka tidak hanya
menulis dalam bahasa Banjar tetapi juga bahasa Indonesia. Dalam
buku ini Indonesia tampak menjadi subordinasi konseptual bagi
Kandangan.
Kebenaran
memang dapat disampaikan dengan bahasa, tetapi tak sepenuhnya.
Pemahaman yang singsetlah yang mengimajinasikan bahwa ada hubungan
esensialis, hakiki, dan tak dapat diganggu-gugat, antara bahasa
dan kebenaran. Pemahaman yang gembrot tidaklah demikian. Meski pemahaman
semacam ini masih minoritas, akhir-akhir ini ia mulai naik daun
karena ikut Miss Impian (baca: impian yang terus hilang
karena “ideologi langsing” tetap menghegemoni).