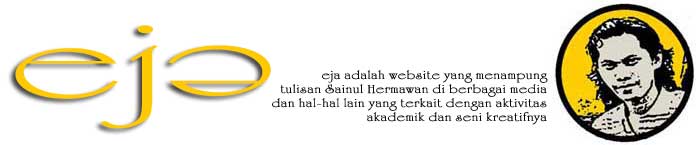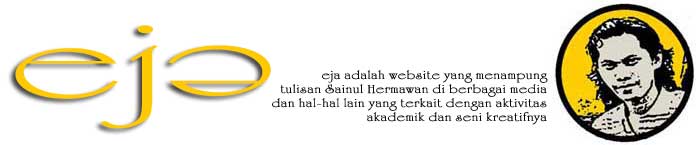Kalimantan,
Kapitalisme, dan Cerpen “Galuh”
Oleh
Sainul Hermawan
Cerpen “Galuh” yang menjadi judul buku antologi sepuluh
cerpen karya Jamal T. Suryanata (Jamaluddin) adalah judul
cerpen ke-10 atau terakhir dalam antologi ini. Pada awalnya
antologi yang diluncurkan sambil berdiskusi pada 16 Mei 2005
di Taman Budaya, Kayutangi, Banjarmasin, tidak sedikitpun
menarik perhatian saya yang baru (sekitar dua bulan)
bersentuhan dengan bahasa dan budaya Banjar. Tetapi ketika
mencoba membaca Sahibar Catatan antologi ini, literary
sensitivity saya jadi tergoda juga. Paragraf yang
mendorong pembacaan yang kemudian diupayakan untuk diulas
dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bubuhan pembaca
nang “baiman”...liati haja nang kaya apa aku malanah teori-teori
nangitu dalam kisdap-kisdap “Galuh”, “Pambatangan”,
“Banjarsari”, ..., atawa nang lain-lainnya (Suryanata,
Galuh, 2005: xv).
Setelah itu saya tak terlalu percaya pada kabar angin bahwa
Jamal sebenarnya kurang baik dalam menulis prosa.
Pernyataannya dalam paragraf di atas secara tidak langsung
menyatakan bahwa Jamal tidak main-main dalam menulis
kisah-kisah dalam antologinya. Ia sangat serius menekuni
bidang ini sebagai media untuk mengungkap rahasia-rahasia
manusia yang dibawakannya dengan cara rahasia pula. Cara ini
pasti diyakininya sebagai jalan paling efektif untuk menggugah
kesadaran menjadi manusia banua yang kritis. Di balik sejumlah
prosanya dalam antologi Sakindit Kisdap Banjar ada
sejumlah teori yang mendasarinya, meskipun dia tidak mau jika
disebut prosais yang berkiblat pada teori semata. Jamal
menulis: ... aku manulis kisdap tu sabujurnya sama lawan
bajajak di babun—artinya jua, karancakan wayah aku mangarang
tu kada talapas pada teori-teori nang sudah kukulum.
Tagal, jangan pulang mun dipadahakan aku bakiblat lawan teori-lah
(Suryanata, Galuh, 2005: xii-xiii).
Sebenarnya secara alamiah urang Banjar sangat memahami
hakikat intertekstualitas yang dimaksudkan oleh M. Riffaterre.
Kata Riffaterre (1978:11) tanda-tanda dalam teks sastra (begitu
pula dalam semua kisdap Jamal) selalu dan akan terus
mengalami proses semiosis. Oleh karena itu, untuk
memahami proses semiosis itu, tanda-tanda itu harus
diletakkan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan
kompleks.
Istilah kisah (kesah) yang secara luas digunakan oleh urang
Banjar juga membawa potensi konotatif sebagaimana hakikat
tanda dalam kisah-kisah handap. Dalam istilah
“kisah” atau “kesah” ada permainan nilai-nilai
ambivalen yang sangat kuat. Pemahaman pragmatik urang
Banjar terhadap hakikatnya sebenarnya adalah potensi urang
Banjar memaknai “kisah” sebagai dunia yang mungkin (possible
world).
Artinya, kisah itu bisa cerita yang memang benar-benar
terjadi, baru dibayangkan akan terjadi, atau bualan kosong dan
gombal semata. Dalam bahasa Riffaterre (1978: 10),
hubungan kisah dan kenyataan yang diacunya bersifat
simbolik atau tidak langsung. Maknanya tidak hanya di kepala
penulis, tetapi juga ada dalam kisah itu sendiri dalam
kaitannya dengan kisah-kisah lain, dan juga ada dalam pikiran
pendengar atau pembaca. Jadi, makna-makna kisdap Jamal
pun bercabang tiga yang secara diakronis akan terus berdialog
dengan kenyataan baru urang Banjar. Sehingga maknanya
pun dapat berlipat ganda melebihi jumlah makna awalnya.
Demikianlah hakikat karya
sastra yang bertujuan agar pembacanya tidak sekedar jadi
konsumen teks, tetapi jadi produsen teks. Memaknai teks dalam
kerangka ini bukan sekedar memberikan sebuah makna bagi teks
tersebut, tetapi berusaha mengapresiasi pluralitas makna yang
mungkin menyusunnya menjadi karya seni yang multi-interpretatif
(Roland Barthes, S/Z, 1974: 5)
Konotasi Sosialis Galuh
Galuh
sebagai tanda secara semiotik merupakan interaksi antara
penanda (signifier) dan petanda (signified),
yang berpotensi membentuk jaringan tanda-tanda baru. Oleh
karena itu, ia dapat dimasuki melalui bermacam-macam pintu.
Dalam konteks ini Galuh dapat dimasuki dari pintu mitos (seperti
pernah dilakukan oleh budayawan Jarkasi), pintu
intertekstualitas, pintu feminitas, pintu Marxisme, dan
sebagainya.
Pintu mitos dapat mengarahkan pembaca pada serangkaian
aktivitas pendulang intan di Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel)
dengan seperangkat mitos yang melingkupinya. Pada tataran
tertentu cerpen ini dapat dilihat sebagai refleksi statis
mitos dan refleksi dinamis mitos Galuh. Pintu
intertekstualitas dapat menunjukkan kepada pembaca bagaimana
teks Galuh menyerap hipogram atau teks-teks acuan (baik
tertulis atau tidak) yang ada, baik secara mikro (dalam
lingkup sistem sastra Banjar) maupun secara makro (dalam
lingkup sistem sastra nasional atau yang lebih besar lagi).
Pintu feminitas dapat dibuka
oleh mereka yang tertarik membaca cerpen ini dari sudut
pandang kajian gender untuk menelaah bagaimana Galuh sebagai
perempuan dan tokoh perempuan lain diposisikan dalam cerpen
ini. Semua ini bukan tugas tulisan ini mengupas tuntas dalam
ruang yang terbatas ini. Ada pembaca lain, seperti para
mahasiswa pemerhati bahasa dan sastra Banjar, yang dapat ikut
berbagi gagasan melalui penelitian yang serius.
Tulisan ini hanya hendak
menunjudkan bagaimana Galuh membangun hubungan simbolik dengan
dunia kapitalisme dan kemiskinan di Kalsel. Secara sintagmatik,
atau berdasarkan jalinan tanda yang hadir dalam teks, Galuh
adalah seorang ratu yang ingin menikah dengan Ancah, seorang
pendulang intan yang miskin. Keinginan itu tidak terjadi di
dunia nyata, tetapi dalam dunia gaib. Tetapi rencana
pernikahan mereka gagal dan sekaligus berarti Ancah urung jadi
raja karena tiba-tiba ada seseorang yang tidak setuju dengan
rencana pernikahan itu. Orang yang tidak setuju itu membunuh
Ancah yang telah terbunuh. Ancah mengalami dua kematian.
Pertama ia mati tertimbun tanah terowongan tempat ia
mengejar-ngejar intan ajaib yang disebutnya Galuh, dan kedua
mati dibunuh dalam kematiannya.
Struktur penceritaan ini sangat menarik. Secara
pragmatik, atau jika tanda-tanda yang pada tataran teks itu
dikaitkan dengan konteks yang mungkin, tampak ada isyarat yang
sangat kuat menegaskan hubungan konflik yang samar
antara tokoh yang berbeda kelas sosial. Ancah adalah simbol
kemiskinan dan Galuh adalah simbol glamoritas kelas sosial
atas. Signifikasi itu dapat kita tarik pada signifikansi
relasi sosial yang terjadi antara para pekerja pendulang di PT
Galuh Permata. Dalam hubungan kapitalistik antara pekerja
pendulang di PT Galuh, kaya hanyalah impian. Impian yang tak
mungkin terjadi nyata karena kapitalisme senantiasa terus
berusaha melanggengkan struktur eksploratifnya untuk membuat
orang-orang miskin di Kalimantan terus miskin dan akhirnya
mati. Demikian juga alamnya, karena yang penting bagi
kapitalis hanyalah uang. Kapitalis tidak peduli pada arti
penting lingkungan hidup dan filosofi bahwa pada akhirnya
manusia tidak bisa makan uang.
Secara tidak langsung, cerpen “Galuh” sebagai
fakta semiotik dalam konsep Riffaterre, menyentil pemikiran
kritis orang-orang Kalimantan terhadap keberadaan penambangan
intan, secara khusus, dan eksplotasi tambang yang lain, secara
umum, dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan dan
lingkungan hidup. Apakah hasil eksplotasi tambang di banua ini
sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Kalsel? Atau
hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja? Jadi
cukup beralasan mengapa sampul antologi cerpen ini didominasi
oleh warna hitam dan merah. Ada semangat untuk menyuarakan
nilai-nilai kiri: nilai-nilai sosialis untuk melawan dominasi
kapitalis di banua ini. Tetapi nilai-nilai itu sangat samar.
Cerpen “Galuh”, dalam
hal ini, cukup memadai sebagai dokumen estetis yang
menggambarkan konflik sosial orang miskin di sekitar wilayah
ekplorasi tambang. Setidaknya cerpen ini secara semiosis
dapat membawa pikiran pada hubungan disharmoni antara
masyarakat petani Palam,
Banjarbaru, dan PT Galuh Cempaka (perusahaan swasta asing)
yang pernah gencar diberitakan koran ini tahun lalu (sekitar
Juni-November 2004). Dari berita-berita itu dan cerpen ini
kita dapat mendapatkan kabar sedih tentang kekalahan urang-urang
miskin di hadapan para kapitalis. Ini adalah salah satu bentuk
kisah silent take over. Kapitalis asing bersekongkol
dengan penguasa dan “urang-urang miskin” mengeruk
habis-habisan alam Kalimantan dan sebagian besar orang yang
tak berkepentingan dengannya hanya dapat limbahnya karena
rendahnya mental, moral, dan sikap pemimpin terhadap arti
penting lingkungan hidup.
Bahkan mungkin juga pembaca
menarik hubungan simbolik cerpen “Galuh” dengan konteks
kontes Nanang-Galuh yang cenderung bernuansa kapitalis. Semiosis
karya sastra dan realitas memfaktualkan aktualitas. Aktulitas
yang serba melintas sekilas disergap menjadi struktur abadi
oleh sastra sehingga yang buru-buru mau lewat dicegat, lalu
dirawat. Karenanya, sastra sering jadi inspirasi untuk
mengkaji segala hal di sekitarnya.
Banjarmasin,
Mei 2005
|