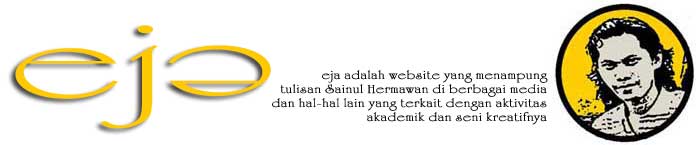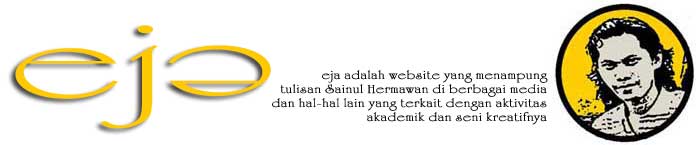Liminalitas
Surealisme Solipsis
(Tanggapan
untuk Rain Fajar)
Oleh
Sainul Hermawan
Untuk
kedua kalinya saya berkesempatan membaca kritik sastra Rain
Fajar di Cakrawala. Kritik itu ditujukan untuk cerpen
surealisme magis “Tapal Adam” (“TA”) karya Esa S.
Soemarno di Cakrawala (Radar Banjarmasin,
03/07/2005). Sebagai orang sesivitas, saya merasa bangga punya
mitra yang selalu mengasah pikirannya dan mengajak orang lain
berpikir. Dengan kritiknya yang, untuk sementara ini,
cenderung religius, fanatis, dan eksklusif, tulisannya
setidaknya mampu mengisi salah satu spektrum penafsiran
teks sastra. Ya, hanya salah satu dan mustahil untuk
menjadi satu-satunya tafsir yang paling benar untuk
teks cerpen yang telah dibacanya karena setiap tindak
pembacaan adalah peristiwa yang unik dan tidak otonom atau
selalu dan pasti dipengaruhi oleh beragam faktor sosial: usia,
keluarga, masyarakat, kelas sosial, sumber bacaan, afiliasi
politik, pengalaman masa lalu, tingkat ekonomi, tingkat
pendidikan, jenis pendidikan, dan sebagainya.
Tulisan
ini dimaksudkan bukan untuk menyalahkan persepsinya tentang
sastra dan bukan pula untuk membela cerpen surealis Era S.
Soemarno, tetapi mencoba menunjukkan betapa sastra olehnya
dipandang terlalu sederhana dengan melandaskan gagasannya pada
asumsi-asumsi teoretis yang masih penuh masalah. Sebagai mitra
berpikir, saya berharap R. Fajar dapat menulis kritik yang
lebih dahsyat lagi dengan pijakan teori yang lebih kuat dan
tak mudah dijatuhkan oleh argumen-argumen lain setelah dia
melihat uraian ini yang berusaha menunjukkan di mana letak
masalah-masalah dalam tulisannya.
Masalah
pertama adalah pengutipan gagasan AN Nabhani yang mengatakan
bahwa teks sastra ditulis untuk membangkitkan kenikmatan,
perasaan, dan kesan. Kebenaran dan ketepatan pemikiran dalam
teks sastra tidak menentu dan tergantung kesan. Teori ini tak
sepenuhnya benar karena teks sastra tak selalu nikmat (seperti
halnya R. Fajar yang merasa terganggu perasaan dan pikirannya
saat baca “TA”), dan teks sastra tak hanya mengusik
perasaan pembaca yang sejak awal berniat membaca teks sastra
dengan akal, rasio, pikiran.
Teori
ini benar karena teks sastra bukan klaim tentang kebenaran
tetapi konstruksi tentang kebenaran yang relatif. Maka nabi,
tuhan, setan, malaikat, yesus, dewa, dan hantu-hantu klenik
dalam teks sastra tidak bersifat referensial dan denotatif,
tetapi bersifat tekstual dan konotatif. Jika teks sastra
mendekonstruksikan tanda-tanda itu, pembaca sastra yang arif
dan bijak, yang paham hakikat polisemi bahasa, tak perlu
lantas naik darah, merah, marah, dan kesetanan.
Masalah
kedua adalah pengutipan gagasan Kutha yang mengesensialkan
status imajinasi dalam struktur karya sastra sehingga terkesan
teks sastra sepenuhnya berisi imajinasi yang berkonotasi
negatif, manipulatif, dan dekonstruktif. Saya yakin Anda akan
segara tahu bahwa imajinasi bukan hanya bagian esensial teks
sastra tetapi juga bagian dari kegiatan berpikir yang lain,
bahkan menuju tuhan juga perlu imajinasi, merancang teori ilmu
pengetahuan apapun juga melibatkan imajinasi. Bedanya,
imajinasi dalam sastra adalah imajinasi untuk seni yang dapat
mengarah keberbagai kemungkinan arah yang luas, meski pasti
selalu terbatas karena di baliknya ada struktur yang masih
dapat kita lacak pola-polanya. Pola-pola itu, menurut
Levi-Strauss, adalah mitos.
Masalah
ketiga, Anda ambigu atau ambivalen dalam melihat hubungan
antara sastra, agama, dan kebenaran. Secara eksplisit Anda
mengatakan setuju dengan gagasan bahwa sastra bukan panduan
agama dan karenanya tak perlu mencari agama dalam sastra.
Tetapi, secara keseluruhan tulisan Anda bertolak belakang
dengan sikap setuju Anda karena Anda tetap mencari agama (akidah-akidah
agama) di tempat yang keliru. Jadi, mengharapkan teks sastra
yang bersinggungan dengan persoalan agama agar selurus dan
selaras dengan pemahaman keagamaan tertentu bukan keinginan
yang harus dituruti oleh teks sastra karena persoalan
keagamaan yang ada dan diselewengkan di dalam teks sastra tak
perlu dipandang semata sebagai pelecehan keimanan kelompok
agama tertentu.
Sebagai
teks yang multitafsir, keadaan menyimpangkan unsur-unsur
keimanan dalam agama yang dilakukan teks sastra mungkin dapat
dilihat sebagai “godaan setan” yang harus disikapi secara
arif oleh orang beriman. Mungkin juga, ia tak harus dipandang
demikian, dan sangat tergantung dengan mediasi teoretis yang
dipakai pembaca untuk melihatnya. Apakah salah Anda
mempersepsikan demikian? Tidak, hanya saja argumen Anda secara
eksplisit sangat kontradiktif.
Masalah
keempat, Anda mereduksi pengertian agnostik sebagai sikap atau
orang yang tak percaya pada (tak meyakini keberadaan) tuhan.
Secara umum orang agnostik bukan orang yang tak percaya pada
tuhan, tetapi orang yang percaya bahwa realitas tuhan yang
sesungguhnya tak dapat diketahui kecuali representasi wujud
ketuhanan yang dapat diindera oleh manusia (lihat pengertian agnostic
dalam A.S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of
Current English, 1974: 18). Artinya, tuhan itu berada di
luar jangkauan kata-kata yang digunakan oleh manusia. Arti
lainnya adalah kata-kata manusia terlalu terbatas untuk
memaknai hakikat tuhan.
Bahkan
tanda-tanda keberadaan pandangan agnostistik dapat juga kita
baca dalam hadits yang diriwayatkan Abu Na’im dan Tirmidzi
yang berbunyi: tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi
dzatillah, fainnakum la taqdurunna qudratahu (lihat di
kitab Bulughul Marom atau kitab Mukhtar Ahadits, hlm.
62). Artinya, renungkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan
dzat-Nya, karena sesungguhnya kamu tak akan mampu mengukur
kekuasaan-Nya. Dengan kata lain, dzat tuhan itu sulit
dijangkau dengan pikiran manusia yang serba terbatas. Alam
semesta inilah yang merepresentasikan kekuasaan-Nya. Alam
ciptaan-Nya inilah mediasi pikiran manusia untuk terus dan
terus merenungkan hakikat keberadaan-Nya. Makanya kita tak
patut mengganggap diri kita sebagai orang yang memiliki
keyakinan yang paling benar, karena ilmu kita hanya setetes
air di lautan, sebutir pasir di padang pasir, sepatah kata
dalam triliunan teks. Kita harus senantiasa menjaga dan
merendahkan hati.
Uraian
ini akan semakin jelas jika kita mau membaca buku Aqidah
Empat Imam: Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin
Hambal yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais
(2003) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari versi
aslinya berjudul I’tiqad al-A’immah al-Arba’ah
dan diterbitkan oleh Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi
Arabia di Jakarta. Ungkapan agnostistik tentang eksistensi
Allah dapat dengan mudah kita temukan dalam buku tersebut,
misalnya pada halaman 12, 14, 15, dan 59-62. Tatkala Imam
Syafi’i menegaskan makna Surah Al-Baqarah: 163-164 dengan
menyatakan, “Jadikanlah makhluk itu sebagai bukti atas
kekuasaan Allah, dan janganlah kamu memaksa-maksa diri untuk
mengetahui hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh akalmu”
jelas ini adalah penyataan yang bersifat agnostistik.
Jadi
agnostistik itu bukan anti tuhan melainkan bentuk pemahaman
terhadap fenomena keberadaan Tuhan yang kompleks karena tuhan
adalah realitas yang berada di luar jangkauan akal, jangkauan
kata-kata, dan abadi dalam kegaiban yang misterius. Agnostik
itu sama sekali tak sama dengan atheis. Pengertian
agnostik dalam konteks agama juga beda dengan yang dalam
konteks sastra.
Dalam
konteks hermeneutik teks sastra, pengertian agnostisisme dapat
kita baca dalam buku Semiotics and Thematics in
Hermeneutics karya T.K. Seung (1982: 3). Dalam buku itu
dinyatakan bahwa agnostisisme tekstual menempatkan teks secara
empatik di luar jangkauan kesadaran subyektif pembacanya. Oleh
karena itu, salah tafsir merupakan keniscayaan yang tak
terelakkan. Agnostisisme tekstual, dalam konteks ini, sering
dipertentangkan dengan solipsisme tekstual yang mengakui
eksistensi teks hanya berada dalam kesadaran subyektif dan
tidak mengakui adanya kemungkinan salah tafsir. Keduanya punya
dilemanya masing-masing.
Akhirnya,
saya ingin mengingatkan bahwa teks surealistik bukan semata
dan selalu berada dalam ranah teks sastra. Ketika Anda
menyebut diri Anda sebagai Rain Fajar, mahasiswa angkatan 2002
di PBSID FKIP Unlam, maka sebenarnya Anda sedang berpikir dan
bertindak surealistik dan agnostistik karena siapa pun yang
mencari nama itu di daftar mahasiswa PBSID FKIP pada angkatan
tahun itu tidak akan menemukannya. Karena nama itu adalah nama
samaran dari seseorang yang tidak ingin diketahui, ingin
bersembunyi, akhirnya menjadi gaib, jadi misterius. Anda ada
tetapi tidak ada. Nama itu tak dapat membantu pembacanya
menemukan realitas atau referensi Rain Fajar.
Jadi,
tulisan siapapun yang ditulis dengan menyamarkan nama adalah
tulisan agnostistik dan surealistik. Fiksi dan fakta bercampur
sehingga realitas faktual tulisan itu sebagian menjadi kabur.
Nama faktual dan nama samaran tak pernah benar-benar menjadi
sinonim yang absolut. Ada aroma split personality di
dalam penyamaran itu karena ketika diri sendiri ingin
mengaktualisasikan diri, sang diri pertama dibebani perasaan
tertentu untuk tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan ingin
menjadi diri yang lain, diri kedua, dengan memilih nama lain
sebagai representasi diri yang pertama.
Nama
samaran yang misterius itu bersama tulisannya menjadi satu
kesatuan agnostistik: ada sekaligus tidak ada. Jadi, sebagai
bagian dari sistem komunikasi dua arah yang tak sepenuhnya
bersifat sama, maka apa yang ditanggapi di sini bisa juga
berada dalam kondisi yang kabur itu: bisa sampai sekaligus
tidak sampai karena hakikat tulisan yang ingin direspons
tulisan ini berada dalam konotasi dan denotasi. Realitas Rain
Fajar tak terjamah: Apa gendernya? Tunggal atau jamak? Serius
atau iseng? Apa agamanya karena nama Fajar bisa saja dijadikan
nama oleh kelompok agama apa saja (Misalnya, Putu Fajar Arcana
itu Hindu, meski Fajar atau Fajri bisa berasosiasi dengan nama
Islam)? Apakah kata “Rain” dalam namanya berarti Timur
atau Barat? Nah, inilah yang dimaksud dengan realitas agnostik
yang kecil-kecilan.
Kalau
sastrawan yang menyamarkan diri, itu wajar karena sastra
identik dengan dunia agnostistik dalam pengertian dunia yang
diciptakannya di atas teks itu ada sekaligus tidak ada dan
sebaliknya, dan seterusnya. Kenyataan semacam inilah yang
sering dimaksud dengan sastra sebagai the possible world
atau dunia yang mungkin: mungkin ada, mungkin pula tidak ada.
Dengan kata lain, realitas sastra serba tak tentu. Tetapi,
kalau orang bersifat agnostistik dengan menyamarkan nama di
atas teks yang bersifat referensial dan denotatif itu berarti
apa? Bagi saya itu berarti naif. Entah sengaja atau tidak,
Anda dan teks Anda saling bersekutu dan masuk wilayah liminal
pertemuan antara denotatif dan konotasi sehingga terciptalah
surealisme di wilayah yang tidak seharusnya demikian alias
surealisme solipsis yang penuh dilema.
Last
but not least, jangan
tergesa-gesa mengharamkan sesuatu. Sempatkanlah baca buku As-Sunnah
An-Nabawiyyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadist karya
Syaikh Muhammad Al-Ghazali (1989) yang diterjemahkan dan
diterbitkan oleh Penerbit Mizan dengan judul Studi Kritis
Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual
(cetakan I, 1991). Pada halaman 89 dia menunjukkan Surah
Al-An’am: 119 yang menyatakan, “Dan sesungguhnya Ia
(Allah) telah merinci apa saja yang diharamkan-Nya atas kamu.”
Dengan demikian, menurutnya, hukum asal segala sesuatu adalah mubah
(tidak terlarang). Tidak ada pengharaman sesuatu kecuali
dengan nash. Bahkan di halaman berikutnya (hlm. 90),
dia mengingatkan bahwa penetapan suatu hukum agama tidak boleh
dilakukan berdasarkan dugaan semata-mata. Adakah nash-nash
yang sangat meyakinkan untuk melarang penggunaan nama malaikat,
setan, nabi, surga, neraka dalam puisi, cerpen, atau novel?
Waspadalah, waspadalah!
|