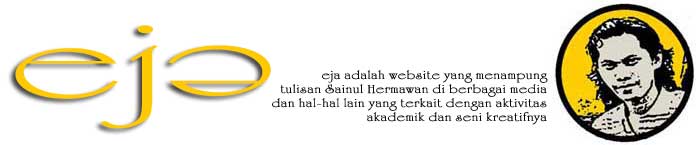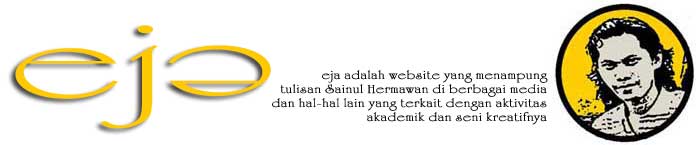Ketika
Tionghoa Angkat Bicara
Oleh
Moh. Yamin
(Pemerhati
Sosial-Pendidikan
&
Pegiat Perbukuan FKIP Unisma Malang)
Judul
: Tionghoa dalam Sastra Indonesia
Penulis
: Sainul Hermawan
Penerbit
: IRCiSoD
Terbitan
: September 2005
Tebal
: 180 Halaman
Membincang
bangsa Indonesia sama dengan mengulas ragam etnis di negeri
ini. Masyarakat Tionghoa sebagai entitas dari sebuah komunitas
kecil di bumi pertiwi ini menjadi satu menu perbincangan
hangat dan menarik dari buku yang ditulis oleh Sainul Hermawan
ini dengan berpijak pada novel Cau-Ba-Kau (CBK) karya Remi
Sylado. Pendapat umum mengatakan bahwa komunitas Tionghoa
merupakan satu kelompok manusia yang hadir bersama kediriannya
untuk menetapkan diri selaku segolongan orang yang bermartabat,
superior, berdaulat, memiliki kebebasan penuh terhadap
nasibnya sendiri, tanpa adanya intervensi pihak luar, tidak
pernah mau diperintah melainkan memerintah, dan seterusnya.
Mereka adalah satu umat manusia kecil di negeri ini yang,
secara tegas, tampil sebagai bangsa yang mandiri, otonom,
independen, dan memiliki satu prinsip hidup, yakni selalu
menatap arah masa depan, tanpa harus toleh kanan maupun toleh
kiri. Artinya, mereka tak peduli terhadap hal-hal yang ada
sekitarnya selama hal semacam tersebut tidak megganggu langkah
perjalanan hidupnya ke depan. Diakui maupun tidak, Tionghoa,
dalam konteks Indonesia, yang sering lebih dikenal dengan Cina
tak pernah luput dari pandangan miring, liar, buruk, dan jelek
bahwa mereka menginjakkan kakinya di nusantara ini sebagai
bangsa yang eksploitatif, pelit, tidak pernah toleran, tidak
bersolidaritas terhadap orang pribumi asli. Lebih runyam lagi,
mereka suka memeras kepada bangsa manusia yang bukan rasnya.
Oleh sebab itu, menjadi tidak asing lagi apabila mereka dikena
stempel sebagai sosok-sosok manusia yang terkadang bisa
dibilang tidak manusiawi, dan bahkan menyenangi sifat serta
karakter buruk lainnya, seperti menipu, mengadu domba demi
sebuah identitas kemenangan dari kelompok mereka sendiri.
Untuk
itu pula, Sainul lewat buku ini mencoba menyerukan bahwa tidak
semua orang Tionghoa itu adalah bejat, dan tidak bermoral.
Akan tetapi, banyak pula diantara mereka yang juga berhati
nurani, suka menolong, memberikan uluran tangan kepada antar
sesama manusia selaku mahluk ciptaan Tuhan. Selain itu,
Tionghoa juga familiar, populis, memiliki patriotisme tinggi
terhadap sebuah kemerdekaan bangsa dari tangan kolonialisme
dan imperalisme, sebagaimana yang terjadi pada Indonesia di
masa lampau. Diatikan bahwa pada saat negeri ini dalam keadaan
genting, sedang dirongrong kedaulatannya oleh Jepang. Maka,
Tionghoa ikut trelibat dalam proses kemerdekaan bumi pertiwi
ini menuju gerbang yang memerdekakan dan merdeka. Dibuktikan
bahwa tokoh yang diketengah-tuliskan dalam buku ini adalah Tan
Peng Liang. Ia adalah figur representatif dari masyarakat
Tionghoa yang benar-benar berkomitmen dengan begitu maha
hebatnya untuk membebaskan tanah pertiwi ini dari penjajahan
Jepang. Sekali lagi, Tan Peng Liang, kendatipun bukan suku
asli di negeri ini, namun ia dengan sebegitu rela dan
ikhlasnya mengorbankan dan kemudian menyisihkan sebagian besar
hartanya untuk pengadaan amunisi militer Indonesia melawan
Jepang. Disadari maupun tidak, Tang Peng Liang ini berusaha
melakukan counter-attack terhadap satu stigma buruk yang
ditohokkan kepada warga Tinghoa.
Dengan
kata lain, Tan Peng liang, dalam konteks ini, memerankan diri
selaku mahluk bersih dan suci dari komunitas Tinghoa bahwa image
buruk sejenis yang dolontarkan masyarakat itu tidak selalu
benar. Lebih dari itu, ia juga mengajak masyarakat di bumi
nusantara ini untuk melakukan satu refleksi bersama demi
sebuah makna kemanusiaan bahwa Tionghoa bukan lagi warga
masyarakat yang rakus akan sebuah harta kekayaan, yang
selanjutnya selalu merajai lini perekonomian di negeri ini,
suka menghalalkan segala cara demi sebuah keuntungan bisnisnya,
yang bertabiat suap menyuap demi sebuah tujuan final, yakni
keberhasilan dan kemenagan tertentu atas nama kelompok maupun
golongan tertentu. Secara sederhananya,
perbincangan-perbincangan yang kerap mendiskreditkan sekaligus
memojokkan orang-orang Tionghoa ingin digeser dari peredaran
pikiran dan pemikiran di republik ini. Tak kurang dari itu,
upaya ini diselenggarakan dalam tingkat wacana semacam ini
untuk mereduksi dan meminimalisasi sebuah opini publik yang
kurang memberi ruang bagi masyarakat Tionghoa untuk menggarap
satu interaksi sosial yang simbiosis-mutualistik sebagai
bentuk implementasi dari sosial kemasyarakatan humanis.
Dikarenakan muncul wacana meresehkan bahwa mereka tidak pernah
toleran pada masyarakat yang lain. Sehingga menjadi satu
keniscayaan apabila garapan-garapan konstruktif semacam ini
dengan berparadigma humanitas yang bernafaskan humanisme
selalu didendangkan oleh Tang Peng Liang.
Aktivitas
pewacanaan semacam itu oleh Tan Peng Liang tidak hanya
berhenti pada wilayah tersebut an sich. Artinya, ranah
agama dan kebudayaan juga dimasukinya. Dengan perkataan lain
dalam buku ini pula, digambarkan bagaimana Tang Peng Liang
pada saat bersembahyang di Kalenteng sebagai ritual suci
keyakinannya untuk memuja pada Sang Tuhan masih menyempatkan
diri membagi-bagikan uang pada kepada sesama warga Tionghoa
temasuk non-Tinghoa di luar tempat peribadatannya sebagai
bentuk ikatan interrelasi sosial. Lebih dari itu, kegiatan
semacam itu dilakukan untuk menanamkan satu kesan baik di
tengah masyarakat bahwa Tionghoa juga merupakan golongan
masyarakat yang pluralistik, inkulisif, memiliki satu
keyakinan diri demi sebuah terbangunnya masyarakat madani
(civil society) dengan tetap berlandaskan pada nilai hakiki
ketuhanan kemanusiaan. Dengan kata lain, perbuatan baik itu
merupakan sebuah pengejewatahan dari ajaran
theo-anthroposentrisme. Di samping itu, sebagai masyarakat
pendatang di negeri orang, Tionghoa, dalam kaca mata budaya,
juga memiliki komitmen diri untuk selalu mengibarkan satu
ajaran konfusianisme yang antara lain menegaskan satu hidup
kebersamaan di atas rel kebenaran untuk saling memiliki, serta
mengukuhkan sebuah ajaran ekonomi humanis bahwa peradaban
kamanusiaan akan terbangun dengan sangat megahnya selama
mereka menghadirkan diri sebagai sosok-sosok yang berbudaya,
mengutip pendapat Spangler. Selain itu, mereka mengedepankan
sebuah nilai keuntungan baik material maupun immaterial dalam
konteks sama rata sama rasa. Untuk itu, Tionghoa menegaskan
sebuah identitas diri dan kedirian sebagai bagian kecil
masyarakat di negeri ini untuk menggapai sebuah cita-cita yang
ber-humanistic-prospect-oriented. Dengan kata lain,
profit-oriented dan value-oriented yang berasaskan pada
keadilan sosial merupakan tujuan hidup yang hakiki dalam
rangka memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi sebuah
bangsa, seperti Indonesia termasuk bangsa Tionghoa yang
berhuni di pertiwi ini.
Harian
Duta Masyarakat, 12 September 2005.
|