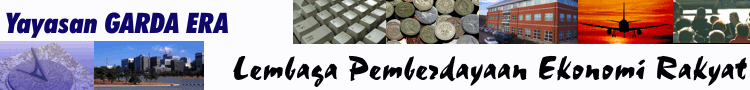|
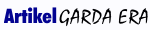
‘Ekonomi
Puasa’ : Makna Religio-Ekonomi Ramadhan
Oleh Muhammad Irfan
Ibadah puasa di bulan Ramadhan, sebagai
suatu bentuk ibadah mahdah (khusus), laksana sebutir mutiara.
Setiap sisinya memancarkan pendar cahaya (spektrum) berdimensi luas
dengan segenap daya pikatnya. Masyarakat tidak lagi hanya mamandang
puasa dari sisi teologis dengan kekayaan kandungan nilai-nilai
spiritualnya. Ia mencakup pula pandangan tentang makna dan manfaat puasa
bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, pembentukan kesadararan hakikat
berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Inilah salahsatu kenyataan
tentang kemenyeluruhan (komprehensivitas) Islam, watak Islam sebagai
agama yang menaungi tiap sisi kehidupan : sistem ekonomi, politik,
sosial dan budaya; material sekaligus spiritual; duniawi dan ukhrawi
; individual dan sosial secara bersamaan.
Dalam kerangka itulah penulis mengajukan terminologi ‘ekonomi puasa’
yang mengacu pada upaya menyingkap makna religio-ekonomi puasa selama
bulan Ramadhan. Karena terdapat gejala-gejala (fenomena) unik yang hanya
terdapat selama pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadhan, yang
berusaha dilihat dari sisi-pandang ekonomi.
Penggalian nilai-nilai ‘ekonomi puasa’ bulan Ramadhan diharapkan
menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Ruh Ramadhan
menghembuskan angin segar bagi pembentukan karakter ekonomi bangsa dan
membangun moralitas pelaku ekonomi secara individual. Hal ini terasa
kian penting karena kerapuhan ekonomi disinyalir kuat bersumber dari
kerapuhan moralitas pelakunya.
Berbelanja Di Jalan Allah
Selama bulan Ramadhan kita dapat mengamati perilaku konsumen dari gejala
perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini dapat disikapi
secara berbeda oleh masing masing individu muslim. Penyikapan muslim
terhadap pola konsumsinya ini dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan,
dengan dampak positif yang semakin besar pada tingkat kedua dan ketiga,
yaitu : pertama, ‘perubahan waktu’. Pada tingkatan ini, puasa
dijalani sebagai kewajiban ritual, dinikmati nuansa spiritualnya,
sedangkan pola konsumsi tidak mengalami perubahan. Pola konsumsi selama
Ramadhan dipahami sebatas ‘pergeseran waktu’ makan dan minum. Dalam
pandangan ini, perilaku konsumsi diluar bulan Ramadhan dari pagi hingga
malam bergeser menjadi antara berbuka dan sahur pada bulan Ramadhan.
Sedangkan kualitas, jenis dan jumlah asupannya relatif tetap bahkan
meningkat.
Kedua, perubahan perilaku. Puasa semakin bermakna manakala setiap pola
konsumsi muslim mampu memenuhi prinsip keseimbangan, halal (sah
secara hukum agama) dan thayyib (barang yang baik dan bersih).
Termasuk didalamnya usaha-usaha yang halal pula dalam memperoleh
pendapatan yang dibelanjakan. Pada tingkatan ini, pola konsumsi
dan penggunaan harta tunduk pada kaidah yang digariskan Allah SWT :
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi” (QS. Al-Baqarah, 2:169).
“Orang-orang yang ketika membelanjakan harta, tidak berebih-lebihan
dan tidak menimbulkan keburukan, tetapi (mempertahankan) keseimbangan
yang adil diantara sikap-sikap yang (ekstrim) tersebut” (QS.
Al-Furqan, 25:67).
Kewajiban memenuhi prinsip keseimbangan atau moderasi (wasathiyah)
sekaligus menunjukkan kecaman ajaran Islam terhadap tindakan pemborosan
(israf) dan pembelanjaan yang mubazir (tabzir) dalam
hidangan berbuka dan sahur, membeli petasan, menyiapkan parcel mewah
untuk pejabat tinggi dan rekanan bisnis, pembelanjaan berlebihan untuk
pakaian, makanan dan dekorasi rumah menjelang lebaran, unjuk diri dengan
mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri (demonstration effect).
Apalagi untuk menyogok (suap atau risywah) dan membeli minuman
keras, narkotika dan zat aditif berbahaya lainnya, usaha perzinaan
berkedok salon, diskotik dan music room, serta segala bentuk perdagangan
pornografi yang telah jelas keharamannya.
Ketiga, perubahan nilai dan paradigma. Selama satu bulan penuh setiap
muslim dilatih untuk mentaati rukun-rukun puasa sebagai perwujudan
ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Setiap muslim, dari terbit fajar
hingga tenggelam matahari, harus menahan makan dan minum dari
barang-barang diperoleh dan dimilikinya sendiri. ‘Nilai dan paradigma
keimanan’ akan mengantarkan kita pada kesadaran terhadap hak
kepemilikan manusia atas harta. Hak kepemilikan manusia bersifat
terbatas dan bersyarat. Allah SWT adalah pemilik sejati segenap faktor
produksi. Dengan kata lain, harta milik manusia merupakan amanat Allah
yang diembankan kepada manusia. Sejalan dengan fungsi manusia sebagai
khalifah di muka bumi (khalifah fil ardh), fungsi perwakilan
untuk mengolah dan memakmurkan bumi. Karenanya, kepemilikan manusia atas
harta harus tunduk pada persyaratan Allah SWT sebagai pemberi amanah,
seperti kewajiban memanfaatkan tanah, mengeluarkan tanggungjawab sosial
dari harta, mewariskannya apabila telah wafat.
Pemberdayaan Kaum Dhuafa
Allah SWT memberikan rangsangan relijius, dorongan spiritual, berupa
pahala yang dilipatgandakan pada setiap amal saleh muslim selama bulan
Ramadhan. Ramadhan menyediakan lingkungan yang subur bagi tumbuhnya
semangat berinfak dan bersedekah di kalangan umat, atas dasar
kesukarelaan. Pada bulan Ramadhan terdapat pula ‘kewajiban khusus’
bagi setiap manusia untuk membayarkan zakat fitrah. Serta adanya
kewajiban membayar fidyah, memberi makan orang miskin oleh orang
yang tidak mampu berpuasa sesuai alasan syariat. Zakat, infak, sedekah,
fidyah merupakan bagian dari instrumentasi (peralatan) kebijakan
ekonomi.
Bulan Ramadhan memberikan makna bagi pencapaian efektifitas
instrumen-instrumen kebijakan ekonomi terutama dalam menyediakan jaring
pengaman sosial, memberikan hak dasar setiap orang untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup minimumnya. Efektifitas kebijakan jaring pengaman sosial
perlu memadukan motif-motif agama dengan kebijakan ekonomi negara.
Dorongan, dukungan, sosialisasi untuk percepatan penerapan UU Nomor 38
Tahun 1999 perlu segera ditindaklanjuti di berbagai daerah, salahsatunya
melalui pembentukan Lembaga Amil (Pengumpul) Zakat yang profesional,
mandiri, dan bertanggungjawab, dari tingkat provinsi hingga ke
kecamatan-kecamatan, bahkan unit-unit kecil perkantoran dan komplek
perumahan. Begitupun kesadaran menyisihkan 2,5 persen penghasilan untuk
zakat, yang akan dipotong pula dari total penghasilan kena pajak.
Disamping penumbuhan, pembinaan, penguatan lembaga mikroekonomi Baitul
Maal wat Tamwil (BMT).
Zakat, infak dan sedekah mengandung makna pemberdayaan. Lembaga Amil
Zakat dituntut kemampuannya mengangkat harkat ekonomi masyarakat dengan
melakukan pembinaan mental untuk membentuk etos kerja muslim dan
pembinaan manajemen usaha agar mustahiq sesegera mungkin berubah
menjadi muzakki.
Dalam Islam, Allah SWT telah menegaskan bahwa zakat bukanlah suatu
bentuk belas kasihan. Zakat memiliki perbedaan penekanan moralitas
dibanding jaminan sosial (charity) di negara-negara penganut ekonomi
kesejahteraan (welfare economy), seperti tunjangan penganggur,
tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan sebagainya di negara-negara
maju. Allah SWT menegaskan zakat, yang bermakna pensucian, merupakan
saluran (mekanisme) yang disediakan Islam untuk menyucikan harta yang
dimiliki oleh orang-orang yang dimampukan secara material oleh Allah
SWT, sehingga mereka menjadi muzakki (orang yang disucikan
hartanya). Pembayaran zakat merupakan pengakuan muzakki terhadap
hak orang-orang yang berhak (mustahiq zakat) atas sebagian harta
yang dimlikinya.
Pembayar zakat bukanlah bentuk kedermawanan individual muslim sehingga
muzakki merasa dirinya lebih tinggi dan mulia karena kekayaannya. Pada
keadaan lain, mustahiq zakat tidaklah patut merasa rendah diri
karena menilai zakat sebagai ungkapan rasa iba orang berpunya terhadap
nasibnya. Zakat menjadi sarana yang disediakan Islam sebagai cerminan
kemauannya untuk memupus individualisme dan egoisme atas kekayaan dan
kemewahan. Zakat sekaligus menjadi bagian dari semesta instrumen
kebijakan bagi pencapaian tatanan sosial yang didasarkan pada prinsip
persamaan, tolong-menolong, dan persaudaraan. Inilah bentuk kongkrit
yang layak-terap (impplementatif) yang ditawarkan Islam untuk mewujudkan
orde sosial yang tertib dan aman karena matinya kecemburuan sosial,
pudurnya angkara kebencian dan pupusnya rasa dendam.
Keseimbangan Makroekonomi
Bulan Ramadhan selalu ditandai dengan kegairahan sektor perdagangan
barang dan jasa. Disamping menjamurnya sektor ekonomi informal yang
dilakoni rakyat kecil, terbentuknya ‘pusat belanja dan jajanan
musiman’ menjadi pemandangan khas yang hanya ditemui bulan Ramadhan.
Secara hipotesis saya dapat menyatakan bahwa sketsa keseimbangan ekonomi
Indonesia tergambar selama bulan Ramadhan. Selama bulan ini,
kecenderungan inflasioner (kenaikan harga-harga) dinilai sebagai
kewajaran. Angka inflasi tak akan mencemaskan perekonomian apabila
meningkatnya sektor moneter (peredaran uang) merupakan konsekuensi yang
menggerakkan sektor riil (perdagangan barang dan jasa). Dengan kata
lain, antara sektor riil dan sektor moneter tumbuh secara beriringan.
Karena itu, Bulan Ramadhan memiliki makna religio-ekonomis bagi
pencapaian keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan makroekonomi yang
tercapai melalui pemenuhan berbagai unsur meliputi : pertama,
pembangunan sektor moneter diarahkan pada penyediaan iklim investasi
yang menggiatkan pembangunan sektor riil. Dengan itu dapat dicapai
keseimbangan ekonomi yang berkembang-berkelanjutan secara nyata (sustainable
economy), bukannya pembangunan semu, melambung tingginya gelembung
sektor moneter (bubble economy) secara sendirian tanpa sektor
riil, yang ditinggalkan jauh dibawah. Keadaan seperti itulah yang
menjadi sumber utama krisis ekonomi sebagaimana pelajaran yang
disampaikan oleh resesi ekonomi Indonesia.
Kedua, memprioritaskan
pengembangan sektor riil yang memproduksi goods (barang-barang)
yang good (baik) yang dibutuhkan sebagian besar rakyat. Good
goods (barang-barang yang baik) sesuai dengan konsepsi Islam
memaknai ar-rizq (rezeki). Dalam terjemahan Al-Quran Yusuf Ali,
dinyatakan bahwa ar-rizq bermakna : “makanan dari Tuhan”,
“Pemberian Tuhan”, “Bekal dari Tuhan”, dan “anugerah-anugerah
dari langit”. Sebagai konsekuensinya, urai Monzer Khaf (1995),
barang-barang konsumsen dalam konsepsi Islam adalah bahan-bahan konsumsi
yang berguna dan baik manfaatnya, yang menimbulkan perbaikan secara
material, moral maupun spiritual bagi konsumennya.
Ketiga, pertumbuhan sektor
moneter dan riil harus diperankan oleh sebagian besar rakyat yang
digerakkan oleh semangat wirausaha yang tinggi dan daya terobos
investasi yang memiliki kebaruan jenis barang dagangan dan jasa.
Integritas Individual
Pelaksanaan kewajiban ibadah puasa merupakan ‘rahasia antara manusia
dengan yang Maha Mengetahui’. Puasa di bulan Ramadhan merupakan ajang
cobaan dan latihan bagi pembentukan integritas individual. Orang yang
berpuasa menunjukkan sifat amanah (bertangungjawab) terhadap berbagai
ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Ia tidak berusaha melanggar
syariatnya walaupun dengan cara rahasia.
Puasa dapat bermakna pada pembentukan integritas individual, kepribadian
muslim yang memiliki kejujuran dan tanggungjawab. Orang yang berpuasa
tidak saja menunjukkan pengakuannya atas kontrol sosial dari
lingkungannya, segan dan malu dengan anak istri, teman sejawat, tetangga
dan masyarakat, yang dapat saja dikelabui dan ditipunya. Lebih dari itu,
keutamaan orang yang berpuasa terletak pada pengakuannya terhadap
pengawasan Allah Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui.
Puasa menunjukkan latihan bagi pelaku ekonomi untuk mentaati berbagai
peraturan dan memenuhi berbagai kewajiban dengan segenap kesadaran. Ia
dapat saja menerjang rambu-rambu moral, melakukan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) namun ia tidak dapat menghindar dari pengawasan Allah
SWT.
Puasa mengkondisikan pelaku ekonomi bekerja secara profesional, baik
sebagai konsumen, produsen dan distributor, penyelenggara pemerintahan,
aparat bea cukai dan sebagainya. Makna profesionalisme diungkapkan dalam
terminologi Islam sebagai ‘ihsan’ . Rasullullah
mendefinisikannya :
“…Ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah SWT seperti kamu
melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya, maka Ia tetap melihatmu….”
(H.R. Muslim, Tirmidzi, dan Nasai)
Rasulullah mengungkapkan pula :
“Sesungguhnya Allah menyukai salah seorang diantara kamu yang
bekerja secara ihsan (profesional)”.
Muslim yang profesional (muhsinin) memenuhi seruan Allah SWT
dalam Surat At-Taubah ayat 105 yang menyatakan :
“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang
beriman akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Sejarah kehidupan kenabian menunjukkan tingginya tingkat produktivitas
kebaikan yang dilakukan selama Ramadhan. Penaklukkan Kota Makkah (fathu
Makkah) terjadi pada tanggal 10 Ramadhan. Perang Badar berlangsung
pada 17 Ramadhan. Muadz bin Jabal diutus berdakwah ke Yaman juga pada
bulan Ramadhan.
Ramadhan dapat dimaknai pula sebagai ajang penempaan kecerdasan
ruhaniah, penajaman kecerdasan spiritual, dan peningkatan kepekaan
emosional muslim. Unsur berharga yang semakin diakui dalam psikologi dan
manajemen sumberdaya manusia, melebihi apa yang dikenal sebelumnya
dengan (hanya mementingkan) kecerdasan intelektual.
Modal Sosial
Perintah berpuasa selama bulan Ramadhan dilakukan secara serentak oleh
muslim di seluruh belahan dunia, telah mengubah watak puasa menjadi
ibadah kolektif (bersama). Ibadah puasa menumbuhkan semangat kebersamaan
bagi keluarga saat sahur dan berbuka atau kebersamaan dengan masyarakat
dan kaum dhuafa. Kebersamaan yang hendak ditumbuhkan Ramadhan tergambar
pula dari berbagai ibadah shalat tarawih dan tadarus qur’an. Mesjid
lebih semarak karena digunakan untuk pengajian dan pesanteren kilat.
Masjid pun disesaki masyarakat yang ingin shalat berjamaah lima waktu.
Puasa mengandung makna kebersamaan untuk turut merasakan derita
kelaparan dan hidup berkekurangan dalam jiwa setiap muslim, sehingga
mendorong tumbuhnya sikap sepenanggungan, berempati, merasakan
kesusahan. Semua itu memungkinkan terjadinya pola interaksi yang acap
dan sehat antar-masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan, yang
seringkali sulit bertemu-muka, berbincang, apalagi berdikusi pada bulan
lainnya.
Mudik ataupun pulang basamo untuk berkumpul bersama keluarga
merayakan Lebaran ataupun ‘pulang kampung’ untuk menikmati Ramadhan
pertama bagi pelajar dan sebagian masyarakat merupakan gejala unik
lainnya di bulan Ramadhan. Ini menunjukkan masih kuatnya ikatan
kekeluargaan dan dihormatinya lembaga keluarga. Sedangkan pada saat
bersamaan di beberapa belahan dunia, lembaga keluarga sudah makin
ditinggalkan. Di Amerika, misalnya, dua dari tiga perkawinan berakhir
dengan perceraian dan sepertiga dari total kelahiranterjadi di luar
pernikahan.
Puasa Ramadhan mengingatkan kembali tentang pentingnya memperhatikan
modal sosial (social capital) sebagai sumberdaya terpenting dalam
menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Bangsa kita memiliki
cadangan modal sosial yang cukup bagi pembangunan. Pencapaian keeratan
(kohesivitas) dan solidaritas sosial merupakan pendidikan terpenting
yang diberikan puasa Ramadhan bagi pembentukan modal sosial.
Kata Akhir
Bulan Ramadhan dinyatakan pula sebagai bulan pembinaan (syahrut
tarbiyah), masa menempa diri untuk melakukan berbagai perbaikan,
masa evaluasi atas berbagai tindakan, masa mengkoreksi dan mengganti
segenap kesalahan dengan kebaikan, masa merencakanan ancang-anacang amal
masa depan, masa peneguhan komitmen terhadap kerja kebaikan. Singkatnya,
masa melakukan perubahan diri untuk mencapai kejayaan. Keberkahan
Ramadhan akan kita rasakan apabila kita mampu menjadikannya momentum
bagi perubahan perilaku ekonomi individual dan kebijakan perekonomian
nasional ke arah perbaikan, menuju cita-citanya yang berkeadaban :
masyarakat yang adil dan makmur. Negeri yang baldatun thayyibatun wa
rabbun ghafur. Wallahu a’lam bisshawab.
Dimuat
harian umum Mimbar Minang secara berseri pada Senin dan Selasa (26-27
Nop 2001).

|