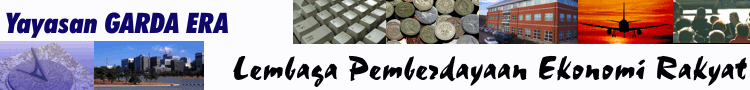|
|
||
|
|
||
|
|
Dampak
Ekonomi HIV/AIDS Pendahuluan
AIDS
dikhawatirkan telah menjadi sebuah epidemi baru di Indonesia.
Kekhawatiran itu rasanya tidaklah terlalu berlebihan, jika merujuk
kepada fakta lapangan yang ada. Data Yayasan Partisipan mengungkapkan
bahwa jumlah pasien HIV/AIDS yang mendaftar ke rumah sakit hingga
Oktober 2003 ini sebanyak 3.925 orang (Republika, 9 Oktober 2003).
Diperkirakan
jumlah penderita yang sebenarnya, yang datanya tidak terekam pada
berbagai sarana pelayanan kesehatan, jauh lebih banyak.
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), di
sejumlah negara di mana tes HIV belum merata dilakukan karena berbagai
sebab maka untuk setiap HIV positif yang terdeteksi berarti di
masyarakat ada 100 orang yang sudah terinfeksi HIV tapi belum
terdeteksi. Inilah yang dikenal dengan fenomena gunung es, bagian
es yang muncul di permukaan air hanyalah sebagian saja dibandingkan
bagian es yang terletak di bawah permukaan air. Jika menggunakan
perhitungan fenomena gunung es ini,
maka jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan hampir
mencapai 400.000 orang pada akhir tahun 2003. Pola
Penyebaran HIV/AIDS Yang
menarik untuk dikaji adalah ternyata
dari jumlah total itu maka lebih
75 % penderita berasal dari kelompok masyarakat produktif yang
berusia dalam rentang 14 - 40 tahun (Data diolah dari Baby Jim Aditya
dot com). Sementara itu, penyebaran jumlah penderita dari hari
kehari juga makin mengkhawatirkan. Jika pada rentang triwulan April-Juni
2003, kenaikan jumlah penderita sebesar 300 orang saja dari triwulan
sebelumnya maka dalam rentang triwulan Juli-September 2003
kenaikannya sebesar 500 orang (pada akhir Juni 2003 jumlah
penderita 3.445 orang). Hal
ini rupanya menunjukkan pola yang sama dengan fakta pada level global.
Pada saat ini saja, sebanyak 6.000 pemuda usia 15 - 24 tahun setiap hari
tertular HIV/AIDS di seluruh dunia atau 1 orang dalam tiap 14 detik.
Secara lebih rinci, saat ini secara global ada 7,3 juta perempuan
muda terinfeksi HIV/AIDS dan 4,5 juta laki-laki muda tertular HIV/AIDS. Nah,
dengan deskripsi kompisisi penderita dan pola penyebaran HIV/AIDS
seperti uraian di atas, terutama besarnya angka penderita pada kelompok
produktif secara ekonomi, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah
bagaimana kira-kira dampak epidemi ini terhadap perekonomian dan
seberapa besar itu ?. Keunikan AIDSSebelum kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu beberapa fakta penting tentang epidemi HIV/AIDS itu sendiri. Para ahli kesehatan sepakat bahwa berdasarkan sifat-sifat dan dampaknya, AIDS tergolong unik (Peter Piot and Per Pinstrup-Andersen, AIDS and Food Security, Reprinted from IFPRI’s 2001-2002 Annual Report). Beberapa keunikan itu, antara lain : Pertama, AIDS membunuh kelompok masyarakat yang paling produktif dan aktif bereproduksi. Kedua, HIV secara sosial tidak terlihat, namun kerusakan yang ditimbulkannya nyata di mana-mana. Sementara itu ketabuan sex dan pola budaya, menyebabkan 90 % para penderitanya tidak terakses oleh pelayanan kesehatan. Hal ini tentu merupakan hambatan besar dalam upaya pencegahan dan pengurangannya Ketiga, HIV memiliki masa inkubasi yang panjang, di mana selama rentang waktu antara masa infeksi sampai timbulnya gejala penyakit, virusnya dapat menyebar. Dengan sifatnya yang tidak terlihat, maka kemungkinan transmisinya akan semakin tinggi. Keempat, HIV/AIDS dapat menyerang berbagai strata demografi dan sosial masyarakat baik pria-wanita, kaya-miskin, desa–kota, dan negara maju-berkembang. Namun jelas bahwa kelompok masyarakat miskinlah yang paling menderita dampaknya. Bagi kelompok masyarakat ini, AIDS memperpanjang dan memperdalam kemiskinan sehingga mereka semakin terjebak di dalamnya. Kelima, dari sisi lain, walaupun HIV dapat menimpa jenis kelamin pria dan wanita, namun dia tidaklah netral gender. Wanita, terutama kelompok usia muda, secara biologis lebih cendrung terkena HIV dibanding pria dalam suatu hubungan seksual Dampak Makroekonomi
Dari keunikannya di atas, epidemi HIV/AIDS kemudian berpretensi kuat untuk mempengaruhi perekonomian melalui beberapa cara; pada level rumah tangga, perusahaan dan negara. Pertama, AIDS mempertinggi angka kematian (mortality) terutama pada kelompok masyarakat yang paling produktif. Dari sisi ini, HIV/AIDS akan memperkecil jumlah populasi dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya hal ini akan merubah struktur populasi dan angkatan kerja sehingga dengan semakin banyaknya tenaga kerja muda belum terdidik memasuki lapangan kerja, tentu akan menurunkan produktivitas. Bagi rumah tangga dengan anggota keluarga yang terkena AIDS, dampak ini akan permanen berupa jebakan kemiskinan. Sementara itu, pada level perusahaan, dengan ekspektasi bahwa AIDS memperlambat pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan merosotnya permintaan konsumsi. Hal ini berarti sebuah peringatan akan melambatnya akses pasar bagi perusahaan yang juga tergantung pada konsumen lokal. Lebih jauh lagi dampak yang meluas terhadap pasar tenaga kerja (melalui penawaran tenaga kerja, produktivitas dan permintaan tenaga kerja) kelihatannya akan mempengaruhi upah dan lapangan kerja. Keduanya bisa menaik atau turun tergantung bagaimana masing-masing variabel berinteraksi. Sementara itu bagi pemerintah, jebakan kemiskinan ini akan mengurangi kemampuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak, sementara di sisi lain terjadi desakan terhadap kenaikan belanja pemerintah untuk berbagai program termasuk di dalamnya program pengurangan kemiskinan tadi. Kedua, infeksi HIV menyebabkan penderitanya menderita sakit (morbidity) lebih sering dan juga mendorong epidemi paralel lainnya seperti TBC (Robert Greener, AIDS and Economics, UNAIDS). Konsekuensinya, peningkatan tingkat kesakitan ini akan memberikan beberapa dampak negatif. Pada level rumah tangga, produktivitas kerja dan penghasilan akan berkurang secara permanen akibat menurunnya jam kerja baik karena sakit maupun pemeliharaan anggota keluarga yang sakit. Di sisi lain, hal ini sementara akan meningkatkan pengeluaran untuk biaya perawatan kesehatan di rumah tangga. Sementara itu perusahaan harus menghadapi kehilangan produktivitas selain juga kenaikan pengeluaran (AIDS Tax) sebagai akibat biaya ekstra untuk training bagi pekerja pengganti serta tunjangan kesehatan oleh perusahaan. Nah, pada akhirnya, bagi pemerintah peningkatan pengeluaran untuk hal-hal di atas tentu akan menguras tabungan atau minimal sebagian dari tambahan pengeluaran akan diambil pendapatan yang seharusnya akan ditabung. Rendahnya tingkat tabungan akan memperburuk iklim investasi karena rendahnya ekspektasi keuntungan atau tingginya ketidakpastian perekonomian dan berkurangnya kemampuan pembiayaan investasi Dengan
menggunakan model ekonometrik dan equilibrium, beberapa penelitian
kemudian menyimpulkan bahwa AIDS memang
akan memberikan dampak negatif terhadap GDP dan GDP perkapita.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti dari
rentang 1992-2001 pada berbagai negara berkembang dengan prevalensi
penderita yang cukup tinggi, di dapat variasi dampak negatif HIV/AIDS
terhadap GDP berada dalam
kisaran 0,6 – 3 %. Kebijakan
Antisipatif Walaupun
data estimasi dampak AIDS terhadap pertumbuhan GDP Indonesia belum
tersedia hingga saat ini, namun diyakini bahwa di masa depan epidemi
HIV/AIDS akan meningkatkan dan memperdalam tingkat kemiskinan
masyarakat.
Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menegaskan bahwa
perkembangan HIV/AIDS sangat tinggi di negara berkembang dibanding
negara maju. Selain
karena masih rendahnya teknologi dan akses pelayanan kesehatan, hal
ini juga terjadi karena paradigma “momok sosial” yang dianut
sebagian besar masyarakat negara berkembang. Mereka masih terus-menerus
melakukan penyangkalan bahwa HIV/AIDS tumbuh subur di kawasannya.
Anggapan bahwa informasi ini akan mencoreng moral masyarakat setempat
dan kekhawatiran industri pariwisata akan hancur dengan informasi ini,
membuat antisipasi HIV/AIDS menjadi minim. Sementara itu`melihat
keunikan dari epidemi ini, maka strategi pengurangan kasus HIV/AIDS
harus dilakukan pemerintah
dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan
berbagai pihak, sumber daya dan manajemen program (untuk
lebih jauh lihat The Three Ones principles pada www.unaids.org).
Kesimpulan
Sementara sebagian orang masih menganggap bahwa HIV/AIDS hanya masalah kesehatan semata, sudah seharusnya dunia menyadari bahwa HIV/AIDS juga menyangkut masalah kesejahteraan manusia, perkembangan sosial-ekonomi, produktivitas, integrasi sosial, dan bahkan keamanan negara. HIV/AIDS bahkan telah menyebar sampai ke sudut-sudut dunia dan mengenai siapa saja, orang tua, anak-anak dan pemuda, pria-wanita, guru dan pekerja kesehatan serta kaya-miskin, Oleh karena itu, sebelum kejadian buruk ini menimpa Indonesia, pengambil keputusan perlu memahami mekanisme engan cara bagaimana HIV/AIDS mempengaruhi perekonomian pada berbagai level dan juga mengestimasi berapa besar dampak itu. Informasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk mendisain kebijakan makroekonomi dan fiskal untuk meringankan dampak terhadap anggaran negara, perusahaan dan rumah tangga. Semoga. Pegiat pada Yayasan
GARDA ERA
|
Link
|