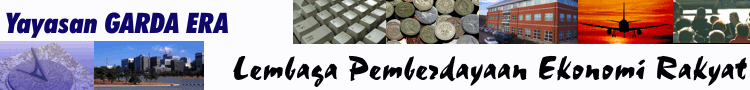|
|
||
|
|
||
|
|
Ujian bagi
Desentralisasi Kesehatan Busung lapar (gizi buruk/KEP) meruyak di NTB. Begitulah berita yang mendominasi media massa nasional, baik cetak maupun audio visual beberapa waktu belakangan. Ironis dan menyedihkan, memang. Tidak ada rasanya kata yang lebih tepat untuk menggambarkan fakta yang ada. Fakta ini menjadi ironi, karena kasus ini justru terjadi di daerah yang menjadi salah satu lumbung pangan (beras) nasional. Menyedihkan, karena temuan ini baru terungkap setelah kondisi para balita penderita sudah sedemikian parahnya, bahkan sudah merenggut sekian jiwa balita yang tak berdosa itu. Apa yang salah ?. Merujuk konsep WHO tentang penyebab KEP (malnutrition), salah satu faktor penyebab lansung (immediate causes) adalah kurangnya asupan makanan bergizi (karbohidrat dan protein) yang diterima balita dalam jangka waktu sekian lama. Balita penderita KEP ini secara umum berasal dari keluarga dengan karakteristik sosial-ekonomi yang rendah yaitu keluarga dengan rendahnya indeks pendidikan, pendapatan dan kebersihan lingkungan dibanding rata-rata masyarakat di sekitarnya (underlying causes). Desentralisasi Kesehatan Fakta ini kemudian menimbulkan kritikan atas peranan pemerintah, terutama pemerintah lokal (local government). Disinilah sebenarnya letak permasalahan. Mulai tahun 2002, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan di bidang kesehatan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuannya, pelimpahan kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja praktisi kesehatan di daerah. Secara umum, pemerintah pusat dengan DPR malah sudah mempersiapkan berbagai perangkat lunak terkait pelaksanaan otonomi daerah ini. Pelimpahan wewenang diatur dalam UU No 22 tahun 1999 dan direvisi lagi dengan UU No. 32 tahun 2004. Sedangkan biaya-biaya yang harus disertakan terkait dengan pelimpahan wewenang tadi diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi dengan UU No. 33 tahun 2004. Lebih detail, Depertemen Kesehatan sebagai regulator malah sudah mempersiapkan berbagai pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) desentralisasi sektor kesehatan ini. Beberapa peraturan dan keputusan itu diantaranya, KepMenkesKesos RI No. 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan KepMenkes RI No. 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah. Dalam pedoman-pedoman tadi diatur beberapa layanan dasar yang harus disediakan rumah sakit dan sarana-sarana kesehatan turunan lainnya di daerah, termasuk di dalamnya tentang pelayanan balita KEP/kurang gizi. Harus diakui bahwa dalam hal penunaian fungsinya sebagai regulator dalam era desentralisasi ini, setidaknya Departemen Kesehatan lebih siap dibandingkan Departemen lainnya. Jika demikian ideal adanya, maka di mana letak titik lemah pelaksanaan desentralisasi kesehatan ini ?. Uraian di bawah ini setidaknya akan membahas 2 (dua) isu utama sebagai kontributor. Kelemahan Pemerintah Lokal Minimnya perhatian pemerintah lokal (provinsi dan kabupaten) terhadap isu-isu preventif dalam bidang kesehatan terutama penyuluhan kesehatan secara berkala dan terus-menerus, bisa dituding sebagai penyebab mendasar (basic causes) dari masalah ini. Pemerintah daerah belum menjadikan kesehatan sebagai prioritas penting dalam pembagunan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. Biasanya alasan klasik ditumpangakn pada keterbatasan anggaran. Apakah alasan minimnya anggaran sehingga perhatian pemerintah daerah lebih dicurahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan PAD, bisa ditolerir ?. Bila ya, hal ini bisa berarti kebijakan desentralisasi telah disalahgunakan hanya sebagai cara untuk meningkatkan beban ekonomi masyarakat tanpa adanya kompensasi berupa pelayanan publik yang lebih baik. Jika demikian adanya, maka desentralisasi dapat menjadi ancaman yang serius terhadap tuuan pembangunan nasional. Padahal seharusnya kesehatan juga menjadi mainstream pembangunan daerah. Kesehatan harus menjadi isu politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran kesehatan seharusnya dilihat sebagai suatu investasi karena kita sudah menekankan pembangunan SDM. Karena investasi, seharusnya penentu kebijakan tidak usah ragu menyediakan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, alokasi anggaran seharusnya benar-benar diutamakan untuk usaha promotif preventif guna menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hal ini setali tiga uang pada level pemerintah pusat. Di Amerika Serikat, isu kesehatan merupakan materi yang selalu diangkat pada kampanye pemilihan presiden. Sementara di negeri tercinta ini, pada pemilu dan pemilihan presiden yang lalu, isu kesehatan sama sekali tidak disinggung. Apalagi pada pemilihan pilkada sekarang. Tak salah bila sebuah adagium mengatakan bahwa sebenarnya masalah kelaparan bukan disebabkan oleh kurangnya makanan, tetapi lebih disebabkan oleh karena faktor kebijakan. Kelemahan Pemerintah Pusat Lebih jauh lagi, terkadang meskipun pemerintah lokal sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap isu-isu ini, namun lemahnya kapasitas aparat dinas terkait daerah masih menjadi masalah utama kesuksesan program. Meskipun kerangka dasar sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun kemudian cerita sukses proses implementasinya sesuai karakteristik daerah sangat bergantung kepada kemampuan daerah itu sendiri. Seperti sebuah contoh kecil, rumusan dasar tentang keluarga miskin saja masih memiliki berbagai tafsiran berbeda di kalangan pelaksana teknis di aderah. Hal ini tentu akan berimbas pula nantinya pada berbagai penentuan strategi dan kebijakan. Simpang-siur dan ketidakjelasan defenisi dan aturan tentang hak masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan dasar menjadikan program subsidi kesehatan tidak berjalan efektif. Sehingga tidak jarang kita mendengar bahwa masyarakat yang seharusnya berhak malah tidak mendapatkan sama sekali. Oleh karenanya, dibalik cerita menggembirakan Depkes dalam mengemban fungsinya regulasinya, maka pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasinya patut dipertanyakan. Peranan pemerintah cq Depkes dalam pembangunan kesehatan sangat sentral. Tugas utama Depkes adalah mendorong peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam kesehatan. Depkes harus lebih berperan sebagai koordinator, dan fasilitator dalam bidang kesehatan ketimbang sebagai implementator atau pemain. Apalagi dengan desentralisasi sekarang ini di mana peranan dinas kesehatan daerah menjadi lebih otonom. Sebagai sebuah saran sederhana, sebaiknya Depkes mulai serius membenahi kembali kapasitas pelaksana teknis di daerah dengan program berkesinambungan dan berjangka panjang dan mulai meninggalkan pendekatan model gebrakan berdurasi pendek berbiaya mahal. Langkah konkrit ini bisa dimulai dengan membekali para ahli gizi di NTB dengan pelatihan know-how penanganan gejala awal gizi buruk dan merevitalisasi posyandu yang masih tersisa. Cukuplah program berskala nasional dengan instruksi pemerintah pusat seperti PIN sampai di sini. Dalam jangka panjang, terlalu mengandalkan pendekatan yang menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek sasaran semata ini akan merugikan usaha pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Memang pada akhirnya keberhasilan pembangunan kesehatan hanya bisa dicapai oleh adanya peran serta aktif masyarakat daerah itu sendiri.
Pegiat
pada Yayasan
GARDA ERA,
|
Link
|