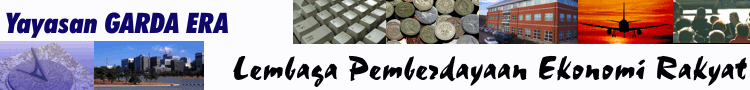|
|
||
|
|
||
|
|
Revitalisasi Posyandu Kemunculan kembali kasus-kasus penyakit menular klasik di tanah air beberapa waktu belakangan telah memicu perdebatan publik tentang politik pembangunan kesehatan nasional. Hal ini terlihat dari komentar beberapa ahli kesehatan terkait dengan maraknya pemberitaan temuan polio, busung lapar dan terakhir campak di beberapa daerah di Indonesia dan respon yang kemudian diambil oleh pemerintah cq Departemen Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatasi kasus polio, Departemen Kesehatan melakukan gebrakan melalui program PIN (Pekan Imunisasi Nasional) gratis yang digelar di 3 propinsi dengan anggaran yang lumayan besar. Kegiatan yang bersifat crash program ini bisa dipahami dan diterima karena adanya desakan waktu sebagai jalan pintas untuk mencapai cakupan imunisasi massive. Namun, di tengah ketatnya alokasi anggaran negara, analisa cost-effectiveness dari PIN dan program-program kesehatan kuratif bersubsidi lainnya menjadi sangat penting untuk dikaji ulang. Penerima Manfaat Sebuah pertanyaan yang harus diajukan adalah sudahkah program ini mencapai hasil seperti yang ditujukan semula ?. Apakah anggaran sudah dialokasikan dengan memenuhi kriteria keadilan dan cost-effectiveness ? Apapun alasan dan berapapun besarannya, penggunaan anggaran ini tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dari sisi ketepatan penerima manfaat (terutama untuk program bersubsidi), luasnya cakupan (coverage level) dan besarnya capaian hasil (policy outcome). Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka tugas pertama yang harus dilakukan oleh praktisi kesehatan adalah memastikan bahwa semua balita dari seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut terutama balita dari keluarga dengan karakteristik sosial-ekonomi yang lebih rendah, telah terjangkau oleh program. Kenapa harus demikian ?. Karena data yang ada menunjukkan bahwa secara umum para balita penderita berbagai kasus penyakit tadi memang berasal dari keluarga yang termasuk kelompok masyarakat dengan indeks pendidikan, pendapatan dan kebersihan lingkungan yang lebih rendah dibanding rata-rata masyarakat di sekitarnya. Amatlah berat bagi kelompok masyarakat ini untuk menanggung biaya yang cukup besar dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan. Pertama, direct cost (biaya lansung) yang harus dikeluarkan oleh konsumen terkait dengan perolehan pelayanan kesehatan. Kedua, opportunity cost yaitu besarnya pertukaran (pengorbanan) yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan utilitas (dalam konteks kesehatan) yang lebih besar dari beberapa pilihan kegiatan yang dilakoninya. Direct Cost Dari pendekatan ini, kalangan ekonom memperkirakan bahwa implementasi dari program-program kesehatan yang diupayakan melalui berbagai bentuk pemberian informasi akan menghasilkan keuntungan-keuntungan eksternalitas. Keuntungan eksternalitas terbesar akan diperoleh oleh ibu-ibu yang berlatar belakang pendidikan rendah dan berasal dari golongan ekonomi lemah (Elfindri, 2001). Rozensweig (1983) dan Schultz (1980) sebelumnya juga telah mengajukan hipotesa bahwa bilamana suatu program pemerintah, seperti program kesehatan dan keluarga berencana diberikan dalam bentuk pemberian informasi dan eksternalities, maka ibu yang berpendidikan rendah dan memiliki akses terbatas terhadap sarana prasarana kesehatan, akan menerima keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi. Sebaliknya, bilamana program kesehatan diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi maka manfaat program kesehatan tersebut lebih banyak diperoleh oleh ibu yang berpendidikan tinggi. Hipotesa demikian dapat dibuktikan mengingat biaya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut secara relatif dianggap nol. Sedangkan sasaran utama dari pemberian tersebut tentu diperuntukkan secara random bagi para ibu balita dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Dengan arti kata segala lapisan sosial-ekonomi rumah tangga pengguna fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat posyandu mendapat kesempatan sama. Opportuniy Cost Selain karena faktor biaya lansung, maka kelompok masyarakat dengan karakteristik sosial-ekonomi lebih rendah tadi seringkali juga dihadapkan pada berbagai pilihan sulit. Di satu sisi, mereka harus memenuhi kebutuhannya akan pelayanan kesehatan. Sementara di sisi lain, kondisi ekonomi yang semakin tidak menguntungkan akibat krisis telah memaksa mereka untuk merobah pola pengeluaran rumah tangga, dengan jalan menciutkan alokasi dana untuk pendidikan dan pemeliharaan kesehatan IFLS (Indonesia Family Live Surveys, 2000) dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari penghasilan (tambahan). Studi awal dampak sosial-ekonomi krisis, menyebutkan bahwa banyak masyarakat dari kelompok ini yang menarik diri dari berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti poskamling dalam bidang keamanan bagi para pria (bapak) dan posyandu dalam bidang kesehatan bagi para wanita (ibu). Dari temuan awal diketahui bahwa banyak para ibu yang terjun aktiv dalam kegiatan ekonomi membantu para bapak untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini kemudian menjadikan sebagian besar kegiatan Posyandu di mana para ibu terlibat sebagai kader maupun peserta, tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Para kader yang selama ini bisa dikatakan bekerja secara sukarela tanpa bayaran tidak lagi aktif. Sementara para peserta semakin jarang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan balita mereka ke Posyandu yang ada. Padahal sesuai dengan analisa penerima manfaat tadi, peranan kader sangatlah vital dalam menyentuh kelompok masyarakat ini, terutama pada daerah-daerah terisolir. Strategi ProgramSelain pertimbangan siapa penerima manfaat terbesar dari program, Dr Firman Lubis MPH (Ketua Dewan Eksekutif Koalisi untuk Indonesia Sehat) dalam tulisannya di HU Kompas, juga mengungkapkan beberapa kelemahan yang terdapat di dalam (inheren) pendekatan model "gebrakan" seperti PIN. Pertama, pendekatan ini lebih didominasi oleh kegiatan seremonial dan publikasi gegap gempita, tetapi kurang serius dalam penanganan teknis detail.Kelemahan lain, kurang bisa mendidik dan menyadarkan masyarakat akan arti dan pentingnya imunisasi bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka mengimunisasikan anak mereka lebih terkesan karena ikut-ikutan atau disuruh oleh aparat desa. Bukan karena merasa sebagai kebutuhan atau mengetahui kegunaannya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan anak-anak mereka. Karena lebih bersifat top down dan kurang dibarengi kegiatan edukasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat, kekurang berhasilan pencapaian cakupan PIN kurang bisa terkompensasi dan tetap terjadi pada kegiatan-kegiatan PIN berikutnya. Akibatnya, cukup banyak anak yang tidak terimunisasi sehingga mudah terinfeksi dan memicu terjadinya KLB polio, seperti yang kita lihat sekarang di Sukabumi, Jawa Barat. Lebih jauh dalam jangka panjang hal ini akan merugikan usaha pembangunan kesehatan secara keseluruhan karena pada akhirnya keberhasilan pembangunan kesehatan hanya bisa dicapai oleh adanya peran serta aktif masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, revitalisasi Posyandu dengan penyediaan beberapa pelayanan minimal seperti konseling, imunisasi dan penimbangan anak mutlak harus dilakukan.
Pegiat
pada Yayasan
GARDA ERA,
|
Link
|