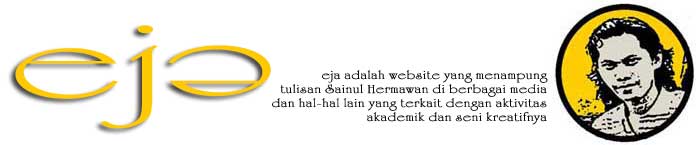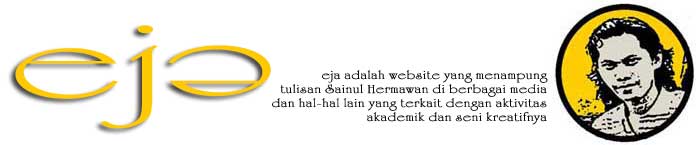|
Hanya
Daun dan Ranting
Cerpen:
Rismiyana
Mereka
duduk bersisian. Kampus sepi. Dingin yang menyertai hujan,
dihantarkan angin sore, menyelusup pori-pori. Dia suka hujan,
teman di sampingnya mengetahui itu.
“Terkadang
aku ingin meyakini bahwa kematian adalah pembebasan, sebagai
akhir kehidupan yang akan membawa pada kekekalan kesunyian dan
keberakhiran dari kesulitan yang kuhadapi.” Dia berkata
sambil mencoba menemukan titik hujan yang membias membentuk
percikan jarum kecil.
“Hanya
saja keyakinan akan adanya hari pembalasan telah mengakar,
mengendap bahkan ketika berada pada batas kewarasan dan
kegilaan sekalipun.”
“Dita,
jangan ngomong seperti itu.” Teman di sampingnya
memandangnya dengan tatapan
prihatin.
“Aku
capek, kalau tidak segera mati aku pasti akan gila…” Dia
menoleh ke samping, menyembunyikan dua titik hujan di pipinya.
“Jangan
menangis, kau membuatku sedih.”
Sesaat
keduanya terdiam, mamandang hujan yang terlihat belum akan
reda
***
Waktu
saat itu menunjukkan pukul lima pagi. Bis yang kutumpangi akan
segera berangkat. Kursi penumpang hampir terisi penuh. Hanya
beberapa saja yang belum ditempati. Mbak Nie duduk di
sampingku, gurat-gurat kelelahan tergambar jelas
di wajahnya. Sehari sebelumnya dia tiba dari Jakarta
untuk memastikan keadaanku. Rapat keluarga yang dipimpin ayah
memutuskan menyetujui kehendakku mengikutinya dan tinggal
bersamanya di Jakarta.
Lima
belas menit kemudian bis penuh. Ayah yang
mengantarku dan Mbak Nie ke terminal, naik ke dalam bis.
Tangannya mengulurkan dua kotak berisi kue untuk sarapan kami.
Mbak Nie kemudian mencium tangannya berpamitan. Aku mengerjakan
hal yang sama, kucium punggung tangan sawo matang kasar yang
mulai keriput itu. Maafkan aku telah mengecewakanmu ayah,
batinku.
“Kembalilah
kalau sudah merasa baikan. Jangan memaksakan diri untuk sekolah
lagi. Bagi ayah, keadaanmu kembali seperti dulu itu sudah cukup.”
Suara ayah terdengar begitu sayu. Saat itu aku seperti tidak
percaya dengan apa yang kulihat. Di kedua sudut mata ayah
kulihat dua mata air mengalir. Sebelumnya aku tak pernah melihat
ayah menangis.
Perjalanan
dalam bis pagi itu adalah perjalanan paling mengerikan yang
pernah aku alami. Bermula ketika bis akan berangkat, kulihat
beberapa orang menaikkan sebuah lemari besar ke atas bis.
Selanjutnya sepanjang perjalanan kudengar suara di belakangku
berbisik. Bahwa lemari itu digunakan untuk mengurungku.
Sementara itu tiga lelaki yang sebelumnya kulihat menaikkan
lemari terus mengawasiku. Aku tahu mereka berencana mengikatku,
mengurungku dalam lemari itu. Sepanjang perjalanan tubuhku
kurasakan gemetar ketakutan.
Semuanya
mungkin berawal sejak lama. Sejak aku suka menyepi di kebun
belakang rumah saat menahan amarah. Kemudian kemarahan itu
menginsfirasiku untuk membakar pohon-pohon di sekelilingku,
mencabutinya, dan melemparkannya ke segala arah. Setelah
amarahku reda aku meninggalkan kebun itu dalam keadaan semula.
Saat
itu aku lebih suka bermain boneka-boneka kayu sendirian dengan
tokoh dan cerita yang kuciptakan sendiri dari pada bermain
dengan kakak-kakakku yang lain. Aku suka menyendiri dengan
buku-buku tentang pembalasan di hari kiamat, buku-buku fiqh, dan
buku kumpulan khutbah jumat milik ayah.
Hingga
sepuluh bulan setelah menginjak bangku SMU. Buku-buku filsafat
dan novel-novel surealis membawa imajinasiku ke dalam ruang aneh.
Terlalu banyak perbenturan nilai. Setiap orang perlu konsep
pasti tentang kebenaran. Dan filsafat menawarkannya hanya saja
ia, menentukan arah nilai itu sesuai selera para pemikirnya.
Menjadi
gila. Dalam novel-novel surealis itu, orang gila tak perlu
tertawa, tak perlu menangis. Tidak perlu pusing dengan kebenaran,
keadilan yang tak ada di sekeliling. Gila yang menenangkan.
Angka-angkalah
yang memberitahuku, bahwa ada yang berubah. Aku yang selalu
juara, lulusan terbaik sekolah, ternyata tak bisa menghitung
angka-angka. Di benakku angka-angka
berserakan tanpa aturan.
Kemudian
aku mulai bermimpi didatangi kecoak raksasa. Kecoak itu ingin
meninjak-injak tubuhku. Setiap malam aku terus bermimpi tentang
kecoak itu, aku dikejar-kejar, berlari, jauh. Akhirnya aku tak
berani memejamkan mata, tapi teror-teror itu tak lagi datang
dalam mimpi. Bermalam-malam selanjutnya aku merasa rumah
dikepung, bisikan-bisikan terdengar di balik dinding kamarku.
Mereka ingin menangkapku, mereka ingin memasungku.
Hanya
aku yang merasakan teror-teror itu. Orang lain tidak. Mereka
hanya melihatku gemetar ketakutan sepanjang malam. Mondar-mandir
di dalam rumah, mengintip orang-orang lewat di pintu kaca
sepanjang siang. Untunglah Mbak Nie segera datang, ingin tahu
keadaanku. Dia menawarkan dua
pilihan; RSJ atau terapi psikiater. Aku memilih yang
kedua dan meminta ikut tinggal bersamanya di Jakarta.
Selama
dua bulan Mbak Nie rutin membawaku ke psikiater. Pil-pil
penenang kuning lonjong, bulat putih, dan bulat mungil biru, 3
kali sehari harus kukonsumsi. Nasihat Mbak Psikiater itu terus
terngiang ditelingaku. Akan tetapi niatku tidak berubah bahwa
aku ke Jakarta, tinggal bersama Mbak Nie adalah agar aku bisa
diam-diam mati.
Sebenarnya
sebelum ke Jakarta aku suidah berniat mati. Hanya, sisa-sisa
kesadaranku masih menyimpan ingatan bahwa memutuskan mati dengan
sengaja karena putus asa letaknya abadi di neraka. Itu tidak
kuinginkan. Bukankah sejak kecil, selesai membaca buku-buku
khutbah Jumat milik ayah aku selalu berdoa untuk mendapat khusnul
khotimah.
Namun,
keadaan terus berubah. Aku lelah. Seseorang yang berada di bawah
bayang kegilaan sepertiku mungkin tak berharap apa-apa selain
mati. Ada ketakutan-ketakutan berlebih pada hal tak berdimensi.
Realita, imajinasi campur aduk. Tak ada ilusi, yang ada
halusinasi. Memang obat-obat penenang itu membuat teror-teror
tak datang lagi. Aku bisa tidur tanpa bermimpi. Tapi, masihkah
ada harapan. Aku sudah drop out dari sekolah, orang-orang
yang mengenalku sudah mencapku gila. Jadi, untuk alasan apa aku
terus hidup dalam keadaan sepertin itu?
Tinggal
memilih cara mati. Berlari menabrakkan diri ketengah jalan raya
di samping rumah. Pergi kedekat stasiun yang berjarak 300 M dari
rumah, tempat kakakku biasa berangkat kerja dan berdiri di
relnya menanti lindasan kereta api. Atau menenggak isi kaleng
baygon di lemari. Masih ada satu lagi, memotong urat darah di
nadi.
Sore
itu pisau kecil itu sudah kubersihkan. Aku telah memutuskan
bahwa cara paling praktis untuk mati adalah memotong urat di
nadi. Aku malas keluar rumah menuju jalan raya dan rel kereta
api. Meminum baygon? Tetanggaku dulu gagal bunuh diri karena
racun itu reaksinya lambat. Aku hanya perlu menekan pisau itu
kuat-kuat ke pergelangan tanganku, seperti aku biasa memotong
ikan mas yang sebelumnya sering kulakukan sebelum menggorengnya.
Untuk memastikan ketajaman pisau, kugoreskan telunjuk kiriku
pada mata pisau. Darah!
Pasti
sakit, tapi hanya sebentar. Setelah itu aku akan mati. Tapi..,
benarkah aku pasti akan mati? Bukankah dalam buku khutbah Jumat
milik ayah mengatakan, waktu kematian telah ditentukan di lauhil
mahfudzh. Manusia tidak bisa memajukannya walau sedetik. Aku
bisa mencobanya! Tapi,
bagaimana kalau setelahnya aku tidak mati, belum saatnya mati.
Bukankah aku sudah terlanjur melukai tanganku. Kalau tidak mati
aku pasti akan sakit,diberi obat, dibawa kerumah sakit, dan itu
perlu biaya. Mbak Nie pasti akan membayar biaya itu, sama
seperti ia membayar biaya konsultasi ke psikiater dan menebus
tablet-tablet penenang itu.
Suara
pluit! Kereta api jam lima sudah datang. Mbak Nie tidak ada
dalam kereta itu. Ia belum pulang, kereta api yang dinaikinya
menjelang Isya baru akan sampai. Perlu waktu tiga
jam di perjalanan. Dia pasti capek. Apalagi hari liburnya
digunakan untuk mengurusku. Mengantarku ke rumah sakit,
mengajakku rekreasi. Dia pun sudah mengurus sekolah baru,
seragam dan semua peralatan sekolah sudah dibelikannya untukku.
Pisau yang akan kugunakan itu biasa digunakan Mbak Nie untuk
memotong buah. Buah-buah apel yang dibelikannya untukku menumpuk
di kulkas. Ada yang sudah membusuk. Ah.., Mbak Nie…. Beberapa
kali dia pulang kehujanan, tapi dia masih sempat membelikan mie
ayam panas kesukaanku. Dia terlalu baik. Aku tak ingin apa yang
dia kerjakan untukku sia-sia. Aku tak tega mengecewakannya.
***
“Kamu
beruntung, penderita scizoprenia jarang bisa sembuh.” Vita
menggelengkan kepala, menatap Dita, yang ada didepannya. Cerita
Dita barusan membuatnya takjub. Skizoprenia, ia yakin itu yang
dulu diidap Dita.
“Pantas
saja, dulu setiap
pulang dari kampus kamu sering menceritakan lelaki gondrong yang
di dekat Sabilal itu. Kamu kasihan melihatnya ngomel sendiri.
Eh, tapi .… kamu
benar-benar sudah sembuhkan?” Pertanyaan itu tampak
mengagetkan Dita.
“Empat
tahun pertama setelah memutuskan berhenti terapi dan memilih
tinggal di sini. Aku masih berfikir tentang mati. Aku terbiasa
berfikir tentang kebenaran segala sesuatu secara detail. Tapi,
standar nilainya tidak jelas. Hasil dari perenungan panjangku
membuatku mengakui yang dikatakan Yoshikawa, bahwa semua hanya
dedaunan dan rerantingan, yang tak berarti” Dita berhenti
berkata, menghembuskan napas pelan.
“Namun,
saat keputusasaan menjangkitiku. Seorang teman datang. Ia
menawarkan konsep kebenaran yang memuaskan akal, menentramkan
jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa apa yang kita
jalani dalam hidup ini, tergantung dari jawaban kita atas tiga
pertanyaan mendasar; dari mana asal kita, untuk apa kita hidup,
dan kemana kita setelah mati. Jawaban atas ketiga pertanyaan itu
akan menentukan sudut pandang kita dalam menilai kebenaran.
Dengan metode berfikir rasional, semua pertanyaanku terjawab.
Bahwa semuanya berasal dari ciptaan Allah, hidup untuk beribadah
kepada Allah, dan kelak akan kembali mempertanggungjawabkan
semuanya kepada-Nya.” Dita memejamkan matanya, sambil menarik
nafas dalam-dalam. “Sekarang aku merasa tiap menit, tiap detik
hidup ini begitu berarti.”
Vita
menatap sahabatnya, lama. Agak ragu, dia
tersenyum, penuh makna.***
|