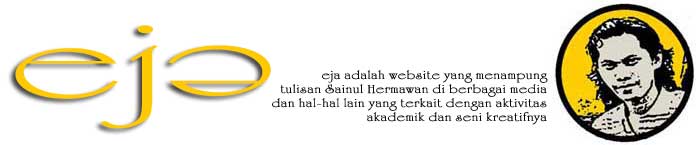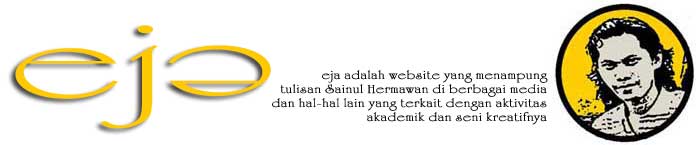|
Dari
Sebuah Rumah Lanting
Cerpen:
Nina Idhiana
Namanya
Yeni. Kanak-kanak usia sekolah. Tak ada yang tahu berapa usia
tepatnya kecuali sang ibu yang pergi meninggalkannya, bahkan
rela mengikat salah satu pergelangan kakinya bak seekor kera
piaraan. Seutas tali yang menghubungkan pergelangan kaki
kirinya dengan salah satu kayu di rumah lanting1)
tanpa atap itu membatasi dunia masa kecil Yeni. Rumah lanting
itulah rumahnya, di mana dulu ayah dan ibu serta
kakak-kakaknya tinggal. Sebelumnya rumah itu beratap, sebelum
para penghuninya memutuskan untuk tidak hidup satu atap lagi.
Kini tinggal Yeni penghuni tunggal rumah mungil terapung itu.
Di sanalah dunianya. Dan dia hanya kenal sungai…sungai…dan
sungai.
***
Orang-orang
kampung memanggilnya Pe’ah. Mungkin nama aslinya Rofi’ah.
Tapi mereka tak peduli, mereka lebih senang menyebutnya begitu.
Lidah orang Banjar kebanyakan manja, tak mau berusaha untuk
mengeja sesuatu yang mereka anggap ribet. Akibatnya,
mereka sulit melapalkan huruf F, R dan Z.
Pe’ah
dan lakinya bukan pengikut KB. Jangankan Keluarga Berencana,
Keluarga Bahagia pun agaknya sulit diwujudkannya. Jauh dari
keluarga sakinah. Lakinya tak punya kerja tetap. Apa saja
dikerjakan asal dapat mengisi perut para anggota keluarganya.
Halal haram tak lagi diperhitungkannya dalam mencari nafkah.
Dengan modal pendidikan enam tahun, pekerjaan yang didapatnya
hanya cukup untuk makan dua kali sehari bagi keluarganya. Ia
tak punya tanah untuk membangun rumah tinggal. Berpedoman pada
pepatah “tak ada rotan, akar pun jadi”, mereka pun
beranggapan “tak ada tanah, sungai pun jadi”. Mereka
merakit sebuah rumah lanting di pinggiran sungai Martapura di
kawasan Banjarmasin Tengah yang ditambatkan di beberapa tunggul2)
di tepi dalam sungai. Bila air pasang, rumah mereka berada di
tepi. Sebaliknya bila air sungai surut, rumah mereka jadi jauh
dari darat alias lebih ke tengah sungai. Kalau dipikir-pikir
lucu juga, mereka jadi sulit menentukan alamat rumahnya
sendiri.
Di
tengah keadaan seperti itulah Yeni lahir. Entah sudah berapa
banyak kakaknya. Saat Yeni mulai tumbuh, Pe’ah, ibu Yeni,
mulai menyadari keterbelakangan mental anak bungsunya itu.
Rupanya malang berulang datang bertandang lagi di keluarga itu.
Laki Pe’ah memutuskan untuk berpoligami. “Haha…”,
Pe’ah hanya bisa tertawa getir dalam hati. Haha… sekali
lagi haha… Seorang pekerja tidak tetap yang lebih condong
kepada pengangguran tidak kentara seperti dia mana bisa
menafkahi dua istri sekaligus. Omong kosong! Padahal syarat
utama poligami harus adil. Adil dalam memenuhi kebutuhan lahir
dan juga batin. Sudah jelas alasan laki Pe’ah untuk berbini
dua bukan untuk alasan ibadah. Ini makin jelas setelah si laki
jadi berbini baru. Ia tak pernah lagi pulang ke rumah. Selama
berhari-hari istri tua dan anak-anaknya menunggu, selama
berminggu-minggu mereka menunggu, sampai berbulan-bulan mereka
menunggu, hingga kejenuhan hinggap di mata, pikiran, dan hati
mereka yang sudah terlalu lelah untuk menyetiai sang kepala
rumah tangga yang nyatanya tak setia pada mereka.
Perasaan
bosan dan tidak sanggup menjadi single parent membuat
Pe’ah nekat menjual anak bungsunya. Pilihannya dikarenakan
hasrat untuk mendapat uang dan mengurangi beban hidup. Yeni
satu-satunya anak yang tak bisa diandalkan baginya.
Saudara-saudara Yeni yang lain bisa disuruh bekerja. Sedangkan
Yeni, bersikap normal saja sulit. Kerjanya hanya diam. Tak
jarang ia bicara dan tertawa sendiri. Ia punya dunia lain yang
baginya tak berbatas ruang dan waktu. Pe’ah malu dan sedih
tak bisa mengobati putrinya. Dengan menjual anaknya setidaknya
ia ingin hidup lebih baik. Namun, sang calon pembeli tak mau
membeli Yeni lantaran penampilannya yang tak menarik. Kulit
hitam terpanggang, dekil, berantakan dan hal lain yang ada
pada Yeni tak membuat sang pembeli rela merogoh kocek untuk
membelinya. Akhirnya Pe’ah meninggalkan Yeni di jalanan. Ya,
dia membuang putri bungsunya! Untunglah salah seorang saudara
Pe’ah tak sengaja bertemu Yeni. Pria itu membawa Yeni
kembali pada Pe’ah.
Pe’ah
frustasi. Ia akhirnya menikah dengan seorang lelaki.
Perceraiannya dengan pendamping terdahulu memang tak pernah
diresmikan baik secara agama maupun hukum. Begitulah. Pada
keluarga dengan tingkat sosial semacam keluarga Pe’ah, tak
perlu adanya surat-surat cerai, apalagi gugat-menggugat dan
berebut hak perwalian anak serta harta gonogini seperti para
selebritis kita yang sedang terkena demam pisah ranjang dan
cerai. Masalah hidup saja sudah bikin pusing tujuh keliling.
Dalam perceraian Pe’ah tak ada kata talak maupun surat cerai.
Mereka berpisah. Bila mereka bertemu lagi, terserah mereka mau
saling beranggapan mantan istri dan mantan suami atau tidak.
Yang pasti mereka sama-sama sudah punya keluarga baru.
Laki
baru Pe’ah tak menyukai Yeni. Ia tak mau menerima Yeni dalam
keluarganya. Demi kehidupan yang diharap Pe’ah lebih baik,
ia meninggalkan Yeni di rumah lamanya. Kaki Yeni diikat dalam
rumah beruang tunggal di sungai itu agar tak ke mana-mana.
Pe’ah sadar, dengan keterbelakangan mental Yeni, bukan tidak
mungkin dia akan menyelam lama dalam air lalu mati, atau
berenang sejauh-jauhnya sampai ke laut dan menjadi manusia
ikan seperti dalam dongeng “Deni Manusia Ikan”. Entah
pemasungan itu lebih dikarenakan keegoisan Pe’ah untuk
menempuh hidup baru atau rasa sayangnya yang tersembunyi
kepada Yeni, yang jelas orang-orang di sekitar tempat
tinggalnya mencap Pe’ah sebagai ibu yang kejam.
Mengetahui
hal itu, paman Yeni yang beberapa waktu lalu mengembalikan
Yeni pada Pe’ah, mengusulkan agar Yeni dititipkan di panti
asuhan agar tak terlantar. Rupanya keluarga sang paman pun
keberatan untuk mengangkat Yeni jadi anak. Paman Yeni
mendatangi panti asuhan yang dimaksud dan mengutarakan
maksudnya pada pihak panti. “ Inya mun behera bepadah
lah?3),” kata pihak panti. “Kada, pang4),”
jawab paman Yeni. Dan pihak panti asuhan pun menolak untuk
menerima Yeni. Kasihan Yeni. Banyak orang mengibainya, namun
banyak juga yang tak menginginkannya. Akhirnya sang paman
setuju untuk membiarkan Pe’ah memasung Yeni dalam rumah.
Awalnya hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Namun,
saat rumah lanting itu mulai lapuk dan kemudian roboh, maka
terbukalah jelas pemandangan mengharukan itu bagi setiap orang
yang lewat di sungai tersebut. Para tetangga ramai
memperbincangkan kisah Yeni. Tak jarang orang-orang di kelotok5)
singgah sebentar untuk memberi Yeni makanan, bahkan kerap
melemparkan baju kaos kepadanya. Mereka saling bertanya-tanya
tentang Yeni, tentang kisahnya. Namun Yeni tetap terbuang,
terkucilkan. Ia tak mau memakai pakaian, ia telanjang. Banyak
yang mengira Yeni anak lelaki, seperti prasangkaku pada awal
melihatnya.
Yeni
anak asuhan alam, dingin dirasa tiap malam. Bila petang mulai
bersetubuh dengan kelam, ia sering terlihat bicara sendiri,
seperti ada teman yang tak terlihat seorang pun kecuali Yeni
sendiri. Entah pada siapa ia bicara. Pada Bulan, pada sungai,
pada angin malam, pada kayu dan tunggul-tungul, atau
pada temannya di alam yang ia ciptakan sendiri. Yeni tak
kesepian, hanya kulitnya yang kian legam yang membuatnya
terlihat memilukan.
***
Pe’ah
duduk menggendong seorang bayi mungil seraya menghitung
receh-receh yang dikumpulkannya sedari pagi tadi. Kemudian ia
menengadah mencari matahari sore yang jingga berkilau sendu. Ia
sekadar ingin mencari tahu pukul berapa sekarang. Setelah ia
yakin bahwa sudah cukup sore untuk mengakhiri pergulatannya
dengan hari, segeralah dipanggilnya beberapa anaknya yang tak
jauh darinya. Si sulung masih asyik menyanyikan lagu “Pudar”-nya
Rossa secara asal-asalan pada seorang bapak yang menunggu lampu
hijau menyala agar dapat melajukan mobilnya. Si bapak cuek.
Sekali lagi Pe’ah memanggil si sulung. Si sulung datang. “Sadikit
haja ma’ ai kolehan hari ini! Sarik bisa abah, ma’ lah!6),”
ujarnya. “Kada papa kalu, nak ai! Mama kolehan banyak hari
ini, nah!7),” jawab Pe’ah. Mereka lalu pulang
ke rumahnya. Di rumah, sang kepala rumah tangga sedang duduk
santai menikmati secangkir kopi pahit sambil menunggu kedatangan
istri dan anak-anak tirinya yang akan membawa banyak receh
untuknya.
***
Sore
itu indah namun terlalu pilu untuk mengingat kisah gadis dalam
pasungan itu. Aku duduk di bangku tepi sungai sambil
memandangnya. Ia melemparkan senyum ajaibnya. Seorang lelaki
berpakaian rapi datang dan duduk di sebelahku. “Coba kalau dia
mau pake baju, aku mau bawa dia ke Jakarta buat jadi anak
angkatku. Kasian, ya, Nin!”, ujarnya. “Heh? Iya…”,
jawabku pendek. Pria itu cuma satu dari sekian banyak yang
berlagak ingin merawatnya tapi cuma bisa diam dan diam. Asal
bunyi! Lebih baik diam kalau tak ada bukti.***
Guntung
Payung, 17 Juli 2005
Nina
Indhiana
Baru
saja tamat dari SMA Negeri 1 Banjarbaru
Catatan:
1)
: rumah terapung
2)
: kayu atau
tonggak yang terpancang di tanah
3)
: apa dia
bilang, kalau mau buang air besar?
4)
: nggak, sih!
5)
: perahu
bermesin
6)
: cuma
sedikit pendapatan hari ini, bu! Mungkin ayah marah, ya bu!
7)
: mungkin
nggak apa-apa, nak! Ibu dapat banyak hari ini.
|