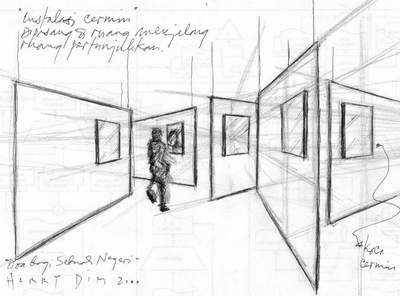eksotika
dotkom
Eksotika
dotkom menangkap gambaran manusia dalam suatu jaringan relasi
persoalan, tentu saja, eksotika dotkom adalah juga soal yang
diturunkan dari penanda semacam "http://www.eksotika.com".
Agus Suwage, seniman yang sering melibatkan gambaran dirinya
jadi bagian persoalan karyanya, menarik kita pada situasi penyangsian,
di situ, gambaran potret diri memang bisa dilihat sebagai 'identitas',
tapi sesungguhnya adalah persoalan 'identifikasi'.
Agus Suwage memang tidak pernah jera menggambar(kan) dirinya
sendiri, atau membenturkan perkara personalnya pada wilayah
diskusi bersama, makanya, ihwal wilayah ini jadi perkara sensitif,
di masa kini, wilayah/tempat itu jadi (seolah) tak berbatas
dan hanya dihidupi oleh gairah 'percepatan' (waktu), dan proyek
eksotika dotkom coba menantang itu.
(Rizky A. Zaelani, kurator)

turmoilisrockingmycountry
(gonjangganjingnegeriku) acrylic on canvas, (9) X 145 X 286
cm, 1998 - 2000
Perjalanan
Herry Dim
Menembus Kemarahan
Oleh : I. Bambang
Sugiharto
Diantara
sekian lukisan Herry Dim yang langsung menyergap sensasi visual
tentunya adalah rangkaian gambar besar berjudul “gonjangganjingnegeriku”.
Lukisan “gonjangganjingnegeriku”
bukanlah serangkaian baliho. Kalau pun kita menganggapnya baliho,
ia adalah baliho yang mengecoh. Gambar-gambar raksasa pada latar
depan barangkali mesti dilihat justru sebagai latar belakang.
Sedang kotak-kotak semiotis kecil pada bagian atas tiap bilahnya
agaknya mesti dilihat sebagai latar depan.
Saya melihat focus sesungguhnya terletak di sana : pada
kotak-kotak yang senyap itu, bukan pada hingar-bingar besar
sekelilingnya. Bentuk berbagai figur dengan sapuan besar dan
kasar dalam kanvas-kanvas raksasa itu memang tampak seperti
potret yang verbal dan wantah dari situasi krisis Indonesia
di masa peralihan tempohari. Pelukisan yang nyaris sangat harfiah
itu sekilas membuatnya tak lebih dari poster jalanan dari kaum
pergerakan atau grafiti kemarahan bersimbah darah pada dinding-dinding
kota dari para vandalis.
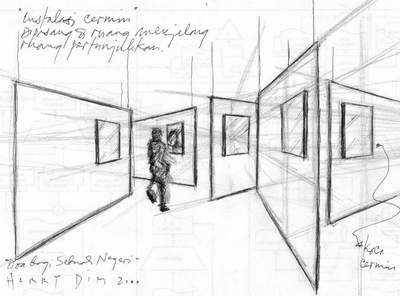
Coretan sketsa Herry Dim untuk karya
"Instalasi Labirin"
, Galeri Nasional,
Jakarta, Agustus 2000 |
Tapi
tentu bukanlah Herry Dim bila hanya berhenti di situ. Ada proses
emosional menarik yang telah melahirkan karya-karya itu. Tapi
juga kesan itu bisa menjadi lain bila semua kita tarik ke arah
figur-figur kecil pada tiap kotak di setiap bilah kanvas itu.
Lukisan-lukisan itu lahir dari kekecewaan, bukan hanya atas
situasi kemelut Indonesia, tapi terutama atas ketidakhadiran
si pelukis sendiri di saat kemelut itu berkobar membakar negerinya
(saat itu ia sedang berada di luar negeri). Format besar kanvas,
karenanya, memberinya semacam sense of involvement, rasa
keterlibatan pada realitas yang lebih besar. Dan kenyataan bahwa
tiap kali ia melanjutkan proses melukisnya persis saat matahari
berada di atas ubun-ubunnya -yang membuatnya terpanggang sinar
matahari selama proses itu- membuat seluruh proses melukis itu
bagai sebuah ritual aneh : barangkali semacam proses meledakkan
kemarahan, merajam diri dengan rasa bersalah yang tak jelas,
serentak menyiangi jaringan kemelut batin itu, merenungi tiap
buhul jaringan tersebut, yang lantas bermuara pada bentuk ikon-ikon
mungil pada tiap kotak kecil di tengah hiruk pikuk gambar besar
itu.

Coretan sketsa Herry Dim untuk karya kola-
borasinya, "Doa bagi Sebuah
Negeri ", bersa-
ma seniman lain, Galeri Nasional, Jakarta,
Agustus 2000 |
Ikon-ikon
kecil seperti mulut, korek-api, tangan mengepal, batu, wajah
Ninja, dsb., itu seperti setiap kali tiba-tiba membekukan gerak
gejolak pada tiap bilah, membuat kita tersentak dan berhenti
sejenak, keluar dari fenomen lalu barang sekelebat melongok
essensi-essensi dari tiap gejolak.
Menarik, juga oleh sebab ikon-ikon itu digarap dengan teknik
berbeda : drawing yang halus dan intens, berlawanan dengan
sapuan-sapuan kuas sekelilingnya yang liar dan kasar. Dan umumnya
ikon-ikon itu pun hitam putih saja, kontras dengan sekelilingnya
yang penuh warna : seperti ajakan masuk sesaat ke dalam kesenyapan
di antara gemuruh teriakan, atau seperti jendela-jendela essensi
yang ditemukan setelah menerobos kabut kemelut emosi.
Yang lebih menarik lagi adalah bahwa pada ikon daun sirih, lalu
cabe, bawang putih dan bawang daun, mulai ada warna lain, tidak
lagi hitam putih. Sepertinya di situ perenungan sampai pada
sejenis optimisme baru?
Dan bila dilihat bahwa daun sirih maupun cabe atau bawang adalah
unsur-unsur dalam ritual tradisional untuk menolak bala, maka
dengan itu ada isyarat bahwa perjalanan Herry Dim menembus amarah
akhirnya seperti sampai pada tataran misteri, dan karenanya
lantas masuk ke wilayah transendental : wilayah dimana perkara
sosial-politik menunjuk lebih jauh pada naluri-naluri terdalam
terhadap kejahatan dan kebaikan, kematian dan kehidupan; naluri
yang akhirnya tak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan.
Agaknya wilayah ritual transendental ini pulalah yang umumnya
bergema pada lukisan-lukisan lainnya. Hal lain yang menarik
dari lukisan “gonjangganjingnegeriku”
adalah sosok perempuan penari yang ada di bagian bawah tiap
bilah kanvas itu. Dengan cepat ia seperti menunjuk pada konsepsi
“ibu pertiwi”, yang sedang menangis. Tapi sosok perempuan macam
itu sebetulnya kerap muncul dalam lukisan Herry Dim yang lain
juga, sedemikian hingga ia nyaris menggantikan fungsi identitasnya
pribadi.

Karya cukil kayu,
"Mulut-mulut & Lampu
15 Wat" , 2000
|
Adakah
ini berkaitan pula dengan kesukaannya meletakkan topeng pada
lukisan-lukisannya? Tak jelas memang. Yang jelas Herry jenis
manusia yang tak suka berkaca (dalam arti harfiah). Barangkali
ada keterkaitan antara itu semua, namun tak mudah memang untuk
menjelaskannya. Sepertinya figur ibu bukanlah hanya figur bumi
atau ibu-pertiwi, ia serentak bagian dari identitas psikologis,
sosiologis, bahkan kosmis, Herry Dim sendiri.
Perjalanan penjelajahan bentuk Herry Dim sebetulnya cukup panjang
. Sekurang-kurangnya ada masanya ia berkubang dalam pola surrealisme,
lantas sempat pula mengeksplorasi motif-motif etnis, garis bentuk
kanak-kanak, teknik-teknik grafis, dsb. Menarik bahwa setelah
itu, pada moment-moment pengalaman emosional tinggi,
ia sepertinya menemukan intensitasnya justru pada bentuk-bentuk
natural, pada sosok-sosok kekonkritan : daun sebagai daun, batu
dalam rupa batu, dsb. Rupanyaintensitas dan sublimitas pengalaman
tak mesti identik dengan keabstrakan. Bisa sebaliknya.***
Ngawawaas
Setiawan Sabana
sebagai Urang Sunda
Sebuah Refleksi Budaya
Oleh
Tjetjep Rohendi Rohidi

Gerbang Alam, etsa aquatint,
37 X 41 cm, 1984.* |
Saya
merasa tersanjung dan sekaligus juga tertantang ketika diminta
oleh Setiawan Sabana untuk memberi pengantar terhadap salah
satu kegiatannya, yaitu pameran (grafis) tunggalnya yang bertajuk
“waas”.
Sekalipun demikian, saya tidak akan membicarakan kiprahnya semata-mata
di bidang seni grafts, melainkan rnencoba melihat sosok Setiawan
Sabana dalam konteks kehidupan budayanya secara lebih utuh.
Dengan sengaja dalam tulisan pengantar ini saya menempatkan
dan melihat Setiawan Sabana sebagai "urang Sunda” --serta
kegiatan pribadi dan profesionalnya sebagai sasaran pembahasan,
katakanlah semacam objek ontologis dan ke kerangka epistemologisnya.
Kemudian, saya mencoba memahami dan memberikan penjelasan mengenainya
sesuai dengan bidang saga (antropologi); dan oleh karena
itu, saya sebut saja tulisan ini sebagai refleksi budaya; sebuah
kegiatan ngawawaas (mengikuti pilihan kata waas
untuk pameran grafisnya ini),
**
Setelah suatu rentang pengalaman hidup --peristiwa jasmaniah
dan rokhaniah, waktu, dan batas-batas lokalitas lainnya-- terlampaui,
apakah yang wajar dan seharusnya dilakukan oleh seseorang yang
memiliki kesadaran budaya?
Setiawan Sabana, sejenak dengan renungan yang dalam, memilih
untuk merefleksi diri masa lalunya; ia tidak sekadar menoleh,
tetapi merenungkan seluruh rentang pengalaman hidupnya, melibatkan
emosinya untuk berempati, menghayati proses perjalanan dirinya,
tetapi sekaligus juga sadar bahwa ia sudah tidak berada lagi
di tempat itu,
Setiawan Sabana memilih kata (kecap Sunda) "waas" , yang
secara harfiah berarti terkenang kepada yang pernah dialami,
untuk suasana dirinya saat ini ketika melihat seluruh pengalaman
hidupnya itu. Kata "waas" sengaja dipilihnya karena dipandangnya
merupakan kata, yang memuat makna budaya yang tepat dan mendalam
tentang suasana diri yang dialaminya saat ini.
Pilihan kata ini saya anggap sebagai pilihan budaya--dengan
pengetahuan dan kesadaran--sebagai urang Sunda.
Setiawan Sabana lahir di Bandung 49 tahun yang lalu (10 Mei
1951). Keluarganya berasal (Sunda, bibit buit) dari salah
satu desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dilihat dari asal-usulnya
dan lingkungannya, cukup jelas untuk menegaskan bahwa Setiawan
Sabana adalah asli urang Sunda (Sunda, pituin);
ia telah mendapat proses enkulturasi kebudayaan Sunda dengan
lancar. Perhatikan pula nama yang disandangnya, yang diberikan
orang tuanya, atau panggilan akrab sehari-harinya; "Wawan",
yang sangat kental dengan cita rasa vokal khas dalam bahasa
Sunda.
Sejak kecil Setiawan Sabana sekolah di Bandung di sekolah-sekolah
terpandang yang memungkinkannya untuk menyerap pendidikan modern
dengan baik, yang memupuk dirinya menjadi lebih terbuka, dinamis,
tingkat pergaulan yang lebih luas, dan minat kegiatan yang cukup
beragam (salah satu di antaranya adalah kegiatan olah raga tenis
meja).
Kota Bandung, sebagai wilayah perkotaan, dengan aneka ragam
kegiatan dan masyarakatnya menjadi lingkungan yang menantang
dalam perkembangan hidupnya. Studinya di Jurusan Seni Murni,
Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB (tamat 1977) dan dari Art
Department, Northern Illinois University, USA dan lingkungan
pergaulan di dalamnya, telah menggiringnya ke arah pencapaian
intelektualisme yang rasional.
Pada saatnya, ketika dan. sepulangnya dari studinya, pemikiran
rasionalnya sangat mendominasi perilaku dan kegiatannya dan
konsekuensinya menjaga jarak dengan asal-usul tradisinya. Barangkali
dalam kondisi seperti itulah beberapa karya grafisnya lahir
dalam rentangan waktu yang cukup lama. Pergulatan hidup, tantangan
zaman, dan nilai-nilai lama, yang menjadi acuan hidup Setiawan
Sabana tampaknya terus bergulir seirama dengan bertambahnya
usia, kematangan, memori primordial, dan tentu saja religiusitas
yang menjadi obor spiritualitasnya.
Pada saat seperti inilah Setiawan Sabana merefleksi perjalanan
hidupnya. Ia mulai meneropong masa lalunya, bukan hanya kecenderungan
berpikir rasionalnya, melainkan juga melihat nilai-nilai tradisinya
dengan pandangan baru, keharuan baru, dan keterpesonaan baru.
Seperti halnya pentahapan karakter budaya pada diri seorang
manusia, yaitu ada kalanya proses imitasi sangat kuat melekat
untuk setiap ekspresi seseorang, kemudian tiba pula saat memberontak
terhadap nilai-nilai lama yang dianggapnya sudah usang dan harus
diganti dengan nilai-nilai baru yang dianggapnya lebih relevan
dan signifikan untuk menghadapi keadaan dan masa yang akan datang;
akhirnya akan tiba pula saat kemapanan yaitu tahap meyakini
bahwa nilai-nilai yang dimilikinya dianggap sebagai nilai utama
yang harus dilestarikan, karena dalam rentang perjalanan kehidupannya
telah terbukti ampuh untuk memahami berbagai masalah yang dihadapi.
Setiawan Sabana tampaknya telah melalui proses itu, dan sampai
pada satu titik rentang perjalanan untuk melihat dirinya dan
sekeliling dirinya dengan jernih, sambil menentukan di mana
ia harus berdiri dalam kehidupannya sekarang dengan lebih arif.
Pada titik ini, sebagaimana saya mengenalnya dengan cukup baik,
Setiawan Sabana melihat masa lalunya dan mengenangnya (dengan
rasa waas) dengan seluruh potensi kemanusiaannya yang tidak
semata-mata rasional, tetapi seluruh penghayatan yang mencakup
emosi, cita rasa, moral, dan keyakinannya.
Ia mulai melihat persoalan dengan kesadaran budaya yang utuh.
Dari sinilah saya melihat bahwa Setiawan Sabana secara jelas
telah menempatkan dirinya sebagai urang Sunda (Sunda,
geus nyunda ayeuna mah!). Artinya, sekalipun ia memiliki
pengalaman lintas batas lokalitas yang bersifat jasmaniah (melanglangbuana
dalam berbagai kegiatan studi dan pamerannya) dan rokhaniah
(kewajiban religius dan perambahan ilmu pengetahuannya), ia
kini menghayati keseluruhannya itu dalam konteks kesundaannya.
Sebaliknya, sebagai urang Sunda ia juga menjadi urang Sunda
yang modern. Saya kira untuk hal ini kita bisa melihat kiprahnya
saat ini; ia bekerja secara profesial dan melakukan berbagai
aktivitasnya dalam lingkup kerja dan kegiatan yang tergolong
modern.
Barangkali, di sinilah relevansi dan signifikansi saya ketika
ngawawaas Setiawan Sabana, perjalanan hidup, dan aneka
ragam kegiatannya.
Setiawan Sabana, berjalan menempuh hidupnya mengalir begitu
saja (Sunda. kumaha loyogna bae), dengan kemampuan adaptasinya
terhadap berbagai perubahan dan persoalan yang dihadapi, serta
kemampuan untuk menciptakan alternatif-alternatif dalam kehidupannya
sambil juga menyadari hasil keseluruhan sebagai sesuatu yang
menjadi suratan hidup (Sunda. kumaha nu “Dibendo” bae).
Bukankah ini semua, secara tidak langsung, merupakan pencerminan
dari karakter budaya urang Sunda. Dengan demikian, ketika
menikmati karya-karya grafis Setiawan Sabana yang dipamerkannya
kali ini seyogianya dipahami dalam konteks perkembangannya pada
masanya dan barangkali ada baiknya juga untuk menghayatinya
sebagaimana Setiawan Sabana melakukannya saat ini, yaitu dalam
kegiatan yang disertai rasa waas, untuk merefleksi perjalanan
hidup kita sendiri. Selamat berpameran, dan tentu saja masih
banyak jalan yang harus ditempuh.*
Bandung, 20 Oktober
2000 Dengan salam dari: Tjetjep Rohendi Rohidi