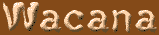
|
Editorial
|
Menutup Abad
Gelap
Oleh:
Herry Dim
|
Selamat
pagi pak, selamat pagi bu, ucap anak sekolah
dengan sapaan palsu. Lalu merekapun belajar
sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah
mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka
yang palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah
mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru
untuk menyerahkan amplop berisi perhatian
dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu
dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya pak guru
dan bu guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu
untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan
nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah
demi masa sekolah berlalu, merekapun lahir
sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu,
ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian
menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu. Dengan gairah
tinggi
mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu
dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu. Mereka saksikan
ramainya perniagaan palsu dengan ekspor
dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan
berbagai barang kelontong kualitas palsu.
Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus
dan hadiah-hadiah palsu tapi diam-diam meminjam juga
pinjaman dengan ijin dan surat palsu. Masyarakat pun berniaga
dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka
uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu
sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis
yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam
nasib buruk palsu. Lalu orang-orang palsu
meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan
gagasan-gagasan palsu di tengah seminar
dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya
demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring
dan palsu.
(Agus R. Sarjono, Sajak Palsu,
1998)
|
Sajak
di atas, sungguh sebuah sajak yang mencerminkan realitas kita
kemarin dan sisanya masih terasa hari ini. Sebuah sajak yang
memperlihatkan kejujuran penyairnya dalam memotret dan mengungkapkan
realitas kita saat ini, di sini, di sebuah negeri yang bernama
Indonesia; sekaligus sajak itu berbayang sensibilitas sastrawai
serta kecerdasan penyairnya. Sebuah sajak yang lahir dan menjadi
saksi zaman. Sejajar dengan ini patut pula bagi siapapun warga
negeri ini untuk menyingkap sajak "Malu Aku Jadi Orang Indonesia"
karya Taufiq Ismail atau "Kesaksian Akhir Abad" karya Rendra.
Itulah kenyataan kita kemarin di masa kekuasaan Orde Baru dan
sisanya masih berakar kuat hingga saat ini. Sekarang akar-akar
"keji" yang merusak segala sendi kemanusiaan itu sedang kita
bongkar, dengan harapan bisa tumbuh benih-benih baru yang betul-betul
berpihak kepada kebenaran, keadilan, menghormati wacana azasi
kemanusiaan.
Kehidupan kemarin yang masih berbayang, itu bisa kita sebut
sebagai kehidupan maya, kehidupan yang seolah-olah, kehidupan
yang penuh kepalsuan, dan bahkan penuh tipu-muslihat. Bisa kita
lihat, misalnya, seolah-olah perekonomian kita ini pernah mengalami
pertumbuhan sebesar 7% per tahun, mengalami swa-sembada beras,
bahkan suatu saat pernah memberikan bantuan pangan bagi warga
masyarakat Ethiopia. Atau dalam bentuknya yang lebih kasat-mata,
bisa kita lihat begitu luar biasanya gedung-gedung menjulang
di Jakarta, mobil-mobil mewah dan kemewahan lainnya berkelebatan
di hadapan kita.
Tapi apakah benar semua itu bisa di-klaim sebagai "kita" yang
artinya di belakang kata "kita" itu adalah 200.000.000 manusia?
Maka keseolah-olahan itu pun segera tampak jelas. Segala kemewahan
dan "pertumbuhan yang konon" itu hanyalah dikuasai oleh segelintir
orang saja. Sama sekali jauh dari "kita" yang berjumlah tak
kurang dari 200.000.000 orang.
Bahkan, lebih jauh lagi, jika benda-benda itu dikumpulkan seluruhnya
lantas diuangkan, maka semuanya tak akan cukup pula untuk membayar
seluruh utang atas nama negara yang bernama Republik Indonesia
ini. Semakin jelas pula bahwa benda-benda gemerlap itu, sesungguhnya
tak pernah dan bukanlah milik kita. Semua hanyalah benda-benda
maya yang seolah-olah ada di tengah kehidupan kita.
Wajarlah kalau kemudian Papua minta pisah, karena yang ada di
sana adalah hal-hal yang sebaliknya yaitu berupa kemiskinan
dan keterbelakangan, demikian halnya saudara-saudara kita di
Aceh yang relatif tak mengenyam pertumbuhan itu kecuali pemerasan
bahkan berbagai penindasan.
Dan sesungguhnya pula, perlilaku masa kekuasaan Orba itu sifatnya
merata diderita oleh mayoritas yang berada di dalam kata "kita."
Kemiskinan yang terjadi di Papua, tak jauh bedanya dengan saudara-saudara
kita yang nyelip-nyelip di lobang-lobang tikus pinggir
gedung menjulang di Jakarta dan kota-kota lainnya, tak beda
dengan saudara-saudara kita yang hidup di pedesaan dikelilingi
pesawahan subur tapi tiba-tiba kesulitan mendapatkan beras karena
sawah-sawah itu ternyata milik segelintir orang tadi.
Pun pembantaian yang terjadi di Aceh pada dasarnya mendapatkan
analoginya dalam bentuk pembantaian "akal pikiran" dan dimensi
kecerdasan manusia. Dalam konteks melihat dunia yang seolah-olah
ini, tentu dengan tetap menyatakan bahwa pembantaian nyawa manusia
itu adalah kekejian yang biadab; tapi mari kita baca pula bahwa
pembantaian "akal pikiran" dan dimensi kecerdasan manusia itu
pun adalah sama kejinya. Moral dan kepercayaan diri sebuah generasi,
misalnya, bisa hancur lebur dan tumbuh menjadi drakula-drakula
atau zombie-zombie yang sangat mengerikan.
Mari kita bermain logika yang amat sangat sederhana, sambil
diingat pula bahwa yang berikut ini adalah satu contoh saja
dan terdapat sederet panjang contoh lainnya bila dikehendaki.
Begini: Suatu ketika karena anak presiden, maka mereka dengan
"sim salabim" bisa menjadi pengusaha yang luar biasa besar,
memimpin berbagai organisasi penting, bahkan menjadi menteri.
Kualifikasi kecerdasan apa yang saat itu diberlakukan?
Segera kita tahu dan bahkan saat itu pun telah tersadari bahwa
satu-satunya logika yang dipakai adalah "kekuasaan."
Apa akibatnya dalam konteks logika sederhana tadi?
Maka tak kurang dari dua generasi runtuh kepercayaannya kepada
dunia ilmu dan pendidikan. "Ngapain sekolah susah-susah, tokh,
yang dapet dia-dia juga," itu pernah menjadi wacana awam. Di
balik itu, virus "maling" dan merebut kekuasaan dengan sendirinya
menyelusup ke benak orang per orang. "Di negeri ini yang penting
bukan menjadi orang pandai, tapi harus pinter-pinter ngatur
strategi agar sampai di suatu pucuk kekuasaan, setelah sampai
di sana maka apapun bisa diatur," itu wacana umum lainnya yang
menyimpan kata "strategi" itu sebagai akal-akalan, muslihat,
persekongkolan membangun kekuatan untuk kekuasaan; dan ujung-ujungnya
meski tak berbentuk langsung pembunuhan tapi pada dasarnya membunuh
harkat kemanusiaan, akal sehat, kecerdasan, fasistis, menindas
yang lain yang lebih lemah, serta sudah pasti: serakah!.
Loyalitasnya yang tumbuh dalam dimensi "kekuasaan" seperti itu,
maka bukan kepada kemanusiaan tapi loyalitas kepada sekongkolnya.
Itu bahkan tercermin sekarang pada euforia pembuatan
partai dan kelanjutan tindak-tanduknya, misalnya, orientasinya
tidak kepada rakyat dan kemanusiaannya secara menyeluruh, melainkan
perjuangan untuk massa partainya, bahkan hanya untuk pribadi-pribadinya
saja dengan memanfaatkan massa partainya.
Kata apa lagi yang paling tepat untuk itu selain kata kanibalistik.
Dan kita tahu, kanibalistik itu adalah perilaku manusia yang
purba dan sepurbawi-purbawinya.
Itulah dunia kita kemarin dan saat in.
Maka
kemerdekaan yang selalu diperingati setiap 17 Agustus itu pun
sesungguhnya merupakan kemerdekaan yang seolah-olah. Berbagai
hal membuktikan bahwa banyak perilaku penjajahan yang dilakukan
oleh kita sendiri terhadap kita sendiri. Feodalisme tak juga
hengkang melainkan bergeser ke gaya berjas dan berdasi, titel
kesarjanaan, raihan kekayaan, dan tentu saja pangkat ketentaraan,
ketenaran. Di sini pula peradaban kepura-puraan dan hipokrit
dimulai dan tumbuh begitu subur.
Oh, tak hanya ethnic cleansing yang terjadi, tapi di
dini di sebuah negeri bernama Indonesia sudah sampai pada batas
human being cleansing; pembantaian kemanusiaan. Tak ada
lagi kemanusiaan. Itu menjadi pemandangan umum di sebuah negeri
yang dulu disebut bangsa ramah-tamah itu.
Saudara-saudara sekemanusiaan, segeralah kita sadari bahwa kemarin
kira berada di dalam sebuah abad yang begitu gelap. Sebuah abad
ketika kita begitu sulit melihat kebenaran sebagai benar dan
kesalahan sebagai salah.
Abad
baru, abad 21, kini telah tiba. Mari kita niatkan untuk menutup
abad kemarin, abad gelap, dengan niat yang menyeluruh: yaitu
memuliakan kembali harkat kemanusiaan.
Tanpa itu, perpindahan abad hanya akan menjadi perpindahan waktu
yang tak memiliki arti apa-apa. Selamat
datang manusia baru, selamat datang abad baru.***
Cibolerang,
7 November 2000
|
|
|
|
